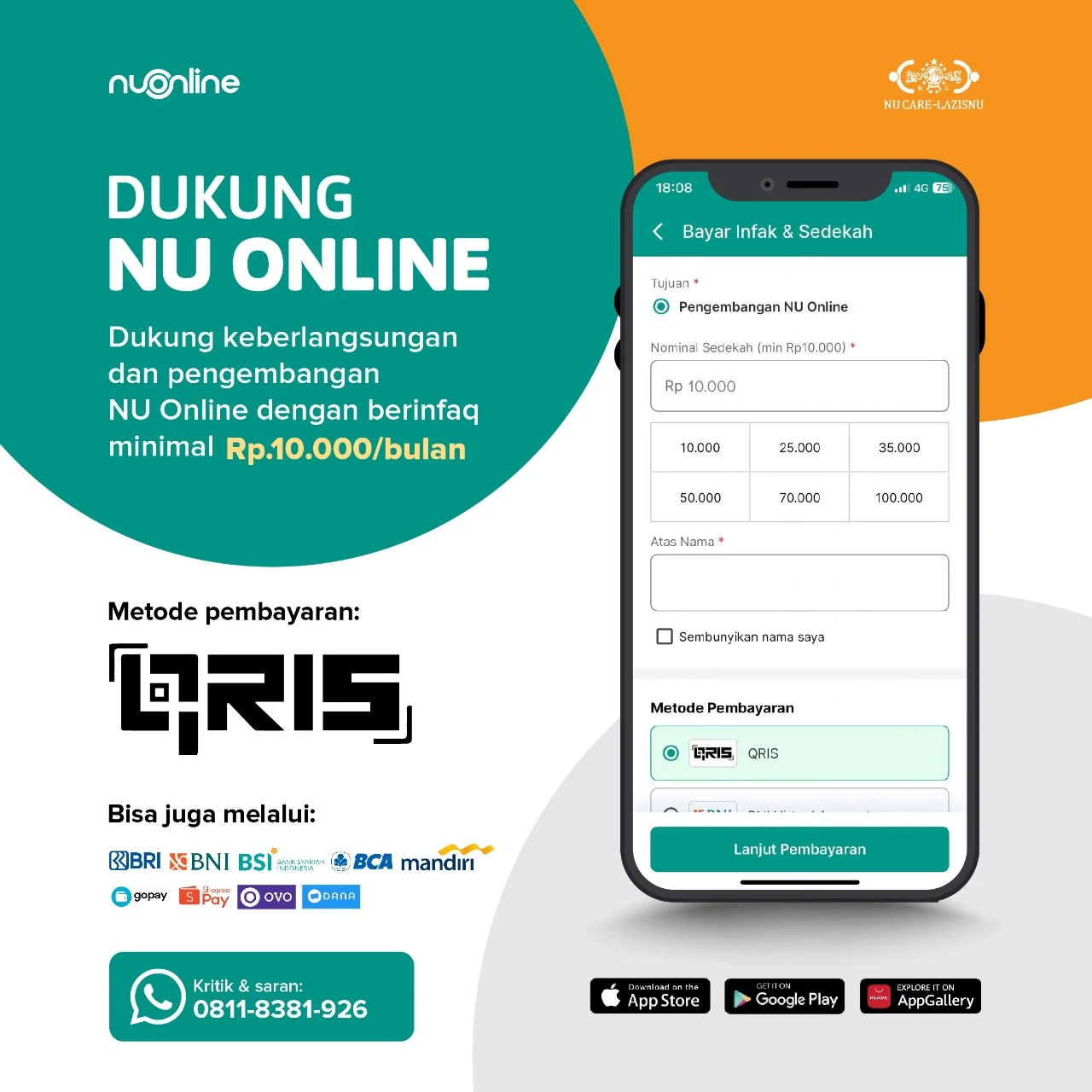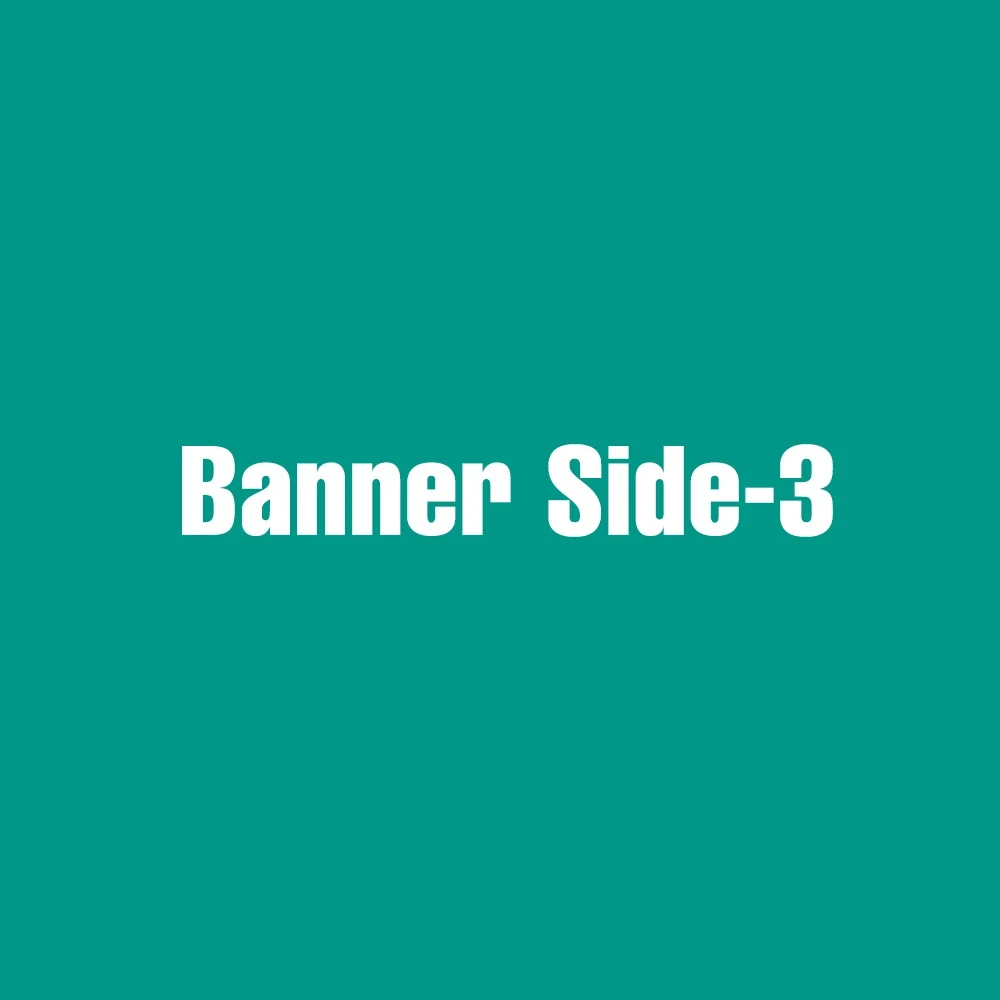Mushaf di Ujung Lidah: Tradisi Membaca Al-Qur’an Manusia Nusantara dalam Kitab Klasik
Selasa, 15 April 2025 | 13:05 WIB
Wahyu Iryana
Penulis
Di bawah langit tropis dan di tengah samudra adat yang kaya, manusia Nusantara merawat Al-Qur’an dengan suara. Ia bukan hanya kitab untuk dibaca, tetapi untuk dihidupkan dalam bunyi, dikidungkan dalam langgam, dan dihayati dalam lidah-lidah para santri dari Aceh hingga Papua. Dan semua itu tak hanya warisan lisan semata. Dalam kitab-kitab klasik beraksara Arab Pegon, Jawi, dan Melayu, terbaca jelas bagaimana manusia Nusantara menempatkan membaca Al-Qur’an sebagai jalan hidup, jalan ilmu, jalan rasa, dan jalan ke langit.
Kitab-kitab klasik (turats) buatan ulama Nusantara adalah cermin zaman yang merekam denyut kehidupan keagamaan. Dalam kitab-kitab tersebut, kita menemukan tak hanya tafsir, tetapi juga etika membaca, adab mengaji, cara melagukan, hingga makna spiritual dari setiap huruf yang dibaca. Tradisi membaca Al-Qur’an di Nusantara bukanlah sekadar aktivitas spiritual, ia telah melebur menjadi kebudayaan.
Membaca sebagai Peradaban
Dalam Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (w. 1812), membaca Al-Qur’an diposisikan sebagai bentuk awal dari peradaban umat Islam di Banjar. Membaca, menurut beliau, adalah gerbang ilmu dan amal. Oleh sebab itu, beliau menulis agar masyarakat memahami hukum-hukum tajwid secara praktis dan etis. Bukan hanya agar bacaan benar, tetapi agar hati turut hadir dalam tiap huruf yang dibaca.
Sementara itu, dalam Hidayatus Salikin karya Syekh Abdus Shamad al-Palimbani (w. 1789), membaca Al-Qur’an dikaitkan dengan perjalanan ruhani. Tiap ayat adalah cermin bagi jiwa. Beliau menekankan bahwa membaca Al-Qur’an bukan hanya untuk menghabiskan waktu luang atau memenuhi target khataman, tapi untuk bercermin. Dalam cermin itu, manusia menemukan dirinya, menemukan Tuhannya.
Kitab-kitab ini memberi kita gambaran bahwa sejak dahulu, manusia Nusantara membaca Al-Qur’an tidak dengan terburu-buru. Ada jeda, ada irama, dan ada kesadaran. Bacaan bukanlah suara semata, melainkan pancaran iman.
Seni Langgam dan Suara
Salah satu ciri khas pembacaan Al-Qur’an di Nusantara adalah langgam. Di Jawa, dikenal langgam Solonese yang merdu dan melankolis. Di Sumatera Barat, ada langgam Minang yang kaya melodi. Di Bugis dan Makassar, pembacaan dilakukan dengan irama khas lokal yang berlapis-lapis.
Dalam kitab Risalah Tajwid yang disusun oleh para ulama pondok pesantren di Jawa Tengah pada abad ke-19, disebutkan bahwa membaca dengan suara yang indah adalah bentuk penghormatan terhadap Al-Qur’an. Bahkan dalam banyak nadzhoman (syair-syair pengajaran agama), anak-anak santri dilatih sejak dini bukan hanya mengeja huruf, tapi juga memperindah suara.
Hal ini berbeda dengan tradisi membaca Barat yang lebih menekankan kecepatan dan teknis. Di Nusantara, membaca itu harus pakai rasa. Maka tidak heran, muncul istilah seperti ngaji rasa, yang artinya membaca dengan perasaan, dengan hati yang halus, bukan hanya dengan lidah.
Dan dalam kitab al-Hidayah fi Tajwid al-Qur’an karya Syekh Mahmud bin Husain dari Cirebon, kita dapati keterangan bagaimana membaca huruf-huruf tertentu harus disesuaikan dengan napas, posisi lidah, dan gerak dada. Seakan-akan tubuh manusia adalah alat musik spiritual untuk melantunkan wahyu.
Mushaf di Tepi Lumbung
Di pedesaan Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi, membaca Al-Qur’an adalah aktivitas harian yang dilakukan di serambi, di langgar, di surau, atau bahkan di tepi sawah dan lumbung. Tradisi ini terekam dalam banyak kitab nadzhoman seperti Syarah Alif Ba Ta atau Nadzhom Qawa’idul Imla’ yang berisi pujian terhadap anak-anak yang rajin mengaji meski hujan turun deras, atau meski lampu teplok hanya tinggal satu nyala.
Tradisi ini memperlihatkan bagaimana manusia Nusantara tidak menjadikan membaca Al-Qur’an sebagai kegiatan eksklusif masjid semata. Ia adalah bagian dari kehidupan harian. Bahkan ada istilah ngaji sambil momong (mengaji sambil menjaga anak), atau ngaji sawah (membaca Al-Qur’an di pondokan sawah sambil menunggu panen).
Di Lampung, saya menemukan manuskrip tua yang ditulis dalam Arab-Lampung Pegon, yang mengajarkan wirid Al-Qur’an harian yang harus dibaca para petani setelah Subuh. Satu halaman ditujukan untuk tiap hari, lengkap dengan doa pembuka dan penutup. Itu menunjukkan bahwa membaca Al-Qur’an tak harus menunggu waktu kosong. Justru, ia menyempurnakan kesibukan.
Santri dan Mushaf: Relasi Sakral
Dalam banyak pondok pesantren, khususnya pesantren tua seperti di Banten, Cirebon, Jombang, hingga Gowa, mushaf Al-Qur’an adalah benda sakral. Ia tidak bisa sembarangan disentuh apalagi dipindahkan. Santri diajarkan untuk menyentuh mushaf dengan hati-hati, bahkan dengan ritual khusus, seperti bersiwak, memakai wewangian, dan membaca doa sebelum menyentuh.
Kitab Adabul Qur’an karya Syekh Nawawi al-Bantani (w. 1897), salah satu ulama besar Nusantara yang juga pengajar di Makkah, menuliskan panjang lebar tentang adab ini. Beliau menulis bahwa menyentuh mushaf itu sama halnya dengan menyentuh hati Rasulullah. Maka harus ada kelembutan. Harus ada cinta.
Santri juga diajarkan bahwa membaca Al-Qur’an tidak bisa dilakukan dalam keadaan emosi atau terburu-buru. Ia harus dilakukan dengan pikiran yang bersih dan hati yang tenang. Bahkan jika sedang marah, maka lebih baik menenangkan diri terlebih dahulu. Ini semua adalah bentuk kesadaran spiritual dalam tradisi membaca Al-Qur’an yang terekam dalam kitab klasik.
Dari Lisan ke Khatam: Jalan Spiritual
Salah satu aspek yang jarang dibahas tetapi sangat penting dalam tradisi membaca Al-Qur’an di Nusantara adalah khataman. Dalam kitab Manhaj al-Tilawah karya ulama Minangkabau abad ke-18, disebutkan bahwa khataman bukan hanya pencapaian, tetapi ritual pembaharuan diri.
Setiap kali seseorang khatam, maka ia diharapkan menjadi pribadi baru. Di beberapa daerah seperti Madura dan Lombok, acara khataman disertai dengan pembacaan doa bersama, selamatan, dan pembacaan kisah Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an bukan hanya dibaca, tetapi dijadikan medium pertautan sosial, spiritual, dan kultural.
Di pesantren-pesantren tua, khataman dilakukan dengan tartil, satu per satu, malam demi malam. Tidak tergesa. Tidak mencari cepat. Bahkan ada yang khatam satu kali dalam dua tahun. Karena tujuannya bukan banyak, tetapi dalam.
Tradisi yang Terancam?
Namun, tradisi ini hari ini menghadapi tantangan. Dalam era digital, membaca Al-Qur’an mulai tergantikan oleh aplikasi dan kecepatan. Banyak yang lebih bangga mengkhatamkan Al-Qur’an dalam satu malam, daripada memahami satu ayat secara perlahan. Dan banyak anak muda yang lebih fasih melafalkan bahasa Korea daripada membaca surah pendek dengan tartil.
Kitab-kitab klasik mulai ditinggalkan. Bahkan, di beberapa pesantren, pelajaran tentang adab membaca Al-Qur’an hanya diberikan sepintas. Padahal, justru di situlah ruhnya. Tanpa adab, bacaan menjadi kosong. Tanpa rasa, suara menjadi gema yang hampa.
Kita perlu kembali membuka kitab-kitab klasik. Bukan karena kita anti-modern, tetapi karena dari sana kita belajar makna terdalam dari membaca. Bahwa membaca itu bukan hanya tindakan fisik, tapi laku spiritual.
Menyulam Kembali Tradisi
Sudah waktunya para pendidik, pengasuh pesantren, guru-guru ngaji, dan para orang tua mulai menanamkan kembali tradisi membaca Al-Qur’an dengan cinta, rasa, dan ilmu. Kita bisa mulai dengan memperkenalkan kembali kitab-kitab klasik seperti Sabilal Muhtadin, Adabul Qur’an, atau bahkan nadzhoman-nadzhoman sederhana yang bisa dinyanyikan bersama anak-anak.
Bukan hal yang mustahil membuat lomba langgam ngaji daerah, atau membuat podcast yang membacakan kitab klasik tentang tajwid. Tradisi itu tak harus kaku. Ia bisa disulam dengan kreativitas zaman kini, asal ruhnya tetap dijaga.
Dan paling penting, mari kita ajarkan bahwa membaca Al-Qur’an bukan soal lulus target, bukan soal lomba suara, tapi tentang menemukan kembali diri kita di tengah dunia yang riuh.
Syair Mahabah Al Qur'an
Kitab-Kitab Tua Itu
Kitab-kitab tua itu
menguning di rak, bersandar pada dinding kayu
ia tak berdebu—sebab di dalamnya
suara para santri masih melagukan huruf-huruf
Mereka tidak membacanya
tetapi mendengarkannya
dari bibir yang patah-patah mengeja
hingga bibir yang purna dalam cinta
Alif di sana bukan angka
tapi tiang yang menyangga langit
dan ba bukan sekadar huruf kedua
tapi benih yang menumbuhkan akhlak
Maka setiap yang membaca
telah menanam: pada dada, pada kata
dan pada senyap yang paling rahasia
di antara huruf dan makna.
H Wahyu Iryana, Sejarawan dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Sejarah Islam Lampung.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Wajib Bahagia Menyambut Maulid Nabi Muhammad Saw
2
Khutbah Jumat: Meneladani Nabi Muhammad di Bulan Rabi‘ul Awal
3
Maulid Nabi 5 September 2025, Ini 5 Alasan Sunnah Merayakannya
4
4 Hikmah Nabi Dilahirkan pada Hari Senin Bulan Rabiul Awal
5
Khutbah Jumat: Merayakan Maulid Nabi, Momen Teladani Akhlak Terpuji
6
PBAK UIN Raden Intan Lampung 2025 Kukuhkan 4.174 Mahasiswa Baru
Terkini
Lihat Semua