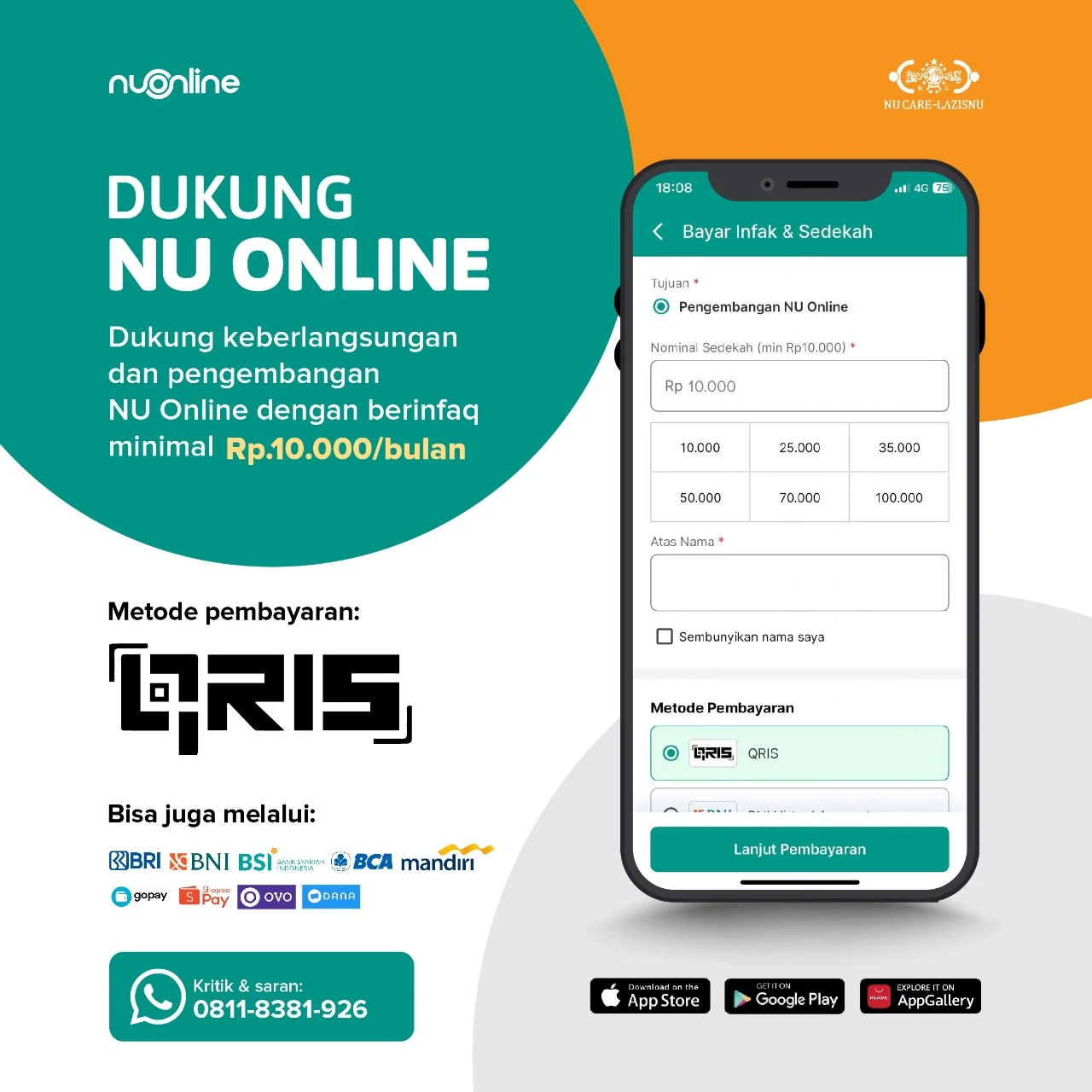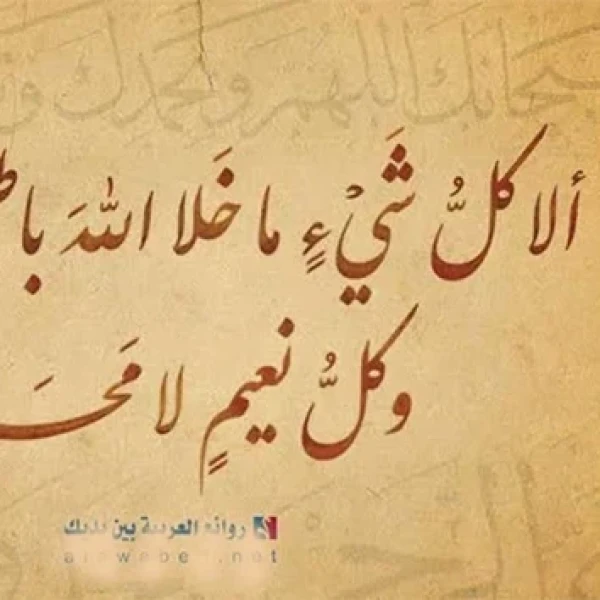Oleh : Yuditeha
Entah mengapa, meski sudah ada keputusan penerimaan santri di pesantren Al-Amin 1 sudah ditiadakan, namun waktu itu saya belum sepenuhnya yakin bahwa pesantren tersebut benar-benar akan ditutup.
Bahkan saya masih ingat, pada saat jam istirahat, tak sengaja saya mendengar pak Amat, salah satu tukang kebun di pesantren Al-Amin 2 ini mengatakan bahwa tanah dan bangunan di mana pesantren Al-Amin 1 berdiri telah dijual pun, saya tetap merasa belum benar-benar percaya.
Karena merasa penasaran, waktu itu saya langsung menghampiri dia yang sedang istirahat dan ngobrol santai bersama tukang kebun lainnya di selasar asrama santri putra.
“Apa kamu yakin, tempat itu dijual?” tanya saya pada pak Amat waktu itu.
Pak Amat terlihat agak terkejut mengetahui kedatangan saya, terlebih ketika mendapat pertanyaan dari saya.
Sesungguhnya saya menyesal telah menanyakan hal itu kepadanya. Pertanyaan saya tadi bisa jadi akan membuat Pak Amat heran, karena saya yakin pastinya Pak Amat menganggap bahwa untuk masalah tersebut sepantasnyalah saya memang sudah mengetahuinya.
Tetapi karena sudah telanjur saya tanyakan, agar tidak membuat Pak Amat semakin heran, saya putuskan untuk menunggu jawabannya. Toh pada kenyataannya waktu itu saya memang belum mengerti kejadian yang sebenarnya, dan tentu saja saya juga ingin tahu.
“Yang saya dengar begitu, Ustadz,” jawabnya.
Ah, mendengar jawaban Pak Amat waktu itu saya langsung merasa bahwa kabar itu membuat kedudukan saya sebagai mudir (kepala pesantren) di pesantren Al-Amin 2 ini seperti dianggap tidak pernah ada, khususnya setelah Kiai Umar meninggal dunia lima tahun yang lalu.
Selama Pesantren Al-Amin masih dipegang Kiai Umar, keadaannya tidak seperti ini. Bahkan semasa kiai masih hidup, sayalah yang cenderung dipercaya untuk mengurusi segala sesuatu tentang pesantren. Meski saya hanya mudir di Al-Amin 2, tetapi untuk jalur komunikasi pertama, beliau lebih memilih saya yang menangani semuanya.
“Maaf Ustadz, bukankah seharusnya Ustadz sudah tahu hal itu?” Pertanyaan Pak Amat membuyarkan lamunan saya.
Persis dengan yang saya pikirkan tadi, Pak Amat merasa heran dengan pertanyaan saya. Jika dipikir-pikir, pertanyaan Pak Amat itu bisa jadi menyinggung perasaan saya. Tapi karena saya menilai apa yang dia tanyakan adalah sesuatu yang masuk akal, dan saya juga menganggap anggapan itu memang sudah selayaknya begitu, akhirnya seperti yang saya sikapkan sebelumnya, tidak saya masukkan ke hati.
Agar tidak membuat keheranan Pak Amat semakin menjadi-jadi saya putuskan untuk memberi jawaban yang sekiranya aman.
“Saya hanya meyakinkan, apakah kabar itu sudah sampai di masyarakat. Eh, ternyata sudah.”
“Benar Ustadz, banyak orang sudah tahu hal itu,” kata Pak Amat. “Gus Udin itu memang keliwat , Ustadz,” sambungnya.
“Ya sudah. Silakan dilanjut istirahatnya. Saya mau ke kantor dulu.”
Saya tidak ingin mendengar bicara Pak Amat melantur ke mana-mana perihal Gus Udin, saya putuskan untuk izin pergi. Membicarakan Gus Khomarudin, begitu nama lengkapnya, memang tidak pernah ada habisnya. Bahkan dari kecil, dia sudah sering menjadi buah bibir di lingkungan pesantren ini, dan yang menjadi topik perbincangan selalu tentang kenakalan-kenakalannya.
Jika mengingat semua itu, saya menjadi tidak habis mengerti, bagaimana bisa, seorang kiai besar seperti Kiai Umar bisa mempunyai anak yang lacugh (nakal). Lebih celakanya lagi, dia ontang-anting di keluarga kiai. Hidupnya hanya sibuk berfoya-foya. Selama ini segala jenis nasihat dan petuah dari siapa pun tak pernah ada yang mempan untuk membuatnya sadar.
Gus Udin dan Kiai Umar ibarat langit dan bumi, bedanya tak terkira. Sebuah ironi yang sering membuat orang yang mengetahuinya bisa geleng-geleng kepala sembari pussau dadou (mengelus dada) karena herannya.
Kiai Umar yang selama hidupnya dikenal sebagai kiai besar, dengan ilmu keimanan yang mumpuni, mempunyai kepribadian yang unggul, dan penderma yang ikhlas, tapi mempunyai putra satu-satunya, yang bernama Khomarudin dengan karakter dan tabiat yang hampir semuanya berkebalikan dengan beliau.
Tetapi yang membuat saya paling heran, Kiai Umar selalu sabar menghadapi kenakalan Gus Udin, seakan-akan beliau tidak pernah menganggap kelakuan Gus Udin adalah hal serius yang perlu ditangani. Kiai Umar terkesan seperti membiarkan saja, bahkan menurut saya beliau malah seperti pejah (membiarkan). Jika Gus Udin meminta sesuatu tidak kakikha (kira-kira), dan kiai tetap memenuhi permintaannya itu.
Mengetahui sikap Abahnya begitu, Gus Udin justru semakin keranjingan dengan permintaan-permintaan selanjutnya. Karena hal itu orang-orang sering ngejaji Gus Udin dengan istilah, diberi hati minta rempela. Meski saya tahu hal itu bukan pernyataan yang tepat, tapi orang-orang sering menganggapnya begitu.
Sebelum Kiai Umar meninggal, sebenarnya saya, juga para ustadz lainnya di pesantren ini sudah memberi pandangan perihal Pesantren Al-Amin kepada kiai. Kami menyarankan agar kelangsungan Al-Amin tetap terjaga hendaknya kelak tidak harus dilimpahkan kepada Gus Udin, bukan karena kami mempunyai pamrih apa-apa terhadap pesantren ini, tetapi pemikiran kami semata agar Al-Amin dapat terus beroperasi dengan baik, lancar dan maju, termasuk kami juga membuka perbincangan dengan beliau perihal wakaf, yang sebenarnya untuk hal wakaf ini pastinya beliau telah sangat paham.
Sebenarnya waktu itu kami tidak sampai hati untuk mengutarakan pendapat kepada beliau, karena saya meyakini, selembut apa pun hati Kiai Umar, apa yang telah menjadi pemikiran dan pendapat kami waktu itu pastinya bisa menyakiti perasaan beliau. Tetapi waktu itu kami memang terpaksa melakukannya demi kemaslahatan orang banyak.
“Saya tahu apa yang jadi kebutuhan Udin,” jawab Kiai Umar waktu itu.
Dan selanjutnya kami tidak berani lagi usul apa-apa perihal Al-Amin, sampai kiai berpulang. Entah semasa kiai masih hidup sudah pernah atau belum membicarakan perihal Al-Amin dengan Gus Udin, kami tidak ada yang mengetahuinya. Yang jelas kami mengetahuinya setelah sekitar setahun kiai meninggal, Gus Udin memberi pemberitahuan kepada kami bahwa sejak itu, dia menentukan sendiri bahwa dirinyalah yang menjadi pewaris kepemilikan dari pesantren, baik Al-Amin 1, maupun Al-Amin 2.
Satu tahun setelah pemberitahuan itu, Gus Udin mengumumkan keputusannya bahwa Al-Amin 1 hendak ditutup pada tiga tahun ke depan, dan langkah itu diawalinya dengan tidak ada penerimaan santri di Pesantren Al-Amin 1 setelahnya.
Puncak dari serentetan peristiwa itu adalah ketika semua yang bekerja di Al-Amin 1 dilimpahkan ke Al-Amin 2, termasuk mudir-nya. Sejak itulah gedung Al-Amin 1 tidak beroperasi lagi sampai akhirnya saya mendengar kabar apa yang disampaikan Pak Amat tadi, bahwa tanah dan bangunan di mana Al-Amin berdiri telah dijualnya. Dan uang hasil penjualan itu kami tidak tahu hendak dikemanakan.
Kami merasa tidak punya kuasa untuk mempermasalahkan hal itu, bahkan sekadar untuk menanyakannya pun tidak berani melakukan. Kami menyayangkan penutupan Al-Amin 1, tapi sebenarnya yang lebih kami sayangkan adalah kelakuan Gus Udin yang jarang sekali mengajak kami membicarakan keputusan-keputusannya.
Meski sejujurnya, kami memang tidak punya hak apa pun terhadap pesantren, tetapi jika Gus Udin bersedia berbagi rembug, paling tidak kekecewaan kami tidak akan sebesar sekarang ini. Dengan begitu, tentu saja kami juga akan berusaha untuk memaklumi jika yang menjadi alasan dan tujuan dari apa yang dilakukan Gus Udin masuk akal.
Seingat kami sebelum semua itu terjadi, hanya satu kali obrolan perihal Al-Amin 1 yang dia lakukan bersama kami.
“Cukuplah hanya Al-Amin 2 yang dipertahankan di tempat ini,” ucapnya waktu itu.
Karena merasa tidak nyaman lagi bekerja di Al-Amin 2, sebagian karyawan Al-Amin 1 yang dulu dilimpahkan ke Al-Amin 2, memilih untuk keluar dan bekerja di tempat lain. Bagi saya sendiri, tidak mudah untuk lepas dari Al-Amin ini, mengingat bahwa di pesantren inilah saya merasa mendapatkan segalanya, terlebih ilmu dan kesejahteraan hati. Saya telah berhutang budi pada Kiai Umar, karena beliaulah yang mengentaskan saya dari jalanan hingga bisa menjadi seperti sekarang ini.
Perihal sikap Gus Udin terhadap saya selama ini, sejujurnya dia tidak pernah berbuat jahat kepada saya. Bahkan sudah tidak menjadi rahasia lagi meski saya yang sering mendapat perlakuan khusus dari Kiai Umar pun, kurasa Gus Udin juga tidak pernah sedikit pun berbuat buruk kepada saya, bahkan saya merasa dia juga tidak pernah merasa tidak memercayai saya.
Bisa dibilang selacugh-lacugh-nya Gus Udin, setahu saya dia tidak punya keinginan untuk menyingkirkan saya. Bahkan sampai saya menduga, mengapa dia memutuskan Al-Amin 1-lah yang dia jual, mungkin karena dia merasa sungkan jika harus ghituki (merepotkan) saya. Sesungguhnya karena alasan itulah saya tidak berani bertindak lebih jauh terhadap keputusan-keputusan yang Gus Udin lakukan selama ini.
Saya merasa lancang jika saya nekat untuk mengajak bicara perihal Al-Amin, terlebih jika saya harus menyarankan sesuatu kepadanya. Dan sikap diamnya kami semakin tidak terusik manakala melihat sepak terjang Gus Udin setelah penjualan aset itu.
Baca Juga
Cerpen : Mencintai Pembunuh Itu
Kami menduga Gus Udin memang tidak melakukan sesuatu yang di luar batas. Semuanya seperti normal-normal saja. Kabar yang saya dengar Gus Udin memang pergi ke luar kota dalam beberapa hari. Meski begitu kami tidak lantas punya pikiran buruk kepadanya, terlebih pada kenyataannya, pada saat dia pulang memang tidak ada sesuatu, juga sikapnya yang pantas untuk dicurigai.
Bahkan ketenangan itu kami rasakan telah berlangsung hampir selama setahun, setidaknya sampai datangnya kartu undangan ini. Sebuah kartu undangan yang bukan hanya untuk ditujukan kepada saya, tetapi juga ditujukan kepada seluruh penghuni Al-Amin 2, termasuk para santrinya.
Inti dari isi undangan tersebut adalah, kami diminta untuk menghadiri pembukaan sebuah pesantren baru dengan nama Al-Amin 1, dan lokasi berdirinya pesantren tersebut berada di kampung yang berbeda. Yang saya tahu keadaan kampung tersebut lebih pelosok dibanding dengan kampung Al-Amin 2 ini.
Yuditeha sudah banyak melahirkan karya sastra. Karya-karyanya antara lain: Novel Komodo Inside (Grasindo, 2014), Kumcer Balada Bidadari (Penerbit Buku Kompas, 2016), Buku Puisi Hujan Menembus Kaca (Kekata, 2017), buku Puisi Air Mata Mata Hati (Kekata, 2017). Selain itu juga Kumcer Kematian Seekor Anjing pun Tak Ada yang Sebiadab Kematiannya (Basabasi, 2017), Kumcer Kotak Kecil untuk Shi (Stiletto, 2017), dan Kumcer Cara Jitu Menjadi Munafik (Stiletto, 2018). Pemilik nama asli Theopilus Yudi Setiawan, ini menetap di Karanganyar, Jawa Tengah. Sering memenangkan berbagai perlombaan penulisan.
Terpopuler
1
Lafal Bacaan Doa Nabi Ibrahim untuk Keamanan Negeri
2
14 Doa Nabi Muhammad Saw, Cocok Dibaca di Hari Maulid Nabi
3
Hukum Menjarah Rumah Orang Lain saat Unjuk Rasa
4
PCNU Pringsewu Terima Wakaf Tanah untuk Lembaga PAUD di Kecamatan Ambarawa
5
PW GP Ansor Lampung Komitmen Jaga Persatuan lewat Istighotsah dan Doa Bersama Serentak
6
NU Lampung Ketuk Pintu Langit untuk Keamanan dan Kedamaian Indonesia
Terkini
Lihat Semua