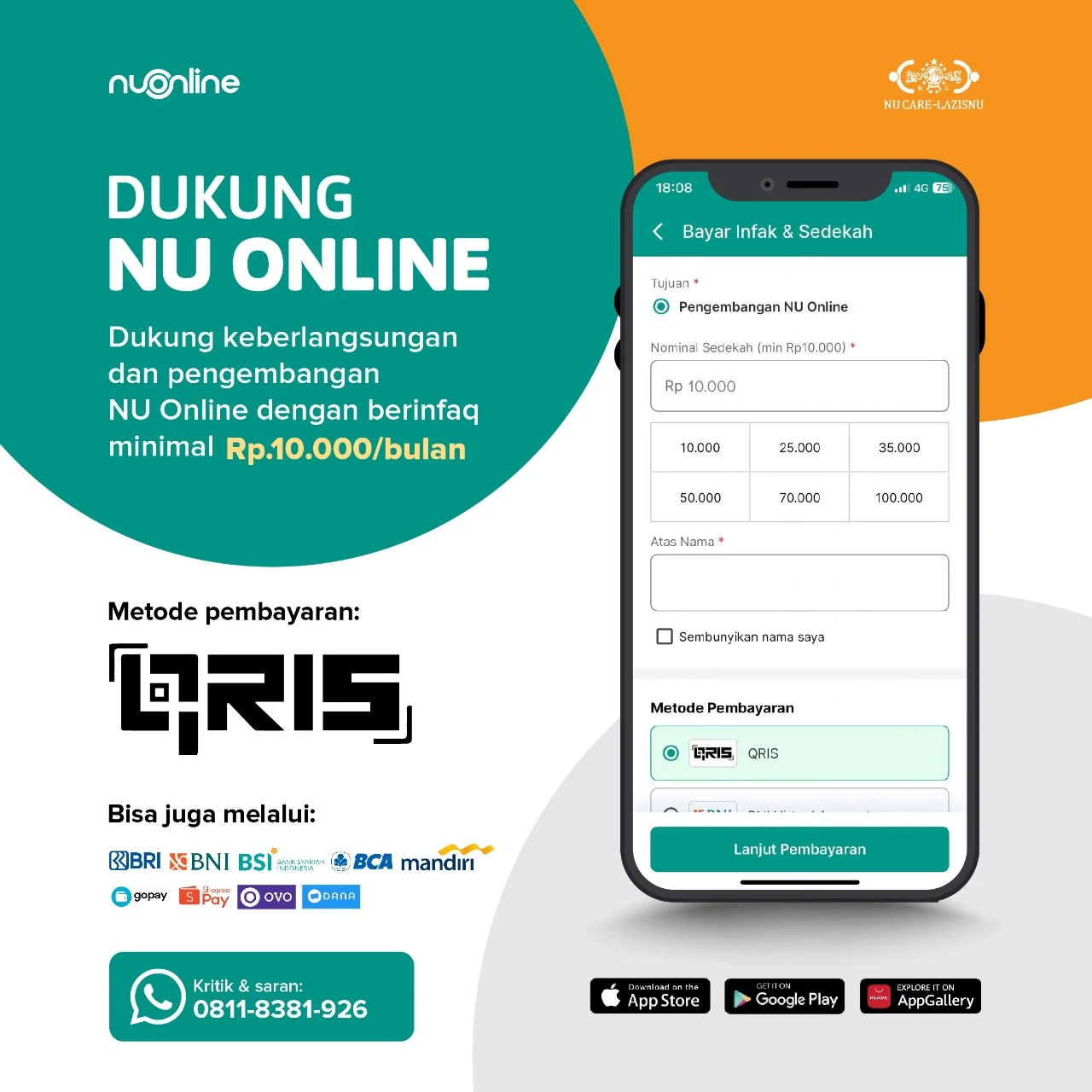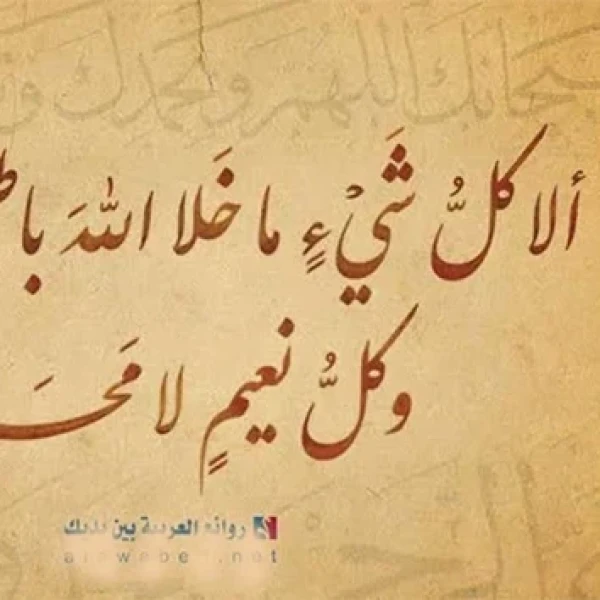Cerpen Adam Yudhistira
Hujat-gunjing yang bertabur dari mulut Umar menjadi musabab paling absah berlarat-laratnya kebencian penghuni pondok pesantren Sibalang kepada Barda. Sejak kedatangannya sebulan yang lalu, Kiai Abdullah membiarkan lelaki setengah baya itu tinggal di mushala.
Keputusan itu karena tak ada satu pun para santri yang sudi berbagi bilik dengannya.
Sebenarnya, penolakan keras itu terjadi bukanlah tanpa sebab. Penolakan itu terjadi lantaran Umar telah menyebarkan desas-desus di kalangan teman-temannya, bahwasanya Barda adalah seorang muncikari sekaligus penjahat kambuhan yang sedang diburu polisi.
“Lelaki itu seharusnya diusir saja,” ucap Umar dingin. “Dia telah membalurkan najis ke tempat ini.”
“Dari mana kau tahu kalau dia seorang buronan dan muncikari?” tanya Hanif tak mengerti. “Apakah sebelumnya kalian pernah bertemu?”
“Aku tahu siapa dia,” kata Umar setengah berbisik. Pemuda itu merunduk sedikit, seolah cemas kata-katanya akan didengar santri-santri lain yang tengah makan siang di kantin Mak Zainab. “Dia berasal dari kampungku, jadi aku tahu benar kelakuannya.”
“Andaipun benar, kita tak berhak menghakiminya,” ucap Sobari menyela. “Urusan dosa adalah urusan Allah semata-mata. Bukan urusan manusia.”
“Itu memang benar,” sahut Umar mencoba memperkuat kata-katanya kembali. “Apa kau lupa bagaimana awal mula lelaki itu datang ke pondok ini? Dia memaksa masuk dalam keadaan mabuk. Kalau tidak gila, orang ini pasti berniat jahat.”
Sobari tersenyum tipis. “Kita wajib memuliakan tamu dengan adab yang baik,” katanya sambil meminum teh hangat yang mengepul di atas meja. “Buktinya Kiai Abdullah mau menerimanya. Menurut hematku, tak baik kita menggunjingkannya. Setiap orang punya masa lalu. Mungkin dia datang ke sini karena betul-betul ingin bertobat.”
Umar terdiam. Raut wajahnya masam. Sebenarnya, bila ditimbang-timbang, perkataan Sobari itu ada benarnya juga. Selama Barda tinggal di pondok pesantren Sibalang, lelaki berperawakan kurus jangkung itu kerap membantu meringankan pekerjaan para santri. Sehari-hari dia mengisi gentong tempat mengambil air wudhu, sesekali mencuci sajadah, menyapu mushala, bahkan tak jarang dia membersihkan bilik para santri tanpa diminta.
Menjelang shalat Ashar, lepas semua aktivitasnya itu, Barda akan duduk di beranda mushala. Dia beristirahat seusai memunguti rerontokan daun-daun angsana di halaman.
Mula-mula tak ada yang peduli. Namun lama kelamaan, kebiasaan itu membuat beberapa santri tersentuh. Namun di mata Umar, semua itu hanyalah siasat Barda untuk mengambil hati Kiai Abdullah, agar dirinya diizinkan tinggal lebih lama.
“Kalian jangan tertipu,” ucapnya menyeringai sinis. “Seperti yang kuceritakan tadi, dia itu lelaki bejat. Banyak dosanya. Jangan dekat-dekat, kecuali kalian mau kecipratan dosa juga.”
Sebagian santri banyak yang termakan desas-desus yang diembuskan Umar, sebagian mengabaikannya, dan sebagian lagi bertanya-tanya. Mereka merasa Umar menyembunyikan sesuatu dari mereka, namun apa itu, mereka tak mampu menerkanya. Hanya saja, setiap kali mereka membicarakan Barda, Umar selalu memasang wajah tak suka.
***
Apabila rembang petang, di waktu pertengahan antara shalat Ashar ke Magrib, Kiai Abdullah biasanya berjalan-jalan mengitari pondok. Suasana pesantren kecil di tengah-tengah kampung Sibalang itu begitu tenang.
Para santri laki-laki menghabiskan waktu dengan bermain bola, sedangkan para santri perempuan duduk-duduk di birai perpustakaan dan sebagian lagi asik menyirami tanam-tanaman.
Ketika tiba di mushala, Kiai Abdullah mendapati Barda sedang duduk melamun. Dia menyandarkan tubuhnya ke tiang musala sambil memandangi para santri laki-laki yang sedang asyik bermain bola. Saking khusuknya, Barda bahkan tak menyadari jika Kiai Abdullah telah berdiri di sampingnya.
“Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu,” ucap Kiai Abdullah lepas menyapa Barda dengan salam yang tak dibalas. “Apa yang membuatmu datang ke sini?”
“Aku ingin belajar agama, Kiai.” Barda menunduk, seperti menghindari kontak mata dengan Kiai Abdullah. Pekik riuh para santri yang asyik bermain bola tak lagi menarik minatnya untuk mengangkat kepala.
Kiai Abdullah tersenyum. “Apakah kaukenal dengan Umar?” tanyanya tenang. “Apakah kabar yang diumbar-umbarnya itu benar?”
Lelaki itu menghela napas panjang. Dia mengangguk, mengusap dahinya sekilas dan jari-jarinya terlihat sedikit gemetar.
Kiai Abdullah memandang melewati pundaknya, memperhatikan bekas luka menyilang di bawah mata. Apa yang dilihatnya pada penampilan Barda, seperti memperkuat apa yang selama ini digunjingkan santri-santrinya.
Lelaki di sampingnya itu pastilah bukan lelaki baik-baik. Setidaknya, dia pasti pernah memiliki masa lalu yang buruk.
Kiai Abdullah diam sejenak, sengaja memberi waktu agar Barda merasa sedikit tenang dan mau bercerita perihal dirinya. Desas-desus yang merebak di kalangan para santri, membuat lelaki sepuh itu merasa perlu mencari kebenarannya sendiri.
Mata tuanya yang berpengalaman itu bisa menangkap beban batin yang demikian berat pada diri Barda.
“Satu hari nanti napasku pasti akan padam,” ucap Barda murung. “Aku tidak mau hidup bergelimang dosa terus-terusan.”
“Ceritakanlah padaku semuanya,” sela Kiai Abdullah seraya tersenyum samar. “Aku akan mendengarkan.”
Mula-mula Barda seperti ragu, namun setelah menghela napas agak panjang, lelaki itu pun menceritakan riwayatnya secara perlahan.
Dia mengaku dirinya memang bekas muncikari di sebuah lokalisasi yang berada di pinggir kampung Cempiring—sebuah kampung yang cukup jauh jaraknya dari kampung Sibalang.
Dalam pungkasan singkat ceritanya, Barda mengatakan bahwa hidup yang dia lakoni selama ini memang lekat dalam gelimang syubhat dan maksiat. Namun sejak kematian istrinya dua tahun yang lalu, lelaki itu sadar dan ingin bertobat.
Anak lelaki satu-satunya menuding bahwa dia adalah penyebab musibah menimpa keluarga mereka. Perempuan itu meninggal lantaran makan hati dan tersiksa, begitu tudingan anaknya yang tak bisa ditampiknya.
Dalam satu pertengkaran hebat, anaknya pergi dari rumah. Satu setengah tahun penuh dia mencari, sampai akhirnya mendapat kabar, bahwa anak lelakinya itu telah menjadi santri di pondok pesantren ini.
Kedatangannya petang itu membawa beban malu tak terpermanai. Dia ingin mengajak anaknya pulang dan menebus dosa-dosanya di masa lalu. Baginya, daripada hidup berkalang dosa, tentulah lebih baik mati berkalang malu. Meski kebencian dan kata-kata tajam akan dia terima dari anaknya, tetap saja terasa lebih baik ketimbang terus-menerus dikejar rasa berdosa.
“Apakah masih ada ampunan untuk orang sepertiku, Kiai?” begitu dia bertanya ketika selesai membuka semua rahasianya. “Dosaku rasanya sudah lepus ke langit junjung.”
Kiai Abdullah termenung sesaat. Dia mendekap tongkat rotan di tangannya. “Aku tak bisa menjawab pertanyaanmu itu. Tapi aku bisa membantumu.”
“Aku sudah lelah dan semakin tua. Aku betul-betul ingin bicara dengannya. Sebagai bapak dan anak.” Barda menghela napas berat, menunduk dan mulai terisak.
“Aku paham kesedihanmu.” Kiai Abdullah memandang ke tengah halaman musala yang sudah sepi. Tak berapa lama lagi waktu Magrib akan tiba. “Menjadi manusia baik itu lebih berat dari yang kau duga, Barda. Tapi jangan berputus asa dari jalan baru yang telah kau mulai. Semua pasti ada hikmahnya.”
Barda menyeka air matanya dengan ujung telunjuk. “Aku akan berusaha, Kiai. Aku akan berusaha ... “ desahnya nyaris tak terdengar.
***
“Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan orang yang telah membunuh ibuku.” Saat berkata, mata Umar berpijar seperti bara. “Jika saja aku tak ingat dosa, mungkin sudah kubunuh dia di tempat ini.”
Kiai Abdullah mendesah pelan. “Bagaimanapun dia adalah bapakmu, Umar,” sahutnya mencoba memadamkan bara itu. “Dia jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menemuimu. Dia ingin meminta maaf kepadamu.”
“Apakah aku harus memaafkannya, Kiai?” tanya Umar dengan nada enggan. Dia duduk dengan gelisah di hadapan meja Kiai Abdullah. Siang itu, secara khusus Kiai Abdullah meminta Umar datang ke ruangannya untuk membicarakan pesan-pesan Barda.
“Aku bisa melihat kesungguhan di mata bapakmu,” ucap Kiai Abdullah lembut. “Dia betul-betul ingin bicara denganmu.”
“Rasanya sulit sekali, Kiai,” keluh Umar dengan suara gemetar. Dia menunduk dalam-dalam. “Setiap melihatnya, aku melihat penderitaan yang diberikannya untuk ibuku. Aku bahkan masih mengingat dengan jelas bagaimana kejinya dia menyakiti ibuku dengan perempuan-perempuan itu.”
Dua tahun yang lalu, selepas kematian ibunya, begitu meninggalkan rumah dan menginjak tanah pesantren Sibalang ini, Umar telah bersumpah pada dirinya sendiri, dia tak akan pulang lagi.
Menjauh adalah pilihan terbaik dari yang paling buruk yang bisa diambilnya saat itu. Sebagai anak lelaki yang telah beranjak dewasa, dia takut tak bisa menahan diri untuk melukai bahkan membunuh bapaknya sendiri.
Pada saat yang sama, tanpa sepengetahuannya, Barda berhasil menemukannya di sini. Entah bagaimana lelaki yang mulai renta itu bisa menemukannya. Seingatnya, dia tidak pernah memberitahu siapa pun, baik kepada pihak keluarga ibunya maupun bapaknya, bahwa dia mengasingkan diri di pondok pesantren ini.
Keputusan Umar menenangkan diri selepas kematian ibunya, mungkin keputusan paling bijak yang bisa dia ambil. Setidaknya, dia bukan berada di penjara dengan dakwaan membunuh Barda. Di sini dia bisa memperdalam ilmu agama, memperbaiki ibadahnya, mengirim doa-doa untuk mendiang ibunya.
Baca Juga
Kanan Mati karena Tidak Mau Naik Perahu
Namun sejak kedatangan Barda, berhari-hari dia jarang keluar dari biliknya. Umar menghindari pertemuan dengan lelaki ringkih itu. Lelaki yang menyamaki hatinya dengan duri-duri benci yang menancap begitu dalam.
“Kalau saat ini kau belum bisa memaafkannya, setidaknya beri dia kesempatan untuk berbicara denganmu sekali saja,” bujuk Kiai Abdullah menyentak lamunan Umar.
“Tapi, saat ini hatiku masih sakit, Kiai,” jawab Umar gamang.
“Kau dan bapakmu terikat hubungan tali-darah, Umar. Sebaiknya jangan kaubiarkan amarah dan dendam itu membuatmu melanggar ajaran agama. Apa pun yang diperbuatnya, kau harus memuliakan orang tua,” pungkas Kiai Abdullah kehabisan cara untuk melunakkan hati Umar.
"Beri aku waktu,” jawab Umar pada akhirnya. Pemuda itu menggeleng lemah. “Aku belum siap berbicara dan berada di dekatnya. Maafkan aku. Aku belum bisa.”
“Baiklah,” ujar Kiai Abdullah mengalah. “Tapi jika sudah sejuk hatimu nanti. Temuilah dia. Jangan kau tunda terlalu lama.”
Umar mengangguk pelan, namun tak menjanjikan apa-apa.
***
Sebuah malam yang kalut dan kalang-kabut, telah menutup kemungkinan bagi dua hati itu dipertautkan kembali. Pondok pesantren Sibalang malam itu terbakar hebat. Bagai dilanda kiamat kecil, sebagian besar bilik-bilik santri, ruang belajar-mengajar, perpustakaan dan ruang dapur dilalap api besar yang berkekuatan sangat dahsyat.
Dalam sekejap, bangunan-bangunan berdinding semi-permanen itu rubuh, ambruk, hingga nyaris rata dengan tanah. Seluruh penghuni pondok yang baru tunai shalat Isya berhamburan ke halaman, meraung-raung ketakutan, sambil lari menyelamatkan diri.
Tak banyak yang bisa diselamatkan oleh para santri dan pengurus pondok, hanya nyawa dan pakaian yang masih melekat di badan.
Sehari setelah kebakaran besar itu terjadi, beberapa orang santri yang baru kembali dari rumah sakit membawa kabar tentang Kiai Abdullah yang turut menjadi korban. Nyawa lelaki sepuh itu masih bisa diselamatkan, namun tidak untuk nyawa Barda yang malam itu berusaha menolong Kiai Abdullah lolos dari kobaran api.
Menurut keterangan santri itu, Barda meninggal lantaran luka bakar yang dia derita terlampau parah.
Umar yang mendengar cerita itu tak sanggup membayangkannya. Kini perasaan pemuda itu bagai terpiuh-piuh remuk redam, sebagaimana terpiuh-piuhnya seluruh bangunan pondok pesantren Sibalang. Hatinya remuk.
Barangkali jauh lebih remuk dari wajah bangunan yang telah hancur menjadi puing-puing arang. Ada kata-kata yang belum sempat dia ucapkan kepada bapaknya. Kata-kata itu kini menjadi gumpalan di tenggorokan dan mungkin akan membeku menjadi batu penyesalan.
Adam Yudistira, lahir di Lampung tahun 1985. Saat ini bermukim di Muara Enim, Sumatera Selatan. Cerita pendek, cerita anak, esai, puisi, dan ulasan buku yang ditulisnya sudah tersiar di berbagai media massa cetak dan online.
Tulisan ini merupakan juara pertama dalam lomba Cerpen tingkat nasional Harlah laman nulampung.or.id. Tulisan ini sudah dibukukan dalam kumpulan Cerpen "Ustaz Miring Kampung Kami" yang diterbitkan oleh LTN PWNU Lampung, Mei 2019."
Terpopuler
1
PCNU Pringsewu Sosialisasikan Keputusan Munas dan Konbes NU 2025
2
3 Amalan Sunnah di Bulan Rabiul Awal
3
Doa dan Niat Menyambut Bulan Maulid
4
Jihad Pagi NU Pringsewu Digelar Kembali, Peringati Kemerdekaan RI dan Songsong Maulid Nabi
5
Surat Yasin: Hati Al-Qur’an dan Kasih Sayang Allah untuk Umat
6
Maulid Nabi 5 September 2025, Ini 5 Alasan Sunnah Merayakannya
Terkini
Lihat Semua