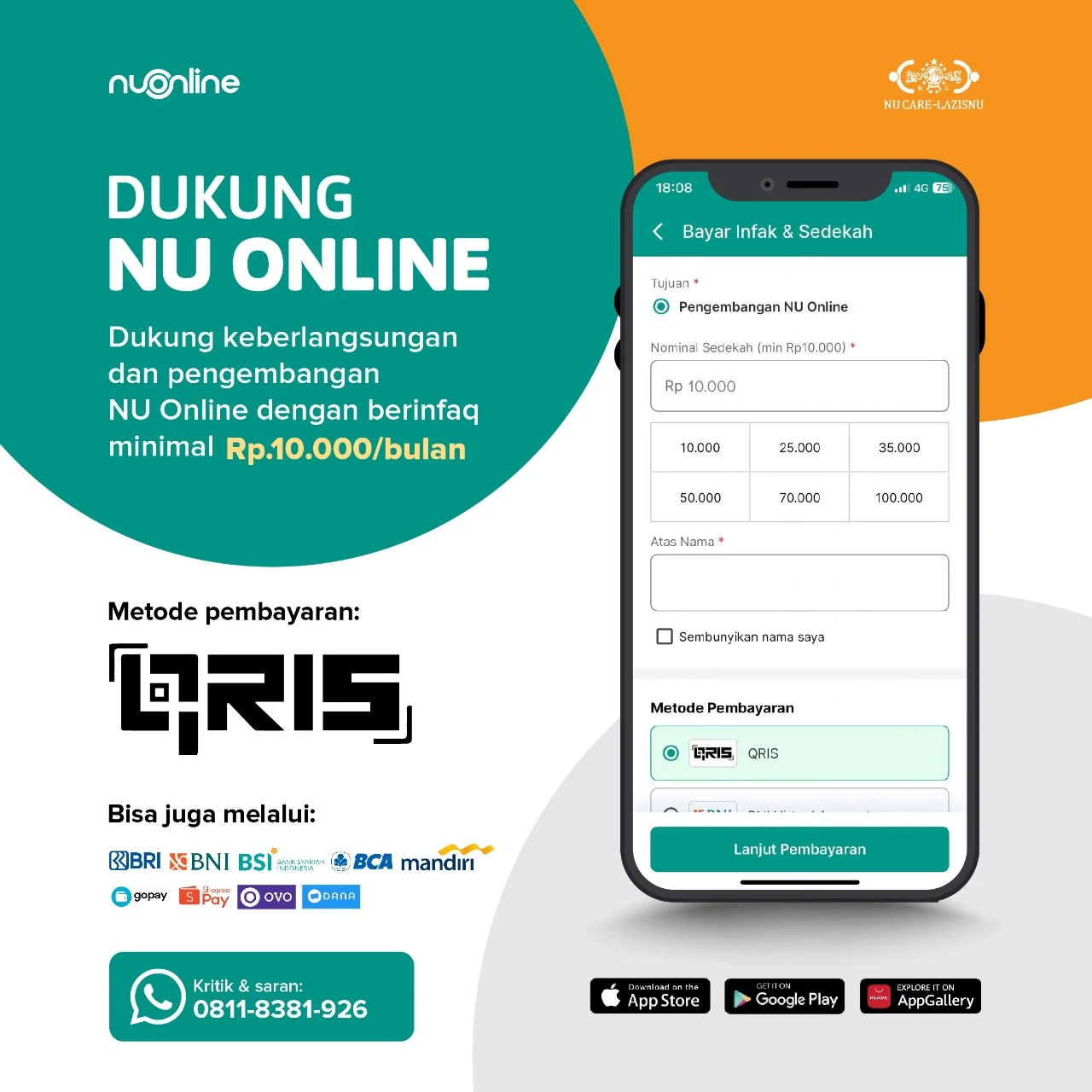Wahyu Iryana
Penulis
Mudik bukan sekadar perjalanan pulang. Ia lebih dari antrean panjang di gerbang tol, lebih dari tiket yang tiba-tiba melambung harganya, lebih dari kemacetan yang membuat para sopir truk membunyikan klakson seperti doa-doa yang tak terkabul. Mudik adalah ritual pertaubatan tahunan, di mana para perantau pulang membawa rindu dan, tanpa sadar, juga membawa dosa-dosa kecil yang ingin dicuci bersih di pangkuan ibu.
Bagi sebagian orang, mudik adalah kesempatan untuk memperbaiki catatan kehadiran di buku kehidupan. Ada yang pulang karena ingin mencium tangan orang tua, ingin memastikan bahwa suara mereka masih utuh meskipun usia telah banyak mencuri tenaganya. Ada juga yang pulang sekadar untuk menunjukkan bahwa hidup di kota bukanlah pilihan yang salah—meski sering kali, lebih banyak pamer daripada kejujuran.
Tetapi, apakah benar semua orang mudik dengan niat suci? Atau jangan-jangan, banyak juga yang sekadar ingin menunjukkan bahwa mereka masih ada? Bahwa mereka belum kalah oleh kerasnya ibu kota? Bahwa mereka masih bisa membawa pulang oleh-oleh meski cicilan di dompet berteriak minta tolong?
Mudik: Antara Kota dan Desa
Di kota, hidup adalah kompetisi. Tidak ada waktu untuk sekadar duduk berlama-lama menikmati kopi di teras rumah. Tetapi begitu mudik tiba, semua berubah. Waktu seolah melambat. Kota dan desa kembali berhadapan.
Di kota, hidup itu eksistensi. Orang dinilai dari kendaraan yang mereka pakai, merek baju yang mereka kenakan, seberapa sering mereka update di media sosial. Di desa, hidup itu silaturahim. Seseorang dihargai bukan karena merek, tetapi karena siapa orang tuanya, bagaimana dia memperlakukan keluarganya, dan seberapa sering dia berbagi rezeki dengan tetangga.
Ironisnya, orang kota yang mudik ke desa sering kali membawa mentalitas kota yang sama. Mereka ingin pulang sebagai pemenang, bukan sebagai anak kampung yang pulang menundukkan kepala. Mereka ingin rumahnya terlihat paling baru, paling megah. Mereka ingin dilihat sebagai orang sukses, meskipun di balik itu semua ada cicilan yang belum lunas dan tabungan yang sudah menipis.
Padahal, bagi orang tua di kampung, anak yang sukses bukanlah yang pulang dengan mobil mewah, tetapi yang pulang dengan hati yang masih mengenali jalan ke dapur. Bagi ibu, anak yang membanggakan bukan yang membayar biaya renovasi rumah, tetapi yang masih ingat bagaimana cara memasak makanan kesukaannya.
Mudik: Antara Dosa dan Pemaafan
Mudik juga sering kali menjadi panggung pemaafan massal. Orang-orang yang setahun penuh tidak saling menyapa tiba-tiba menjadi ramah. Saudara yang dulu bertengkar karena warisan kini bersalaman sambil tersenyum. Mantan yang dulu ditinggalkan tanpa pesan sekarang disapa dengan basa-basi, meskipun sama-sama tahu bahwa luka lama tidak benar-benar sembuh.
Lucunya, mudik juga mengandung dosa-dosa kecil yang sering kita anggap remeh. Ada dosa menyombongkan diri di depan saudara yang tidak seberuntung kita. Ada dosa melupakan saudara jauh yang seharusnya kita kunjungi. Ada dosa pura-pura sibuk agar tidak terlalu lama duduk di rumah orang tua.
Mudik adalah ujian. Ia menguji kesabaran di tengah kemacetan. Ia menguji keikhlasan ketika melihat teman lama ternyata lebih sukses. Ia menguji seberapa besar rindu kita kepada rumah, dan seberapa banyak kesalahan yang berani kita akui di hadapan orang tua.
Dan pada akhirnya, mudik mengajarkan kita satu hal: tidak semua orang yang pulang benar-benar pulang. Ada yang hanya tubuhnya yang kembali, tetapi hatinya tetap tersesat di kota. Ada yang pulang hanya untuk membuktikan sesuatu, bukan untuk menebus rindu.
Tetapi, bukankah itu juga bagian dari perjalanan hidup? Bahwa tidak semua perjalanan punya akhir yang sempurna? Bahwa tidak semua orang yang kembali akan menemukan apa yang mereka cari?
Mudik adalah soal kembali. Dan di antara semua perjalanan, pulang adalah yang paling sulit.
Syair Mudik
Di jalan tol, kita antre bersama rindu,
mobil-mobil saling berdesakan seperti doa,
tapi mengapa doa kita terdengar seperti klakson?
Ibu di kampung menunggu dengan sepiring cerita,
bapak menyiapkan kursi di teras rumah,
sementara kita membawa pulang oleh-oleh berupa kenangan.
Mudik bukan soal pulang ke rumah,
tetapi soal memastikan bahwa hati kita masih ingat jalan pulang.
H Wahyu Iryana, Penulis adalah Sejarawan dan Penyair UIN Raden Intan Lampung.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan di Zaman Sekarang
2
Fatayat Miliki Peran Strategis Tingkatkan Kualitas Perempuan Muda NU
3
DPRD Lampung Gencarkan Upaya Tingkatkan Siswa SMA Masuk Perguruan Tinggi
4
Kebaikan Menghapus Dosa: Pesan QS Hud Ayat 114 dan Kisah Lelaki Anshar
5
Minat Ikut Seleksi Pimpinan dan Anggota Baznas? Ini Syarat dan Ketentuannya
6
Songsong HUT Ke-80 RI, PCNU Pringsewu Bagikan Bendera Merah Putih ke Masyarakat
Terkini
Lihat Semua