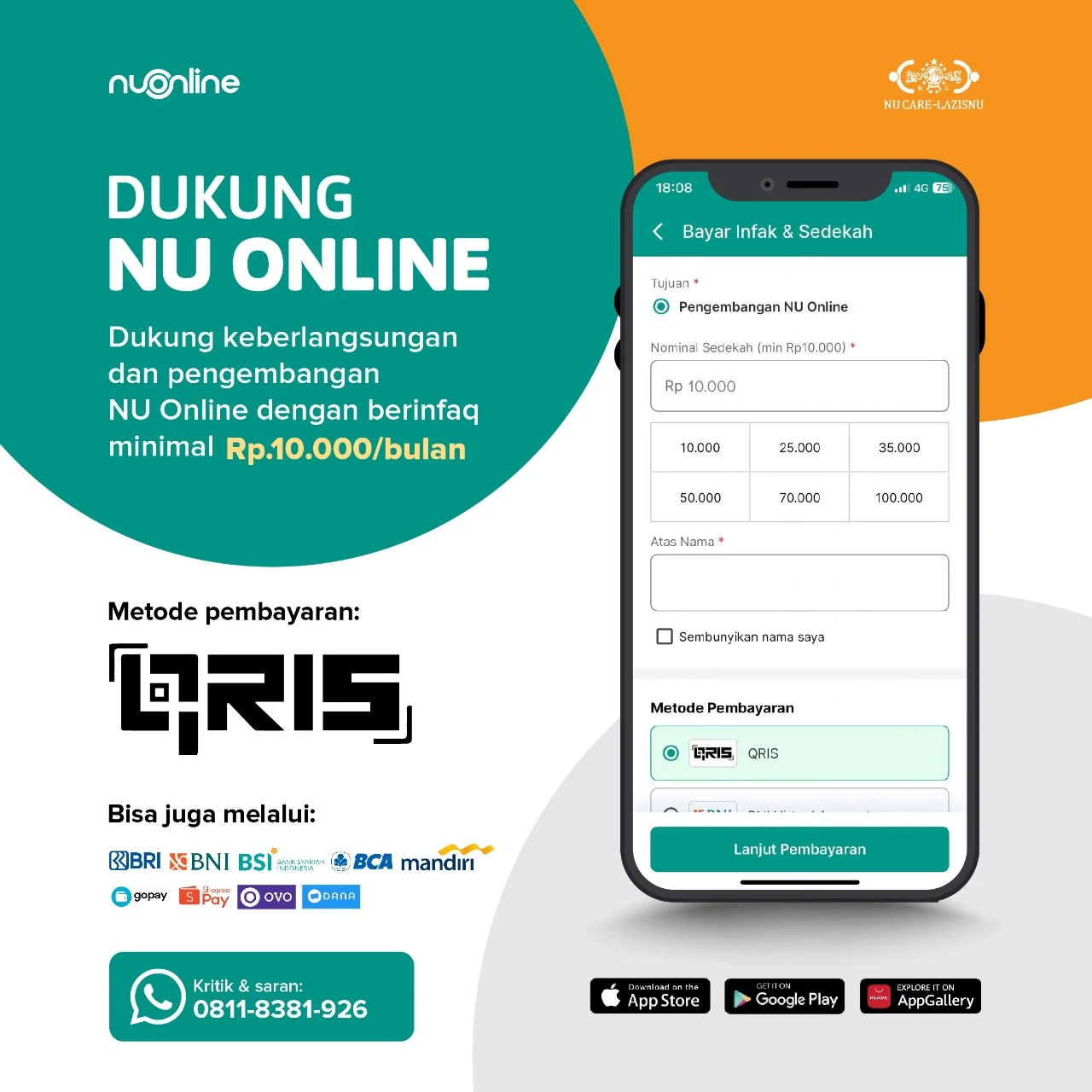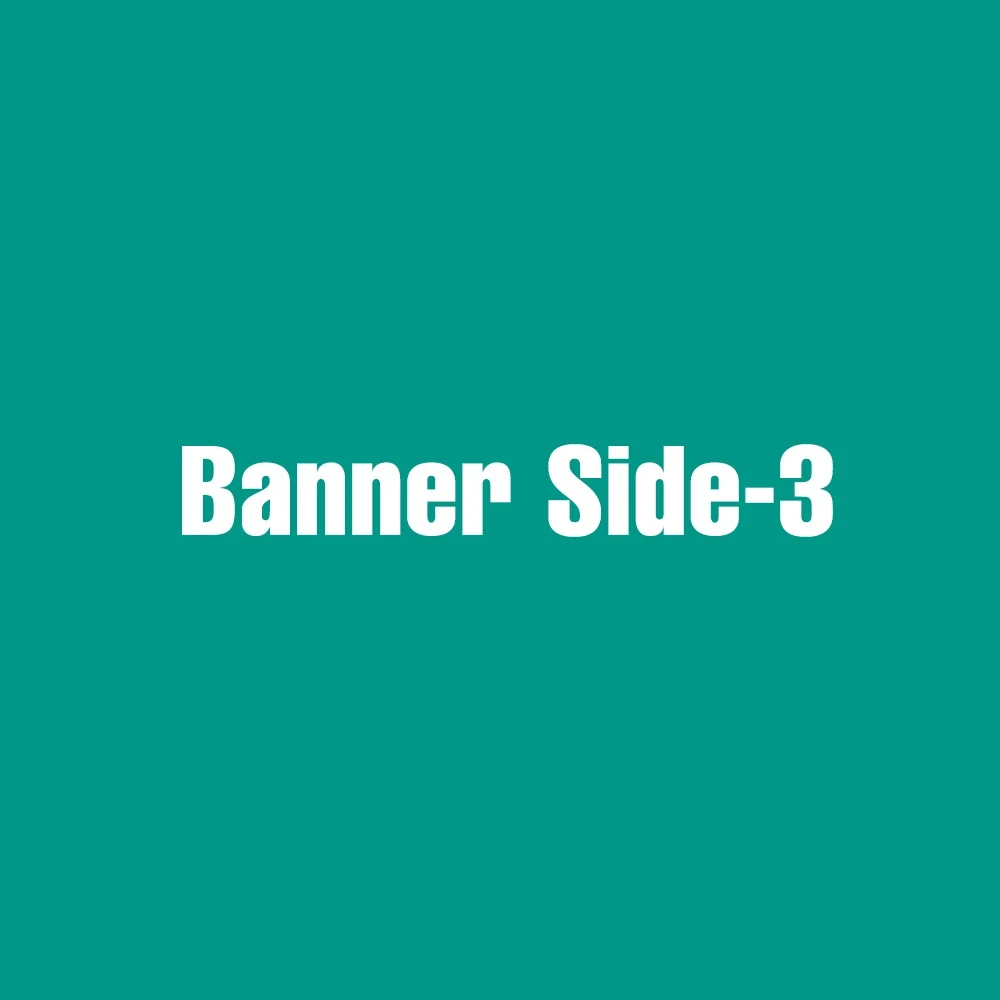Wahyu Iryana
Penulis
Setiap Agustus tiba, Indonesia tak hanya menyambutnya dengan tradisi lomba panjat pinang, karnaval meriah, atau unggahan media sosial bertagar #DirgahayuRI. Bulan ini membawa gema emosional yang lebih dalam kenangan kolektif, kebanggaan, sekaligus refleksi penting: sejauh mana kita telah merawat kemerdekaan? Apakah kemerdekaan yang kita rayakan benar-benar hidup dalam makna keberagaman, keadilan, dan kebersamaan?
17 Agustus 1945 bukan sekadar momentum pengibaran bendera merah putih. Ia adalah titik balik sejarah, saat Indonesia memutuskan untuk menjadi subjek atas dirinya sendiri, bukan objek yang diperintah asing. Namun, perjuangan kemerdekaan tidak hanya soal senjata di medan perang. Ia adalah gerakan pemikiran yang menuntut persatuan, solidaritas lintas budaya, dan keberanian untuk melawan ketakutan kolonialisme.
Menurut catatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), lebih dari 35 kelompok etnis dari seluruh nusantara aktif berkontribusi selama fase perjuangan kemerdekaan 1945–1949. Santri dari pesantren, petani dari desa terpencil, jurnalis yang menulis di bawah ancaman, perempuan yang berperan sebagai pejuang dan pendukung, guru yang mengajarkan semangat kebangsaan, dan tokoh adat yang menjaga nilai budaya, semua bersatu dalam satu nafas yang sama: Indonesia merdeka.
Kini, dalam era globalisasi dan digitalisasi, “perang” yang kita hadapi berbeda. Bukan lagi melawan penjajah yang bersenjata, tetapi berhadapan dengan tantangan yang lebih halus dan kompleks: pengaburan identitas bangsa, intoleransi yang muncul di ruang publik, dan disinformasi yang memecah belah. Kemerdekaan sejati menuntut kita untuk berperang melawan arus disintegrasi yang muncul dari dalam diri bangsa sendiri.
Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman: 718 bahasa daerah, lebih dari 1.300 suku bangsa, dan enam agama resmi yang diakui. Namun realita di lapangan masih penuh tantangan. Laporan Setara Institute 2024 mencatat 229 kasus intoleransi berbasis agama dalam ruang publik selama satu tahun terakhir, angka yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Apa artinya kemerdekaan jika antarwarga masih saling curiga? Jika perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan mengadu domba? Merdeka tanpa keadilan sosial dan persatuan hanyalah selebrasi kosong tanpa substansi.
Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk memaknai ulang Bhinneka Tunggal Ika “Berbeda-beda tetapi tetap satu” bukan sebagai kalimat simbolik semata, melainkan sebagai pijakan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di tengah derasnya arus disrupsi digital dan polarisasi politik, budaya lokal masih menjadi energi penyatu yang kuat. Tradisi-tradisi seperti Sedekah Bumi di Jawa, Mappalili di Sulawesi Selatan, atau Bakar Batu di Papua bukan sekadar ritual, melainkan ekspresi spiritual dan sosial yang merangkul semua golongan masyarakat.
Riset oleh Balitbang Kemdikbudristek (2023) menemukan bahwa 78% masyarakat yang aktif melestarikan tradisi lokal memiliki tingkat kohesi sosial yang lebih tinggi dan sikap toleransi yang lebih baik terhadap perbedaan. Ini membuktikan bahwa semakin kuat akar budaya lokal, semakin kokoh pula fondasi kebinekaan bangsa.
Kebudayaan menjadi jembatan untuk mengenal dan menerima perbedaan, sekaligus memperkuat ikatan sosial yang menjadi modal utama bangsa dalam menghadapi tantangan zaman.
Kemerdekaan di abad digital tidak lagi dapat dipisahkan dari literasi digital. Kebebasan berekspresi di dunia maya adalah hak, namun tanpa literasi yang memadai, ruang digital justru menjadi ladang subur bagi hoaks, ujaran kebencian, dan konflik sosial.
Laporan Kementerian Kominfo (2024) menyebutkan bahwa satu dari tiga pelajar Indonesia pernah terpapar hoaks atau ujaran kebencian melalui media sosial. Ini adalah peringatan keras bahwa merdeka digital harus dibangun dari dasar yang kuat melibatkan sekolah, pesantren, komunitas lokal, dan media independen untuk menciptakan budaya digital yang sehat.
Literasi digital bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tapi juga kemampuan memahami, memilah informasi, dan menciptakan narasi yang mempererat persatuan, bukan memecah belah.
Pelajar, santri, dan generasi merah-putih
Mereka bukan hanya peserta upacara atau pengibar bendera di 17 Agustus. Mereka adalah penjaga cerita bangsa ke depan. Sekolah dan pesantren harus menjadi lebih dari sekadar tempat belajar teori. Mereka harus menjadi ruang praktik nilai-nilai gotong royong, dialog antariman, dan kreativitas dalam keberagaman.
Program kolaborasi antar sekolah, pelatihan menulis lintas budaya, serta platform seni yang inklusif harus didorong untuk mengasah empati dan kecintaan pada bangsa. Dari tangan generasi muda inilah, Indonesia akan terus ditulis ulang dengan semangat baru yang segar dan inklusif.
Penulis mencoba menulis syair tentang Merah Putih di Pinggir Sawah dan Sajadah
Di pinggir sawah Indramayu dan ujung Cirebon,
Bedug menggema di antara debu dan suara gamelan.
Kemerdekaan bukan ancaman di ujung golok cawang,
Tapi doa yang lahir dari darah Ki Kuwu dan airmata pertiwi.
Merah adalah peluh petani yang menari dengan cangkul,
Putih adalah ayat-ayat yang disusun sunyi oleh para santri.
Di atas janur yang melambai di alun-alun,
Tumbuh harap, menyatu: sawah dan sajadah.
Allahu Akbar, bukan pekik perang,
Tapi lirih doa di sela azan dan puisi
Metafora mawar berduri dan melati suci,
Yang disulam dari airmata ibu dan tekad anak negeri.
Merdeka bukan sekadar kata,
Tapi embun yang menyusup di pori-pori bangsa,
Menjelma budaya, menjadi ladang dan jalan,
Menjadi cerita kecil di rumah-rumah sederhana.
Inilah kemerdekaan
Saat darah dan doa menjelma cahaya,
Di mana "satu" dan "beragam"
Menjadi puisi yang terus ditulis oleh waktu.
Sebagai penutup kalimat opini ini penulis perlu menegaskan bahwa Agustusan memang perayaan yang penting. Namun lebih penting lagi adalah bagaimana kita memelihara semangat kemerdekaan dalam tindakan nyata dalam kerja, toleransi, karya, dan keberanian untuk terus berdialog dalam perbedaan.
Karena kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu berkata:
“Aku berbeda darimu, dan karenanya aku butuh kamu.”
H. Wahyu Iryana, Penulis Buku Sejarah Pergerakan Nasional; Melacak Akar Historis Perjuangan Santri Mempertahankan NKRI
Terpopuler
1
Selamat, Lutfiah Abbas Kembali Terpilih Pimpin PAC Fatayat NU Pagelaran
2
Ketua PCNU Pringsewu: Organisasi Ibarat Mobil Berjalan Menuju Satu Tujuan
3
PMII Gelar Pelatihan Kader Nasional di Lampung, Pertama Kali di Luar Jabodetabek
4
Budiman AS: Penggabungan Empat Desa Lampung Selatan ke Bandar Lampung Belum Dibahas DPRD
5
Guru Besar UIN RIL Ajak Pengurus Koperasi Serikat Bisnis Pesantren Terus Berdayakan Ekonomi Pesantren
6
Rahmat Allah Seluas Hidupmu, Mengapa Amalan Saja Tidak Cukup Menyelamatkan
Terkini
Lihat Semua