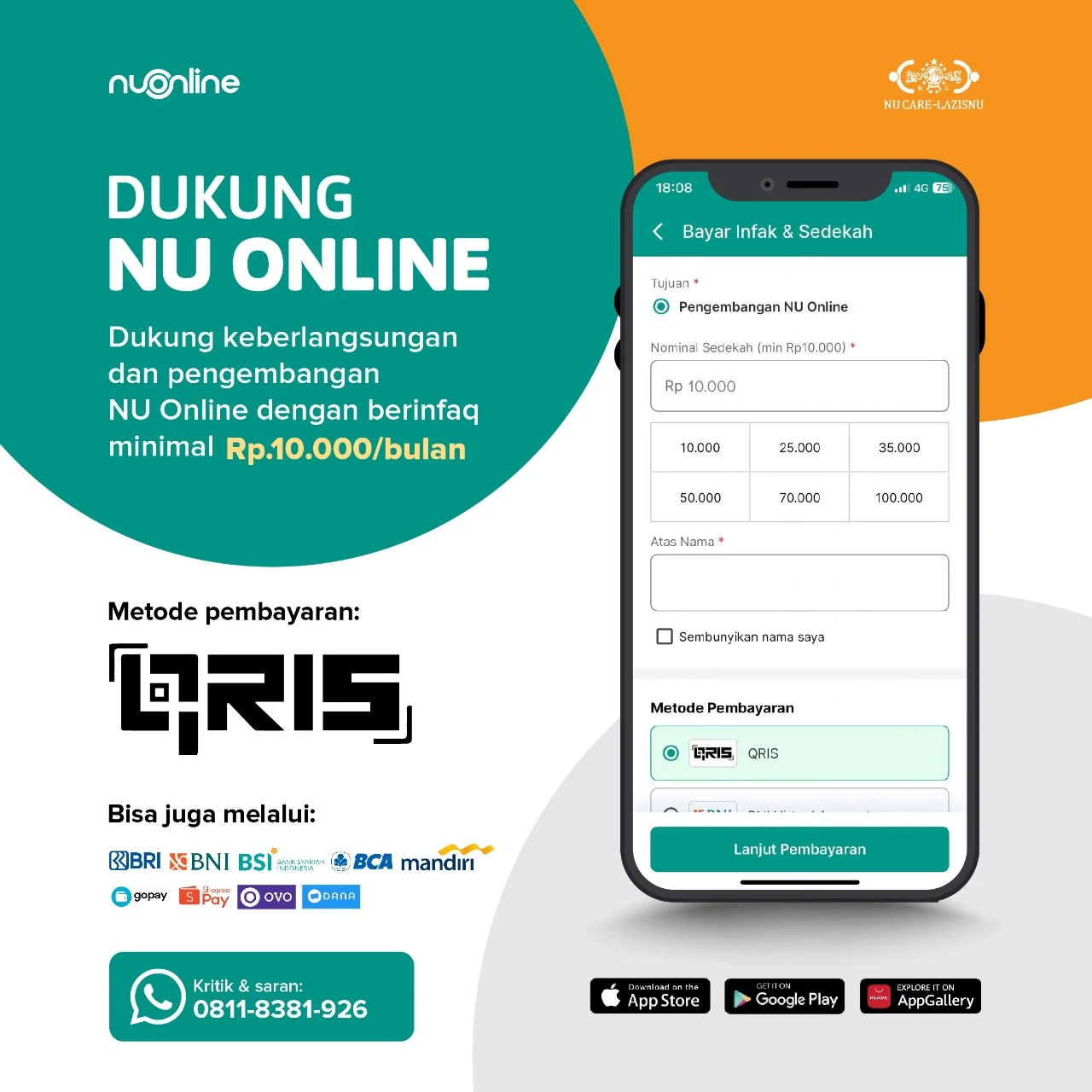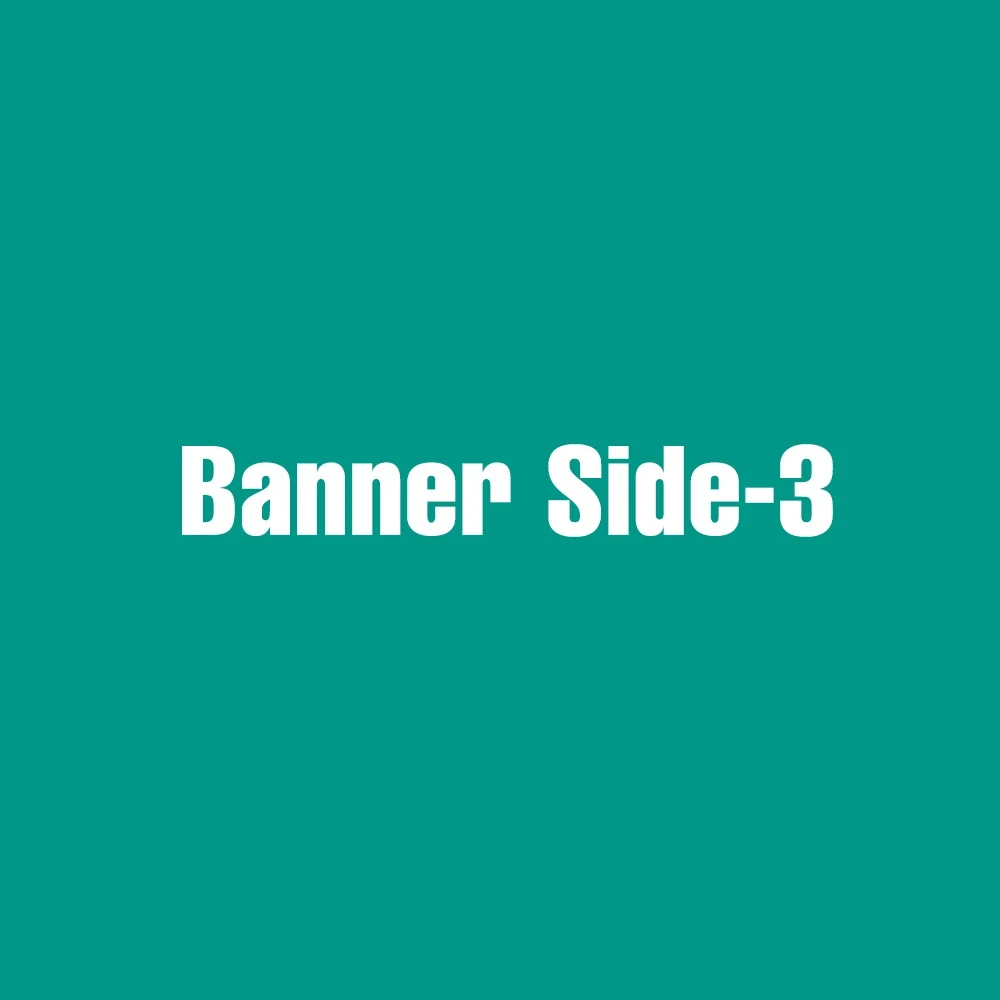Wahyu Iryana
Penulis
Dalam Histories, Herodotus menuliskan bagaimana bangsa Persia, Mesir, dan Yunani membentuk mozaik peradaban melalui perang, diplomasi, dan mitos. Sebagai “Bapak Sejarah”, Herodotus meletakkan fondasi dari apa yang kini dikenal sebagai historiografi deskriptif suatu pendekatan naratif yang berupaya menyajikan kejadian masa lalu melalui pengamatan dan testimoni, dengan latar budaya sebagai bingkai tafsirnya. Ia mencatat bukan semata kronologi, tapi juga mentalité (pola pikir) masyarakat.
Historiografi Yunani Klasik: Dari Mythos ke Logos
Herodotus (±484–425 SM) menulis sejarah dengan pendekatan narrativist, di mana narasi menjadi instrumen epistemologis untuk memahami tindakan manusia. Di balik fakta-fakta, tersirat etika dan pembacaan moral. Namun gaya ini bertransisi menjadi historiografi kritis bersama Thucydides (±460–400 SM), yang menulis History of the Peloponnesian War. Di sinilah sejarah mulai bergerak dari mythos menuju logos. Ia tidak lagi percaya pada intervensi dewa-dewa, tetapi pada motif kekuasaan, diplomasi, dan struktur politik sebagai faktor kausal.
Menurut Thucydides, sejarah bukan cermin masyarakat ideal, tapi konflik antara kepentingan dan kekuatan. Ini menjadi embrio bagi pendekatan realist dalam teori hubungan internasional modern, dan juga cikal bakal historiografi struktural.
Historiografi Romawi: Moral, Kekuasaan, dan Narasi Negara
Di era Romawi, pendekatan historiografi semakin terinstitusionalisasi. Annales karya Tacitus dan Ab Urbe Condita dari Livius menunjukkan bahwa historiografi bukan sekadar catatan, melainkan bagian dari proyek ideologis membangun legitimasi imperium.
Dalam kerangka historiografi klasisisme Romawi, sejarah dipahami sebagai speculum principis (cermin bagi pangeran): alat didaktis untuk mengajarkan kebajikan (virtus) dan keagungan negara. Namun, Tacitus menyelipkan kritik dalam bentuk rhetorical irony, mengungkap sisi gelap tirani dan manipulasi elite, sehingga menjadikannya pelopor dari kritik ideologis dalam penulisan sejarah.
Abad Pertengahan: Historiografi Teologis dan Providensialis
Memasuki Abad Tengah, penulisan sejarah bergeser ke providensialisme gagasan bahwa sejarah adalah ekspresi dari kehendak Tuhan. Seperti yang tampak dalam karya Agustinus De Civitate Dei, sejarah dibingkai sebagai linear teleologis, menuju finalitas eskatologis: keselamatan jiwa.
Historiografi Kristen awal menekankan transcendental causality: Tuhan sebagai agen utama sejarah. Karya-karya Beda Venerabilis, Otto of Freising, hingga kronik perang salib seperti William of Tyre mengandung narrative typology, di mana tokoh dan peristiwa masa lalu dibaca sebagai “tipe” dari rencana ilahi yang sedang berlangsung.
Historiografi menjadi sakral, tetapi juga menyimpan dinamika sosial dan politis Gereja, terutama dalam kontekstualisasi sejarah sebagai alat legitimasi gerejawi dan feudalisme.
Renaisans dan Rasionalisasi Sejarah: Dari Humanisme ke Kritis
Memasuki masa Renaisans, lahir historiografi humanistik di tangan sejarawan seperti Leonardo Bruni dan Machiavelli. Mereka menolak tafsir providensial dan kembali ke sumber klasik. Sejarah dipahami sebagai hasil agensi manusia (human agency) dan tidak lagi hanya akibat kehendak ilahi. Sejarah kini ditulis berdasarkan ars historica: teknik dan seni menulis sejarah secara sistematik, kronologis, dan berbasis sumber primer (ars critica).
Di sini berkembang kritik sumber (source criticism) dan metode filologi sejarah, yang kelak disempurnakan oleh Leopold von Ranke pada abad ke-19. Ranke memperkenalkan metode positivistik dalam sejarah: “wie es eigentlich gewesen” (apa adanya). Historiografi menjadi disiplin ilmiah dengan prinsip objektivitas, verifikabilitas, dan kronologi empirik.
Namun pendekatan ini dikritik karena mengabaikan struktur, kelas, dan kultur bawah. Maka lahirlah reaksi Annales School (Marc Bloch, Lucien Febvre) pada abad ke-20 yang memadukan sejarah dengan ilmu sosial, menggunakan konsep longue duree (sejarah jangka panjang) dan memperhatikan mentalites populaires (kesadaran kolektif masyarakat awam).
Hegel dan Marx: Dialektika Sejarah
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) menginterpretasikan sejarah dalam kerangka dialektika idealisme. Menurutnya, sejarah adalah manifestasi Weltgeist (roh dunia) yang berproses menuju kebebasan. Karyanya, The Philosophy of History, memandang sejarah sebagai drama ide-ide, yang berkembang melalui tesis, antitesis, dan sintesis. Negara (der Staat) adalah puncak realisasi etika dan rasionalitas dalam sejarah.
Karl Marx (1818–1883), murid Hegel yang revolusioner, membalikkan idealisme itu dengan historical materialism (materialisme historis). Dalam The German Ideology dan Das Kapital, Marx menyatakan bahwa sejarah adalah konflik kelas yang lahir dari kontradiksi dalam sistem produksi.
Historiografi Marxian menempatkan basis ekonomi sebagai fondasi, dan superstruktur (ideologi, hukum, seni) sebagai refleksi dari relasi produksi. Sejarah bergerak lewat revolusi sosial, bukan kehendak ilahi atau ide. Inilah pendekatan struktural-dialektik, yang kelak melahirkan tradisi historiografi radikal dan subaltern (E.P. Thompson, Howard Zinn, Ranajit Guha).
Sejarah dalam Al-Qur’an: Narasi Profetik dan Pelajaran Moral
Al-Qur’an tidak menyajikan sejarah dalam arti kronologi linier, melainkan sebagai qasas (kisah-kisah) yang sarat pelajaran (‘ibrah). Dalam QS. Yusuf: 111 ditegaskan, “Laqad kana fi qasasihim ‘ibrah li-ulil albāb”—“Sungguh, pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang berakal”.
Sejarah dalam Al-Qur’an adalah narasi profetik transhistoris: kisah Musa melawan Fir’aun bukan sekadar peristiwa Mesir kuno, tetapi simbol perlawanan terhadap tirani sepanjang zaman. Tafsir klasik seperti Tafsir al-Tabari, al-Qurthubi, hingga Ibn Katsir menafsirkan kisah-kisah ini secara naratif-moralistik, sementara sarjana modern seperti Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd membaca kisah-kisah itu dengan pendekatan hermeneutika historis.
Menurut Arkoun, kisah sejarah dalam Al-Qur’an mengandung tawḥīdi epistemology, di mana sejarah bukan hanya “apa yang terjadi”, tetapi mengapa itu terjadi, dan bagaimana manusia dapat mengambil hikmah darinya. Maka sejarah dalam Al-Qur’an adalah tafsir ilahi atas realitas duniawi.
Historiografi sebagai Cermin Jiwa Zaman
Historiografi bukanlah cermin netral, melainkan konstruksi pengetahuan yang lahir dari konteks sosiokultural, ideologi, dan kepentingan politik. Michel Foucault menyebutnya sebagai discursive formation: sejarah adalah produk diskursus kekuasaan.
Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa tidak ada sejarah yang murni objektif. Bahkan dalam tradisi microhistory seperti Carlo Ginzburg, atau historiografi feminis seperti Joan Scott, sejarah menjadi medan narasi tandingan (counter-narrative) bagi suara-suara yang lama dibungkam.
Indonesia: Membangun Historiografi yang Mencerahkan
Indonesia memerlukan dekolonisasi historiografi. Selama ini narasi sejarah terlalu berpusat pada elite, birokrasi, dan perang. Seperti dikatakan Taufik Abdullah, kita butuh historiografi yang menggali sejarah sosial, kultural, dan spiritual masyarakat.
Menulis sejarah Indonesia tidak cukup dengan kronologi perang atau daftar presiden, tetapi juga kisah para petani, guru, santri, perempuan, dan komunitas adat. Sejarah bukan hanya milik negara, tetapi juga milik rakyat.
Dalam semangat ini, pendekatan sejarah kritis, historiografi Islam Nusantara, dan kronik lokal harus dihidupkan kembali. Kitab-kitab seperti Hikayat Banjar, Sejarah Melayu, atau Tarikh al-Fattani harus dibaca sejajar dengan Annales dan The Communist Manifesto.
Sebagai penutup, sejarah dari Herodotus hingga Al-Qur’an mengajarkan bahwa menulis sejarah bukan hanya perkara mencatat peristiwa, tetapi menafsirkan makna. Herodotus membuka jalan bagi sejarah sebagai cerita manusia. Thucydides mengajarkan ketelitian dan realisme. Hegel dan Marx menunjukkan arah sejarah dalam dialektika. Al-Qur’an menanamkan bahwa dalam setiap kisah, ada hikmah untuk yang berpikir.
Kini, saatnya kita menyusun kembali sejarah dengan semangat keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan pada kebenaran. Sebab seperti kata Ali bin Abi Thalib, “Kebenaran tidak diukur dari siapa yang berkata, tetapi dari apa yang dikatakannya.”
Dan sejarah adalah identitas kebenaran suara yang layak didengarkan.
H. Wahyu Iryana, Penulis Buku Historiografi Umum Penerbit Yrama Widya.
Terpopuler
1
PCNU Pringsewu Sosialisasikan Keputusan Munas dan Konbes NU 2025
2
3 Amalan Sunnah di Bulan Rabiul Awal
3
Doa dan Niat Menyambut Bulan Maulid
4
Maulid Nabi 5 September 2025, Ini 5 Alasan Sunnah Merayakannya
5
Jihad Pagi NU Pringsewu Digelar Kembali, Peringati Kemerdekaan RI dan Songsong Maulid Nabi
6
4 Hikmah Nabi Dilahirkan pada Hari Senin Bulan Rabiul Awal
Terkini
Lihat Semua