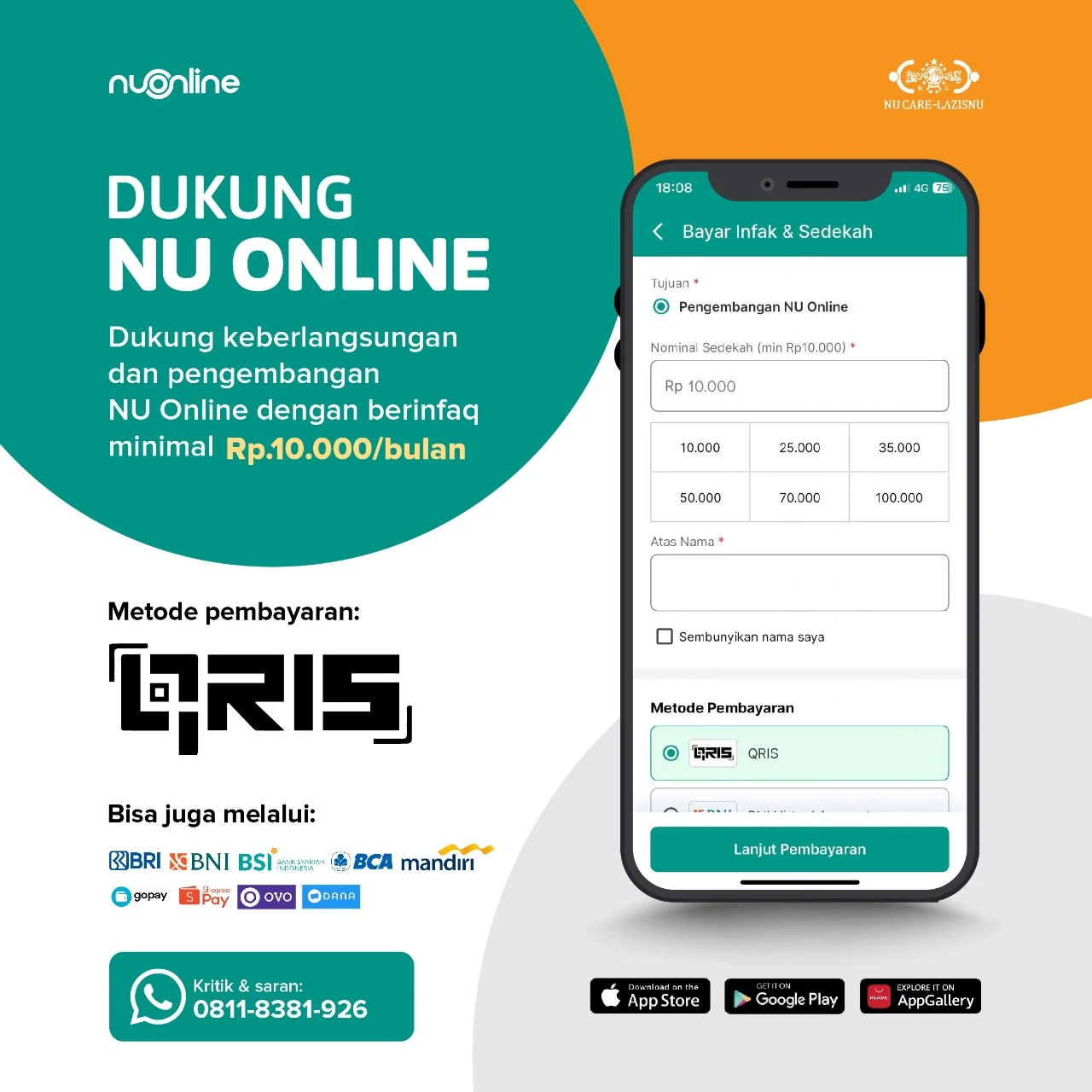Dinamika Politik dan Militer dalam Historiografi Islam: Telaah atas Kitab Futūḥ al-Buldān
Selasa, 8 April 2025 | 12:22 WIB
Wahyu Iryana
Penulis
Sejarah bukan sekadar catatan tentang masa lalu, melainkan ladang tafsir yang subur, tempat berbagai kepentingan, narasi, dan memori kolektif bertemu dalam satu lembar manuskrip. Jika kita menyelami sejarah Islam klasik, salah satu samudra yang luas untuk direnangi adalah Futūḥ al-Buldān karya Ahmad bin Yahya al-Balādhurī. Kitab ini bukan hanya catatan tentang penaklukan militer umat Islam, tetapi juga refleksi dari dinamika politik, legitimasi kekuasaan, dan diplomasi kekhalifahan Abbasiyah yang kala itu sedang dalam masa puncaknya.
Kitab ini ditulis sekitar pertengahan abad ke-3 H atau abad ke-9 M, dan menjadi semacam “buku putih” kekuasaan Islam yang membentang dari Andalusia sampai Sindh. Di balik deretan nama-nama kota yang ditaklukkan, tersimpan narasi yang kaya akan ketegangan militer, perundingan politik, hingga kompromi budaya.
Menelusuri Jejak Balādhurī
Balādhurī adalah sejarawan yang hidup di masa Kekhalifahan Abbasiyah, terutama di bawah pemerintahan al-Mutawakkil. Ia bukan prajurit, bukan pula gubernur, tapi karyanya berbicara lantang mengenai ekspansi dan militer. Sumber utama yang digunakan oleh al-Balādhurī adalah lisan para perawi, dokumen administratif, dan surat-menyurat antara panglima dan khalifah. Metodenya mirip dengan historiografi Arab klasik lainnya, seperti yang dilakukan oleh Ibn Sa'd dalam Ṭabaqāt al-Kubrā atau oleh al-Ṭabarī dalam Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk.
Namun yang unik dari Balādhurī adalah kecenderungannya yang anti-glorifikasi. Ia tidak melulu mengagungkan jihad, melainkan justru menekankan pada aspek administrasi, perjanjian damai, penarikan jizyah, dan diplomasi. Dengan kata lain, ia menghadirkan realitas yang lebih rumit daripada sekadar hitam-putih perang suci.
Politik Penaklukan atau Penaklukan Politik?
Satu hal yang menjadi pusat perhatian dalam Futūḥ al-Buldān adalah bagaimana setiap penaklukan tidak berdiri sendiri secara militer, tetapi selalu dibingkai dalam keputusan politik yang lebih besar. Misalnya, penaklukan Damaskus bukan hanya kemenangan militer Khalid ibn al-Walid, tapi juga hasil dari jaringan aliansi lokal dan perjanjian dengan elite-elite Bizantium-Suriah yang kecewa dengan Konstantinopel.
Begitu pula ketika wilayah Persia jatuh satu per satu ke tangan Islam. Balādhurī mencatat dengan rinci bagaimana administrasi lokal tetap dipertahankan. Di sinilah terlihat bagaimana Islam menaklukkan dengan politik akomodasi, bukan sekadar pedang.
Dalam kasus Mesir, ada korespondensi menarik antara ‘Amr ibn al-‘Āṣ dan Khalifah Umar ibn al-Khaṭṭāb yang menunjukkan bahwa penaklukan bukan hanya urusan ekspansi, tapi juga pertimbangan ekonomi dan stabilitas. Menurut Balādhurī, Umar bahkan beberapa kali menyuruh menghentikan ekspansi jika situasi internal umat Islam belum siap.
Narasi dari Pinggiran
Yang menarik, Futūḥ al-Buldān juga memberi ruang bagi narasi dari pinggiran tentang perlawanan lokal, tentang daerah yang menolak tunduk, atau tentang kaum Kristen dan Yahudi yang mengadakan perjanjian khusus dengan umat Islam. Dalam hal ini, Balādhurī sangat berharga bagi sejarawan kontemporer yang ingin melihat sejarah Islam dari sudut pandang non-Arab atau non-Muslim.
Misalnya, dalam penaklukan wilayah Armenia dan Transoxiana, kita bisa melihat dinamika antara Islam dan dunia Kristen Timur, termasuk negosiasi yang melibatkan bahasa Persia, Syriac, dan Armenia.
Dibandingkan dengan Historiografi Klasik Lain
Jika dibandingkan dengan karya al-Ṭabarī, maka Balādhurī jauh lebih teknokratik. Sementara Ṭabarī fokus pada kronologi dan tafsir ilahiyah sejarah, Balādhurī seperti pegawai kementerian luar negeri yang tengah menulis policy brief. Ada kejujuran administratif dalam narasinya.
Sementara itu, karya lain seperti Kitāb al-Kharāj karya Abu Yusuf lebih fokus pada tata kelola ekonomi dan perpajakan, tetapi tetap sejalan dengan spirit administratif yang diusung Balādhurī. Dalam historiografi modern, Futūḥ al-Buldān bisa disejajarkan dengan semacam "buku biru" diplomasi kekhalifahan.
Kritik dan Tafsir Ulang
Meski begitu, bukan berarti karya Balādhurī tidak memiliki bias. Ia adalah bagian dari elit intelektual Abbasiyah dan tentu saja tulisannya tak bebas dari kepentingan ideologis. Dalam beberapa narasi, peran khalifah sering ditinggikan, seakan penaklukan berhasil berkat restu dan kebijakan pusat. Ini menunjukkan bagaimana historiografi klasik berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan.
Beberapa akademisi modern seperti Fred Donner dan Patricia Crone membaca Futūḥ al-Buldān dalam bingkai “early Islamic state formation”—bahwa di balik catatan kota demi kota yang jatuh, ada upaya membangun struktur negara baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam dunia Arab.
Mengapa Ini Relevan Hari Ini
Pertanyaannya mengapa kita perlu membaca ulang Futūḥ al-Buldān hari ini, saat dunia sedang berbicara tentang AI, demokrasi digital, dan ketimpangan global? Jawabannya sederhana: karena sejarah selalu punya cara untuk menyusup ke masa kini. Di tengah krisis Timur Tengah, perang identitas, dan konflik antar negara, kita butuh melihat bagaimana peradaban Islam pernah membangun kekuasaan lewat politik kompromi, bukan hanya konfrontasi.
Kitab ini juga menjadi semacam pengingat bahwa narasi besar seperti jihad dan ekspansi tidak selalu bertumpu pada senjata, tetapi juga pada pena, diplomasi, dan kontrak sosial. Dalam dunia yang makin terpolarisasi, warisan Balādhurī mengajak kita untuk membaca sejarah dengan nalar, bukan dengan gemuruh.
Futūḥ al-Buldān bukan sekadar buku sejarah perang. Ia adalah memoar tentang bagaimana kekuasaan dibentuk, bagaimana kota-kota bertransformasi, dan bagaimana Islam menyebar bukan hanya karena pasukan, tapi juga karena sistem, perjanjian, dan kelenturan budaya. Sebuah bacaan wajib bukan hanya untuk sejarawan, tapi juga untuk politisi, diplomat, dan siapa pun yang ingin membayangkan masa depan Islam dengan menelusuri akarnya yang kompleks dan penuh nuansa.
Dan jika kita punya waktu, mari buka kembali kitab itu, di sela-sela secangkir kopi dan suara azan yang menggema dari menara kota mengingatkan kita bahwa sejarah belum selesai ditulis.
Daftar Bacaan
1. Al-Balādhurī, Futūḥ al-Buldān, edisi Beirut: Dār al-Fikr.
2. Al-Ṭabarī, Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk.
3. Abu Yusuf, Kitāb al-Kharāj.
4. Ibn Sa‘d, Ṭabaqāt al-Kubrā.
5. Fred Donner, The Early Islamic Conquests.
6. Patricia Crone, Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity.
7. Hugh Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates.
H. Wahyu Iryana, Penulis Merupakan Sejarawan UIN Raden Intan Lampung
Terpopuler
1
Amalan dan Doa Rabu Wekasan, 20 Agustus 2025
2
Membaca Surat Yasin pada Malam Rabu Wekasan, Ini Hukumnya
3
Dianjurkan Menulis 7 Ayat saat Rabu Wekasan
4
7 Golongan yang Mendapat Naungan Allah: Menjadi Calon Penghuni Surga
5
Resmikan Majelis Dzikir Al Bustomiyah, Ketua PCNU Pringsewu: Tarekat Penting di Era Kesenangan Semu
6
Membaca Pajak Lewat Kacamata Fiqih NU
Terkini
Lihat Semua