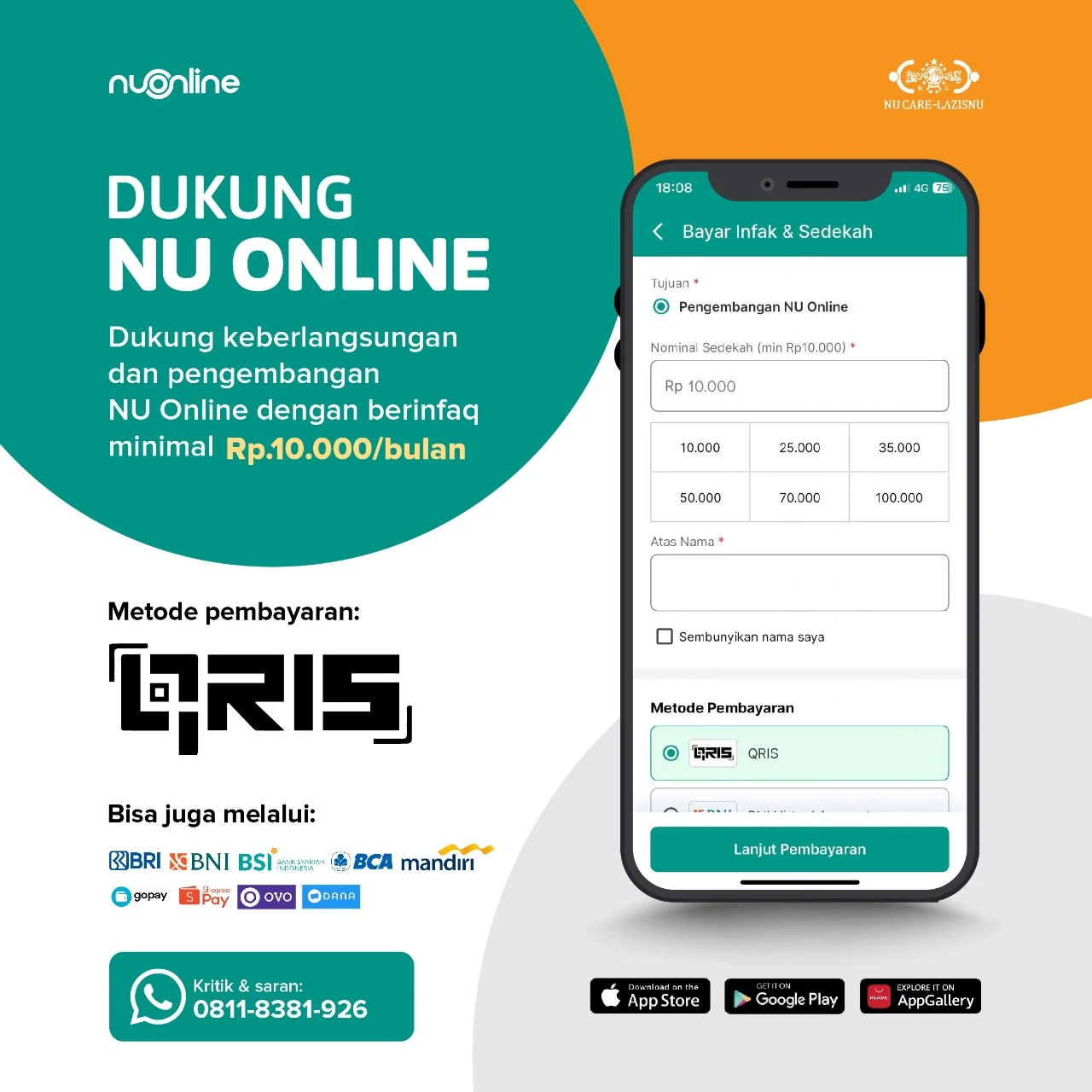Wahyu Iryana
Penulis
Kita hidup di tengah budaya serba instan. Segala hal diukur dari seberapa cepat hasil bisa diraih: kuliah ditarget empat tahun atau kurang, bisnis harus untung dalam hitungan bulan, dan politikus dihargai bukan karena gagasan, tapi seberapa sering muncul di media. Obsesi kita pada panen sering kali membutakan mata pada pentingnya proses menanam.
Tak heran jika banyak yang lebih sibuk menunggu hasil daripada merawat akar. Kita lebih terpesona pada buah ranum daripada proses fotosintesis yang sunyi. Lebih kagum pada kesuksesan tokoh ketimbang kerja keras yang berdarah-darah. Padahal, tak ada panen tanpa benih, tak ada buah tanpa akar.
Ajaran Nabi: Menanam Adalah Iman
Islam memuliakan proses menanam, baik secara harfiah maupun maknawi. Dalam banyak hadits sahih, Rasulullah saw menjelaskan betapa mulianya orang yang menanam meskipun tak sempat memetik hasilnya.
Satu hadis yang populer meriwayatkan: "Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu dari tanaman itu dimakan oleh manusia, binatang, atau burung, melainkan menjadi sedekah baginya" (HR Bukhari dan Muslim).
Hadits ini mengandung filosofi mendalam, bahwa menanam adalah amal jariah, laku memberi yang tidak minta kembali. Bahkan ketika hasilnya bukan untuk diri sendiri, Allah mencatatnya sebagai kebaikan abadi.
Baca Juga
Hukum Menyewa Pohon Buah dalam Islam
Dalam riwayat lain disebutkan: "Jika kiamat telah tiba dan di tangan seseorang ada biji kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat tiba, tanamlah" (HR Ahmad).
Bayangkan, di ambang kiamat pun Rasulullah masih menganjurkan untuk menanam. Ini bukan hanya soal pohon, tapi soal harapan. Karena menanam adalah ekspresi iman paling jujur: kita percaya bahwa meski tak sempat memetik, tetap saja ada nilai dari yang kita tanam.
Tradisi Ulama: Menanam Ilmu, Akhlak, dan Cinta
Para ulama Nusantara adalah penanam sejati. Mereka tidak hanya menanam padi atau pohon kelapa, tapi juga menanam ilmu, adab, dan keteladanan. Mereka sadar, buah dari ajaran mereka mungkin baru akan dipetik oleh generasi berikutnya.
KH Ahmad Sanusi, ulama asal Sukabumi yang pernah dipenjara kolonial, memilih menulis tafsir Al-Qur’an dalam bahasa Sunda. Ia tahu, mungkin tidak semua orang akan membaca saat itu juga. Tapi ia menanam. Dan benih itu kini tumbuh dalam bentuk tradisi pesantren Sunda yang terus berlanjut.
KH Ahmad Hanafiah dari Sukadana, Lampung Timur, adalah contoh penanam sejati. Di tengah tekanan kolonial dan ketidakpastian zaman, ia mendirikan lembaga pendidikan Islam dan mengajarkan kitab Al-Hujjah. Saat Agresi Militer Belanda 1947 terjadi, ia gugur. Ia tak sempat melihat hasil didikannya menjadi ulama besar atau tokoh masyarakat. Tapi kita tahu, benih yang ia tanam tumbuh.
Kitab Klasik dan Filosofi Proses
Dalam al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menulis, “Jika manusia terlalu berambisi pada hasil dan melupakan proses, maka kehancuran peradaban hanya tinggal menunggu waktu.” Ungkapan itu relevan hari ini, ketika kita menyaksikan banyak lembaga dan institusi tumbang karena fondasinya lemah: tak pernah dibangun dengan proses menanam yang sabar.
Kitab-kitab fiqih klasik seperti Bidayatul Mujtahid dan al-Taqrib diajarkan di pesantren dengan metode talaqqi, bukan sekadar membaca cepat, tapi menanam pemahaman mendalam. Ini menandakan betapa Islam lebih menghargai proses belajar daripada sekadar mengumpulkan ijazah atau gelar.
Modernitas dan Krisis Kebertahanan
Di era sekarang, budaya menanam ini mulai tergeser. Pendidikan dikejar dengan target, bukan dengan ketekunan. Mahasiswa dikejar deadline skripsi, tapi minim penanaman literasi. Dosen dikejar akreditasi, tapi lupa menanam karakter dan ketulusan.
Dalam dunia media sosial, kita berlomba menunjukkan hasil: foto panen, caption pencapaian, video viral. Tapi jarang ada yang menunjukkan prosesnya: pagi-pagi buta menanam, kesulitan mengairi ladang, atau sakit hati karena benih tak tumbuh. Padahal di situlah esensi kemanusiaan.
Kita menyaksikan krisis kebertahanan karena terlalu cepat ingin jadi pohon besar tanpa akar. Banyak tokoh muda yang langsung ingin dikenal luas, tapi rapuh saat diterpa ujian. Sebab ia lupa: butuh waktu untuk mengakar.
Politik Tanpa Penanaman
Dalam dunia politik, krisis ini terlihat nyata. Banyak pemimpin terpilih yang tidak memiliki rekam jejak menanam gagasan. Mereka tiba-tiba muncul menjelang pemilu, menawarkan janji manis panen, tapi tak pernah menanam kepercayaan, integritas, atau pelayanan jangka panjang. Akibatnya, publik hanya disuguhi hasil palsu dan proyek pencitraan, bukan kerja nyata.
Rakyat pun dididik untuk hanya memanen: terima sembako jelang pemilu, pilih yang memberi uang. Tapi melupakan bahwa lima tahun ke depan adalah masa menanggung akibat dari panen yang dipaksakan.
Mari Kembali Menanam
Kini saatnya kita kembali pada prinsip dasar: menanam. Menanam kejujuran di lingkungan kerja. Menanam kesabaran dalam keluarga. Menanam kasih di masyarakat yang mulai terbelah. Ini bukan pekerjaan yang langsung terlihat hasilnya. Tapi justru karena itulah ia bernilai.
Gerakan literasi di sekolah-sekolah, pesantren yang sabar membina santri tanpa pamrih, komunitas yang tanam pohon tanpa sponsor—semua adalah praktik menanam yang perlu kita dukung.
Kita tak perlu menunggu dunia sempurna untuk mulai menanam. Seperti kata Rasulullah: meskipun kiamat datang, tanamlah biji kurma itu.
Menanam sebagai Amal Abadi
Dalam tradisi Islam, sedekah jariyah adalah amalan yang terus mengalir pahalanya meski pelakunya telah wafat. Salah satu bentuknya adalah ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan, atau pohon yang meneduhkan banyak orang. Tiga hal itu tak muncul begitu saja. Ia butuh proses menanam.
Maka, siapa pun kita—guru, petani, dosen, aktivis, pelajar, bahkan politisi—marilah kita lebih giat menanam. Tak masalah jika yang memanen nanti bukan kita. Tak masalah jika kita dilupakan. Yang penting: kita telah menanam dengan cinta.
Sebaris Sair Soneta tentang Menanam dalam Senyap
Perbanyak menanam, katamu suatu hari,
meski tanahnya retak dan langit pelit hujan.
Aku percaya pada benih yang sabar,
pada tangan-tangan sunyi yang tak minta tepuk.
Kita menanam: doa, kata, peluh,
di ladang hidup yang tak pernah rapi.
Tak apa jika buahnya untuk cucu tetangga,
asal rindangnya meneduhkan siapa saja.
Biar waktu yang panen,
biar sejarah yang mencatat.
Yang penting: kau tak berhenti menanam
meski dilupakan atau diremehkan.
Satu hari nanti,
akan ada yang bersyukur atas kerja senyapmu.
H. Wahyu Iryana, Penulis Merupakan Sejarawan UIN Raden Intan Lampung.
Terpopuler
1
Lafal Bacaan Doa Nabi Ibrahim untuk Keamanan Negeri
2
14 Doa Nabi Muhammad Saw, Cocok Dibaca di Hari Maulid Nabi
3
Hukum Menjarah Rumah Orang Lain saat Unjuk Rasa
4
PCNU Pringsewu Terima Wakaf Tanah untuk Lembaga PAUD di Kecamatan Ambarawa
5
PW GP Ansor Lampung Komitmen Jaga Persatuan lewat Istighotsah dan Doa Bersama Serentak
6
NU Lampung Ketuk Pintu Langit untuk Keamanan dan Kedamaian Indonesia
Terkini
Lihat Semua