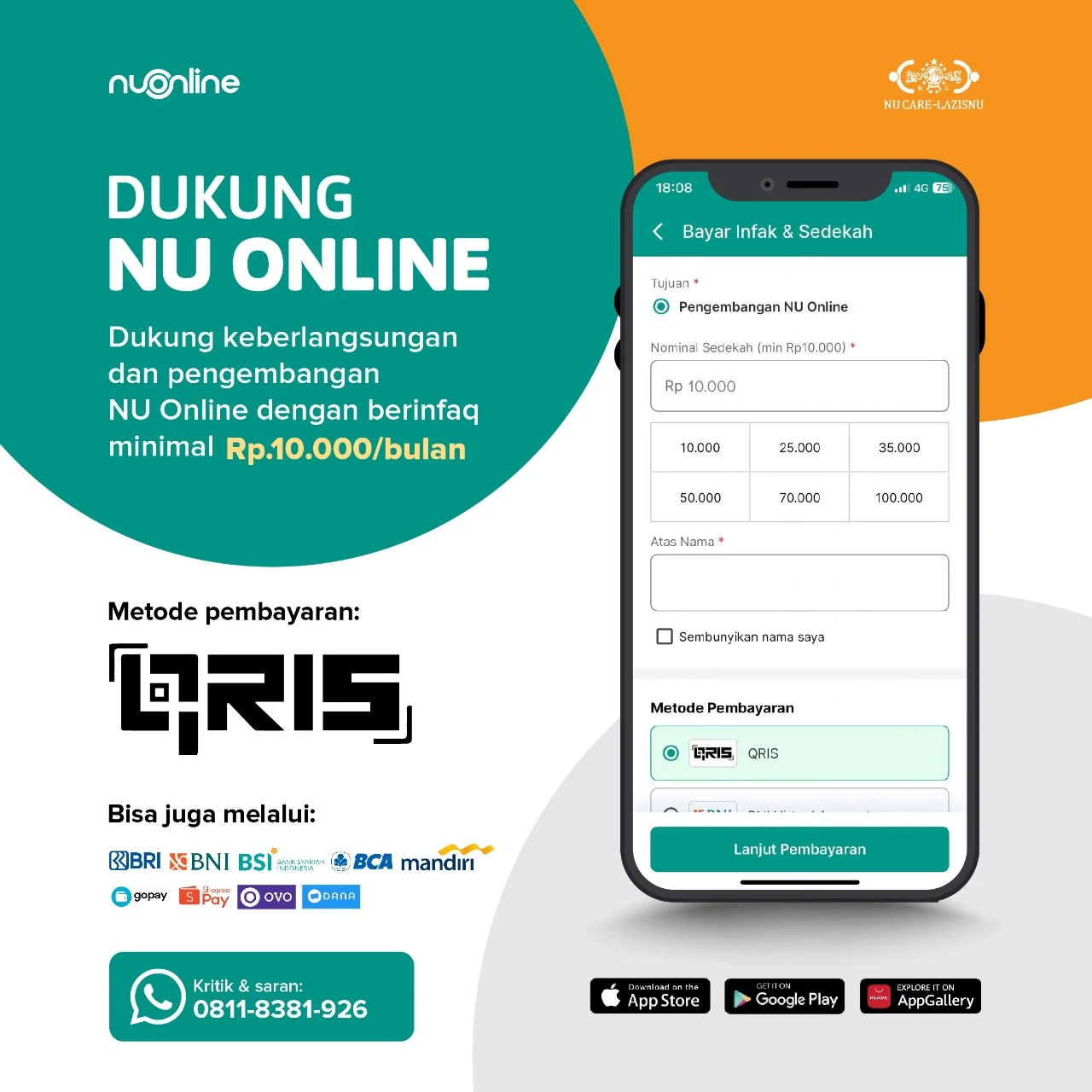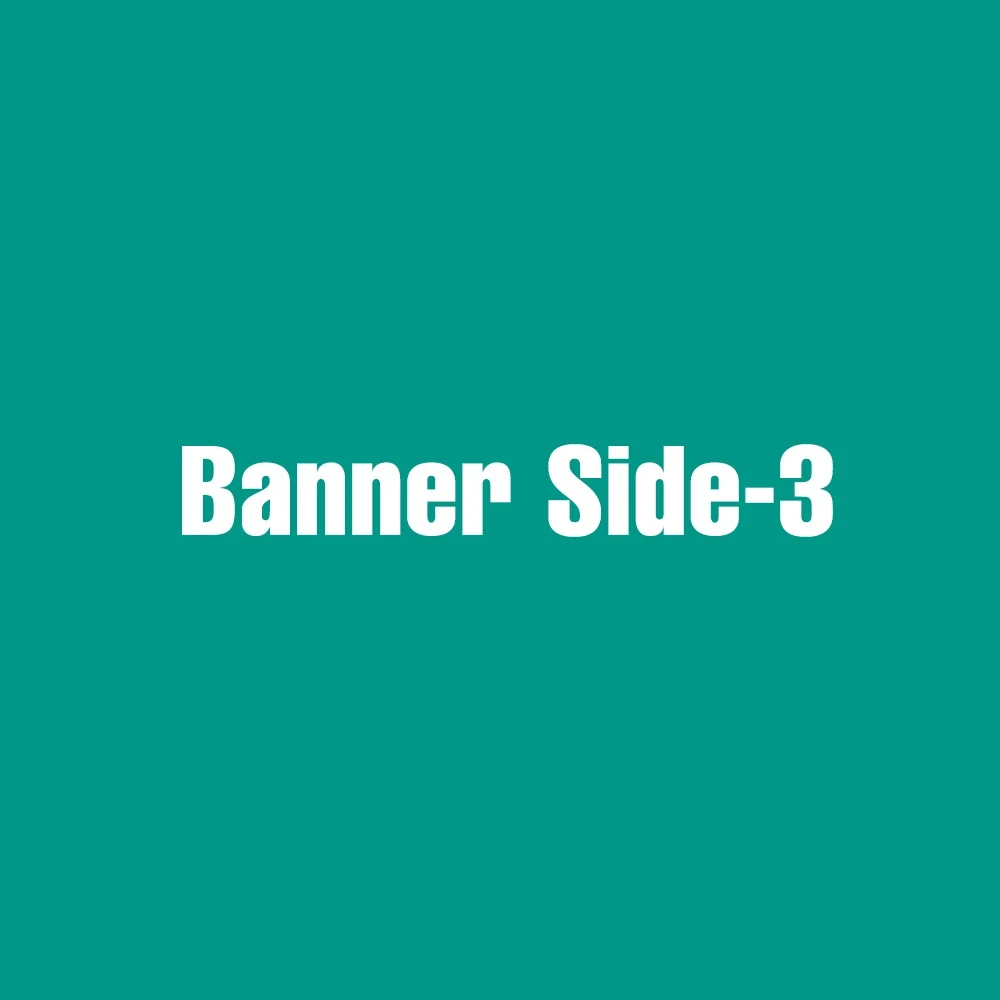Distorsi Sejarah; Kritik Sejarawan ketika Sejarah Dijadikan Alat Politik
Sabtu, 17 Mei 2025 | 16:08 WIB
Wahyu Iryana
Penulis
Di negeri ini, sejarah seringkali tidak dipelajari untuk dimengerti, melainkan digunakan untuk dimanipulasi. Ia tak lagi menjadi ruang tafakur dan kontemplasi kolektif bangsa, melainkan dijadikan tirai teatrikal yang menutupi ambisi kekuasaan para pejabat.
Para elite politik, terutama menjelang pemilu atau saat mendapat tekanan publik, kerap menjelma sejarawan dadakan. Mereka menyitir nama-nama besar masa lalu dari Bung Karno hingga Syekh Nawawi, dari Tan Malaka hingga Pangeran Diponegoro bukan untuk meneladani prinsip hidup mereka, tetapi sebagai tameng legitimasi atas agenda politik yang seringkali tak menyentuh kepentingan rakyat.
Apa yang dilakukan para pejabat kita hari ini sejatinya adalah mempraktikkan apa yang dalam nalar klasik peradaban Islam disebut sebagai al-mulk 'adhudh, yaitu kekuasaan yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan dan maslahat umat, melainkan pada kerakusan, nepotisme, dan kesewenang-wenangan. Ini adalah bentuk kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan materi dan simbol, bukan oleh etika siyasah syar’iyyah politik yang tunduk pada nilai-nilai moral dan kepentingan publik. Para penguasa jenis ini tidak malu memakai pakaian simbolik dari masa lalu seolah mereka pewaris kejayaan Majapahit, Sriwijaya, Padjajaran, Kesultanan Islam, atau Proklamator Kemerdekaan padahal tindakan dan kebijakannya sering bertentangan dengan semangat zaman yang mereka kutip.
Jika kita menengok kembali sejarah Islam pasca keruntuhan tiga kekhalifahan besar Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah kita menemukan sebuah masa yang dikenal sebagai Mulk al-Tawā’if, sebuah fase ketika dunia Islam terpecah-pecah ke dalam kerajaan-kerajaan kecil, dengan para penguasa lokal yang saling bersaing dalam simbolisme, upacara, dan klaim legitimasi.
Di masa itu, kitab-kitab sejarah penuh dengan kisah tentang penguasa yang membangun istana mewah dengan anggaran rakyat, menulis puisi tentang kebesaran mereka sendiri, menyuruh para ulama menyanjung dalam khutbah, tapi tak pernah menyentuh persoalan sosial mendasar seperti kelaparan, kemiskinan, dan ketimpangan.
Fenomena Mulk al-Tawā’if bukan hanya soal fragmentasi politik, tetapi juga krisis moral dan kepemimpinan. Para amir dan sultan dalam fase ini cenderung lebih peduli pada kehormatan pribadi ketimbang kemaslahatan umat. Mereka memperindah kota, tetapi membiarkan desa-desa hancur. Mereka membangun madrasah dengan menempelkan nama mereka, bukan sebagai amal jariyah, tapi sebagai instrumen politik. Dalam bahasa peradaban Islam, ini adalah bentuk kemunduran dari madaniyyah (peradaban berbasis keadilan dan ilmu) menjadi tahadhdhur semu kemajuan semu yang hanya terlihat dari luar, tapi rapuh di dalam.
Apa yang terjadi dalam politik kita hari ini nyaris menjadi cermin dari Mulk al-Tawā’if. Kita menyaksikan munculnya “raja-raja kecil” di berbagai daerah yang dipuja bak sultan, dengan iring-iringan adat, karpet merah, dan baliho sepanjang jalan. Mereka menyebut diri sebagai penerus semangat sejarah, padahal yang diwarisi hanyalah gaya feodal yang menyerap anggaran untuk citra, bukan untuk kesejahteraan publik. Di banyak kota, wajah pejabat lebih dikenal daripada kebijakan publiknya. Bahkan, proyek pembangunan kerap diberi nama keluarga mereka, seolah pembangunan adalah hadiah pribadi, bukan hasil pajak rakyat.
Dalam dunia Islam klasik, praktik semacam ini juga dikritik tajam oleh para ulama dan cendekiawan. Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah-nya, menyebut bahwa kekuasaan yang terlalu larut dalam simbol dan kultus pribadi akan berujung pada kemunduran. Ia menulis bahwa kekuasaan yang tidak berbasis pada solidaritas sosial (‘asabiyyah) dan prinsip keadilan akan cepat hancur. “Ketika penguasa lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada memelihara rakyat, saat itulah benih kehancuran ditanam,” begitu kira-kira pesan sang bapak sosiologi itu.
Sayangnya, pejabat kita tampaknya lebih senang menyitir kutipan para tokoh sejarah dalam pidato, tanpa membaca konteksnya. Mereka bicara tentang revolusi mental, tapi perilaku birokrasi justru semakin pragmatis dan transaksional. Mereka mengklaim melanjutkan semangat Trisakti, namun menyerahkan kedaulatan ekonomi ke tangan konglomerat dan investor asing. Bahkan, dalam peristiwa tertentu, mereka menyulap acara keagamaan atau budaya menjadi panggung personal, lengkap dengan barisan ASN yang dikerahkan untuk tepuk tangan.
Lebih miris lagi, budaya pengkultusan pejabat kian merajalela. Ada kepala daerah yang dielu-elukan seperti raja, dengan masyarakat dipaksa untuk menunjukkan loyalitas bukan pada sistem atau konstitusi, tapi pada figur tertentu. Di level pusat, praktik ini semakin terstruktur: ada yang menciptakan dinasti politik, mengorbitkan anak, menantu, atau kerabat ke jabatan strategis. Mereka menyebut ini sebagai regenerasi, tapi yang sebenarnya terjadi adalah reproduksi kekuasaan. Dalam kacamata fiqh siyasah, praktik semacam ini mencederai prinsip maslahah ‘ammah karena meminggirkan kompetensi demi hubungan darah.
Jika semua ini dibiarkan, kita akan menyaksikan lahirnya kembali bentuk kekuasaan model al-mulk al jabri kekuasaan koersif yang berdiri di atas legitimasi semu. Demokrasi hanya akan tinggal prosedur, bukan substansi. Pemilu hanya akan menjadi kontes popularitas dan kekuatan modal, bukan ruang artikulasi kepentingan rakyat. Ini adalah jebakan besar bagi bangsa yang sedang tumbuh, sebab sejarah mengajarkan kita bahwa bangsa yang terlalu sibuk membanggakan masa lalu justru rentan kehilangan masa depan.
Sudah saatnya kita membalikkan arah. Sejarah tidak boleh lagi dijadikan kosmetik kekuasaan. Ia harus kembali menjadi ruang refleksi kritis dan etika kolektif. Para sejarawan, pendidik, dan jurnalis perlu mengambil peran lebih aktif dalam melawan manipulasi sejarah yang dilakukan secara sistemik. Kampus dan ruang publik harus mendorong narasi tandingan sejarah rakyat, sejarah dari bawah, sejarah yang tidak dibungkus oleh retorika elite.
Kita juga perlu membangun tradisi siyasah syar’iyyah dalam konteks Indonesia modern: politik yang berbasis pada keadilan sosial, partisipasi rakyat, dan tanggung jawab moral. Bukan politik basa-basi, bukan politik pencitraan. Sudah terlalu lama rakyat kita disuguhi drama kekuasaan, sementara kebutuhan dasar mereka diabaikan. Sudah terlalu sering mereka dijadikan komoditas elektoral, tapi dilupakan setelah suara didapat.
Dalam tradisi Islam, seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang banyak menampilkan simbol-simbol kesalehan atau silsilah agung, tapi mereka yang takut pada Allah dan bergetar ketika menyebut rakyat. Nabi Muhammad saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” Hadis ini bukan slogan, tapi prinsip moral yang seharusnya menjadi standar etik setiap pejabat publik, dari tingkat kelurahan hingga istana.
Penutupnya, mari kita jaga warisan sejarah bangsa ini dari tangan-tangan yang hendak menjadikannya alat politik. Sejarah adalah milik bersama, bukan properti elite. Ia adalah cermin, bukan topeng. Dan bila kita terus membiarkan sejarah dipakai untuk menyembunyikan wajah aslinya kekuasaan, maka kita akan kehilangan orientasi sebagai bangsa. Karena bangsa yang tak jujur melihat masa lalunya, hanya akan tersesat dalam masa depan yang semu.
Baca Juga
NU dan Sejarah Berdirinya
Wahyu Iryana, Sejarawan UIN Raden Intan Lampung.
Terpopuler
1
PCNU Pringsewu Sosialisasikan Keputusan Munas dan Konbes NU 2025
2
3 Amalan Sunnah di Bulan Rabiul Awal
3
Doa dan Niat Menyambut Bulan Maulid
4
Maulid Nabi 5 September 2025, Ini 5 Alasan Sunnah Merayakannya
5
Jihad Pagi NU Pringsewu Digelar Kembali, Peringati Kemerdekaan RI dan Songsong Maulid Nabi
6
4 Hikmah Nabi Dilahirkan pada Hari Senin Bulan Rabiul Awal
Terkini
Lihat Semua