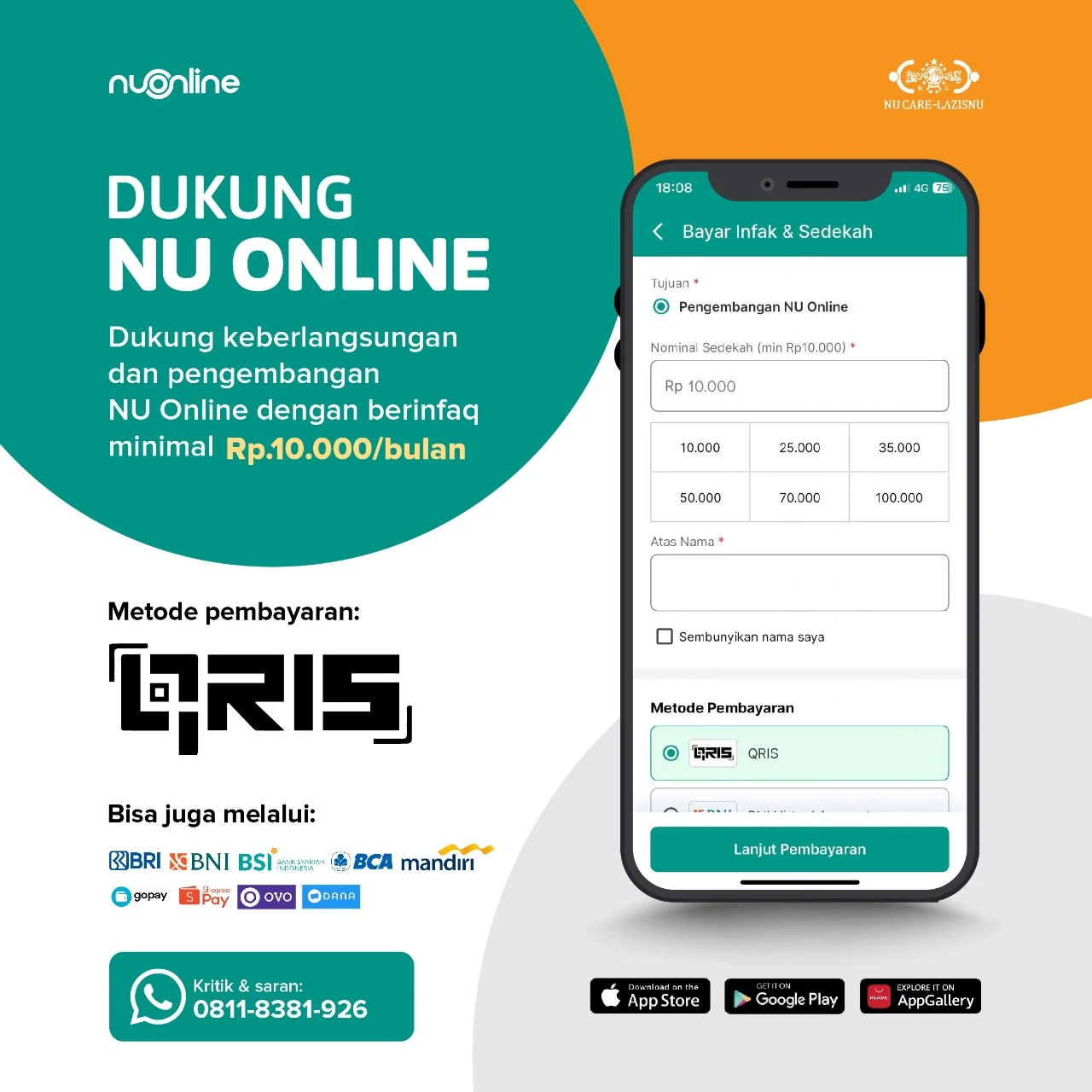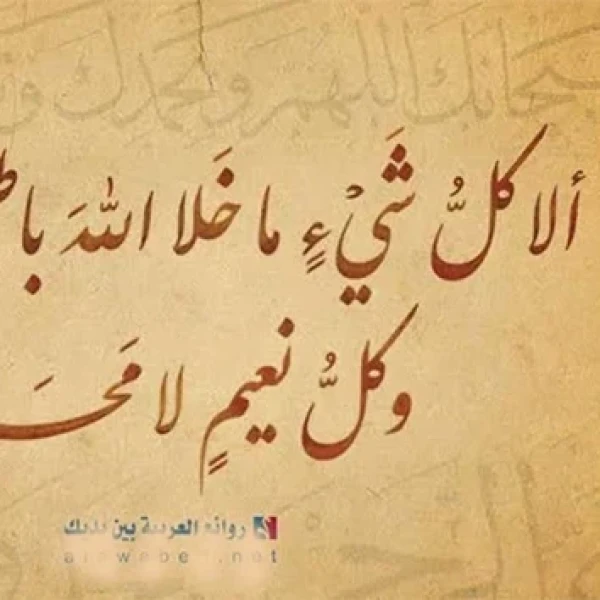Cerpen Riqqi Ramadhan
Aku baru saja tersadar, entah dari tidurku atau, dari pingsanku. Aku tak ingat apa-apa lagi setelah peristiwa itu. Seperti gerombolan burung yang hinggap di ranting pohon lalu datang seorang bocah dengan ketapel di tangannya. Trass... semuanya terbang berhamburan ke angkasa. Hilang.
Tak ada yang bisa aku ingat lagi. Yang jelas sekarang kepalaku terasa sakit. Rasanya, kepalaku baru saja dihantamkan ombak laut yang sedang pasang pada batu karang di tepi pantai. Aku juga merasakan sakit dan perih di sekujur tubuhku. Pun di kedua lengan dan kakiku.
Ruangan di sekitarku gelap. Tak ada setitik cahaya pun. Meskipun aku sudah sadar sesadar-sadarnya. Sebenarnya, di mana aku berada? Apa sekarang aku sudah mati? Kapan maut menjemputku? Kenapa aku tidak menyadarinya? Kalau memang aku sudah mati, apa ini yang namanya alam barzakh? Ya, sepertinya aku sering mendengarnya.
Biasanya orang-orang sering membicarakannya saat sehabis pulang dari pengajian bulanan.
“Kata kiai, semua yang hidup itu bakalan mati. Dan setelah mati kita akan tinggal di alam barzakh. Dan katanya, alam barzakh itu gelap. Tak ada teman. Pengap dan sempit. Dan lagi kita akan tinggal di sana sampai hari kiamat tiba,” kata seorang dengan kopiah putih. Merinding.
“Lalu, akan datang dua malaikat yang berwajah sangar. Yang tidak bersahabat sama sekali,” lanjut seorang yang lainnya.
“Ya, kemudian mereka akan mengajukan banyak pertanyaan. Siapa yang tak bisa menjawab, maka tak ada ampun baginya,” sambung orang yang berkopiah putih tadi, sembari membetulkan posisi kopiahnya.
Tak ada angin berhembus di ruangan ini. Pengap. Sangat sulit rasanya untuk sekedar bernapas. Apalagi bergerak. Dan sepertinya aku mendengar deru nafas seseorang di samping kanan dan kiriku. Adakah orang lain di ruangan ini selain diriku?
Tapi perhatianku teralihkan karena tiba-tiba aku melihat setitik cahaya di kejauhan sana. Semakin lama cahaya itu semakin besar dan terang. Cahaya itu berjalan kearahku. Lalu, terdengar pula suara mengiringi cahaya itu.
Klotak...klotak...klotak...
Tiba-tiba ingatanku kembali. Utuh. Seperti gelas yang semula kosong kemudian dituangkan air hingga penuh kembali.
“Kalian tahu tidak kalau kiai punya terompah yang keramat?” kata Mamad, salah seorang teman sekamarku di pondok.
“Emangnya kamu tahu dari siapa?” timpalku tidak percaya, “Shahih nggak tuh kabar?” lanjutku, menyelidik.
“Jangan-jangan cuma kabar burung-burung sawah yang kelaparan tuh atau mungkin kamu cuma nge-dongeng lagi,” timpal teman yang lain, namanya Darso.
“Ya, kamu kan jago-jagonya pendongeng di seantero pondok ini.” Terdengar tawa Darso menggema di dinding-dinding kamar. Mamad menekuk mukanya. Marah.
“Ya sudah kalau kalian tidak percaya!” Tandas Mamad ketus.
Aku dan Darso tertawa melihat Mamad yang tertekuk wajahnya karena marah. Kemudian kami berpelukan dalam gelak tawa. Seekor cicak yang bersemayam di belakang gambar kaligrafi nongol setengah kepalanya, menyaksikan keakraban kami.
Kami bertiga adalah santri di sebuah pondok pesantren di Madura. Kami berasal dari daerah yang berbeda, kecuali Aku dan Darso yang memang berasal dari satu desa di Madura.
Sedangkan Mamad adalah seorang santri yang berasal dari Pulau Jawa yang sudah lihai berbahasa Madura sejak lahir, karena nenek moyangnya memang orang Madura yang pergi merantau dulu, sehingga tak perlu repot-repot kami ajari lagi untuk berbicara bahasa Madura. Madura swasta, begitu kami istilahkan.
***
Cerita Mamad tentang sandal kiai selalu terngiang di pikiranku, meskipun pada awalnya aku tak mau percaya dengan dongeng hayalannya itu. Tapi ucapan Mamad seperti mantra. Semakin aku berupaya tidak memercayainya semakin lekat keimanan tentang cerita itu di hatiku.
Akhirnya, diam-diam aku selalu mendengarkan ocehannya tentang sandal keramat itu kepada teman-teman yang lain. Konon, sandal keramat itu adalah milik Kiai Sulaiman, pendiri pesantren yang aku tempati saat ini, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga sampai pada keturunan terakhir saat ini, Kiai Khidir.
Kata Mamad, seperti apa yang sering ia ceritakan, “Siapa yang memakai sandal itu ia akan dapat berjalan di udara, seperti halnya Nabi Sulaiman dengan permadaninya.” Ia selalu saja memasang wajah serius kalau sedang mendongeng. Sebab itulah kenapa dongengnya selalu mendapat banyak perhatian.
“Dan lagi, sandal keramat itu,” kata Mamad, “Bisa menjadikan perjalanan yang jauh menjadi singkat. Makanya, Kiai Khidir selalu tidak tampak saat shalat jumat, alasannya karena Kiai Khidir shalat jumat di Masjidil Haram, Mekah. Di tempat Ibrahim membangun Ka’bah, kiblat kita saat ini. Dan tempat Allah mencurahkan zamzam untuk Ismail kecil yang kehausan,” lanjutnya dengan ekspresinya yang meyakinkan.
Kisah-kisah seperti itu yang selalu ia ceritakan kepada teman-temannya, tak terkecuali aku dan Darso. Sampai suatu ketika Mamad datang dengan tergesa-gesa. Membangunkanku yang sedang tidur pulas. Ia datang bersama Darso yang sambil memutar tasbihnya, begitulah kebiasaannya.
Baca Juga
Cerpen : Ustadz Miring Kampung Kami
“Jon, Jono, bangun!” dasar tukang molor,” teriak Mamad sambil memanggil namaku, Jono, Ahmad Jono. Darso hanya tersenyum memperhatikan.
“Ada apa Mad?” balasku malas.
“Pokoknya kamu harus bangun dan dengarkan cerita tentang bukti kebenaran dongeng sandal keramat kiai.”
Baca Juga
Cerpen : Mencintai Pembunuh Itu
Mendengar pernyataannya, entah karena apa rasa kantukku tiba-tiba lenyap dari pelupuk mataku. “Emang apa buktinya?” tanyaku.
“Kau lihat tanah yang basah itu? Tadi sebelum hadiran dimulai dan kamu masih saja molor, hujan turun deras sekali.” Mamad menarik napas, “Lalu terdengar suara klotak...klotak...klotak...
Kau tau apa yang terjadi setelah itu? Hujan berhenti seketika, setetes pun tak ada. Dan cuaca cerah seketika. Seperti siang hari pada musim kemarau. Padahal sebelumnya, cuaca gelap gulita. Awan hitam menyelimuti seluruh permukaan bumi.
Kemudian terlihat Kiai Khidir berjalan menuju mushalla untuk mengimami shalat jamaah. Shalat jamaah pun dilaksanakan. Dan setelah selesai mengimami shalat jamaah beliau langsung kembali ke dhalem.
Tatkala beliau sudah masuk ke pekarangan dhalem,” Mamad berhenti sejenak, “Hujan turun kembali. Deras. Bahkan lebih deras dari sebelumya disertai angin kencang dan petir yang menyambar keras.
Banyak santri yang menjadi saksi kejadian itu. Termasuk aku dan Darso. Kami menyaksikan dengan mata kami sendiri. Hujan deras itu berhenti karena mendengar suara sandal keramat Kiai Khidir,” Mamad menghentikan ceritanya.
Setelah mendengar cerita itu, hatiku seperti mendapat charger. Keimananku bertambah kuat. Dan semenjak saat itu juga rasa penasaranku tak dapat kutahan. Aku ingin membuktikan. Aku ingin mencoba. Dan aku ingin memiliki.
***
Sebenarnya keimananku ini berawal dari suatu peristiwa yang hanya aku dan Tuhan yang menyaksikannya dan tak pernah kuceritakan kepada siapapun. Semua cerita Mamad itu sebenarnya hanya kelanjutan dari rasa penasaranku setelah peristiwa itu.
Begini ceritanya. Pada suatu malam, tepatnya malam Jumat sekitar pukul 23.53, aku berjalan tepat lewat di depan pagar dhalem Kiai Khidir. Suasana hening dan gelap gulita, entah apa penyebabnya lampu mercury yang terletak di seberang jalan dhalem kiai mati. Sehingga pupil mataku membesar untuk mengumpulkan segenap cahaya yag ada.
Namun tiba-tiba mataku silau. Sebuah cahaya yang sangat terang melintas di depanku menembus pagar besi dhalem Kiai Khidir. Karena penasaran, aku mendekat dan mengintip dari celah-celah kecil pagar besi itu. Aku terkejut sebelum akhirnya cahaya itu menyilaukan mataku kembali. Aku melihat sayap-sayap putih bercahaya terbang ke angkasa.
***
Sekarang adalah malam Jumat. Rupanya hasratku tidak padam juga. Dari cerita Mamad bahwa sandal keramat itu hanya dipakai pada malam Jumat hingga Jumat malam saja. Hadiran masih berjalan satu rakaat, tanpa seorang pun tahu aku sudah berada sekitar dua meter dari jarak sandal keramat itu. Aku melesat ketika semua orang tenggelam dalam sujud.
Selangkah lagi aku telah sampai tepat di tempat sandal keramat itu. Terdengar suara yang memekakkan telingaku. Aku menoleh. Dua orang berbaju hitam dengan sayap hitam pula diselimuti kilat petir menatap tajam ke arahku. Rupanya suara petir itulah yang memekakkan telingaku. Lalu, cahaya di sekitarku meredup seketika, sayap-sayap itu seperti benda magis yang memiliki kekuatan menyerap cahaya.
Tanpa aba-aba, aku telah melesat. Berlari ketakutan. Detak jantung memompa darahku dengan cepat. Aku terus berlari hingga tiba di ujung lorong pesantren, melompati pagar. Lalu, berlari menyusuri persawahan yang terletak dibelakang pesantren.
Aku mencoba menerobosnya dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Cahaya rembulan, satu-satunya penerang jalanku, semakin lama semakin meredup. Hingga akhirnya gelap gulita.
***
Aku baru saja tersadar, entah dari tidurku atau, dari pingsanku. Aku tak ingat apa-apa lagi setelah peristiwa itu. Seperti gerombolan burung yang hinggap di ranting pohon lalu datang seorang bocah dengan ketapel di tangannya. Trass.. semuanya terbang berhamburan ke angkasa. Hilang.
Tak ada yang bisa aku ingat lagi. Yang jelas sekarang kepalaku terasa sakit. Rasanya, kepalaku baru saja dihantamkan ombak laut yang sedang pasang pada batu karang di tepi pantai. Aku juga merasakan sakit dan perih di sekujur tubuhku. Pun di kedua lengan dan kakiku.
Ruangan di sekitarku gelap. Tak ada setitik cahaya pun. Meskipun aku sudah sadar sesadar-sadarnya. Sebenarnya, di mana aku berada? Apa sekarang aku sudah mati? Kapan maut menjemputku? Kenapa aku tidak menyadarinya? Kalau memang aku sudah mati, apa ini yang namanya alam barzakh?
Tak ada angin berhembus di ruangan ini. Pengap. Sangat sulit rasanya untuk sekedar barnapas. Apalagi bergerak. Dan sepertinya aku mendengar deru nafas seseorang di samping kanan dan kiriku. Adakah orang lain di ruangan ini selain diriku?
Tapi kemudian perhatianku teralihkan karena tiba-tiba aku melihat setitik cahaya di kejauhan sana. Semakin lama cahaya itu semakin besar dan terang. Cahaya itu berjalan ke arahku. Lalu, terdengar pula suara mengiringi cahaya itu. Klotak...klotak...klotak...
Ya, itu suara sandal Kiai Khidir yang berjalan ke arahku.
“Bersihkan hatimu, Nak!” seru Kiai Khidir seraya menunjuk dadaku, “berdzikirlah! Itulah kuncinya. Ingat Allah selalu dekat denganmu,” lanjut beliau, seraya berlalu meninggalkanku.
Lalu semuanya kembali gelap gulita.
Annuqayah
April 2018
“Tulisan ini merupakan juara kedua dalam lomba cerpen Harlah laman nulampung.or.id”
Riqqi Ramadhan adalah anak tunggal dari pasangan Junaidi dan Azizatun yang lahir di Desa Cangkreng, Sumenep, Jawa Timur pada tahun 1999. Saat ini sedang mendalami ilmu agama di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Annuqayah Latee, Sumenep, Kabupaten paling Timur di Pulau Madura.
Terpopuler
1
Lafal Bacaan Doa Nabi Ibrahim untuk Keamanan Negeri
2
14 Doa Nabi Muhammad Saw, Cocok Dibaca di Hari Maulid Nabi
3
Hukum Menjarah Rumah Orang Lain saat Unjuk Rasa
4
PCNU Pringsewu Terima Wakaf Tanah untuk Lembaga PAUD di Kecamatan Ambarawa
5
PW GP Ansor Lampung Komitmen Jaga Persatuan lewat Istighotsah dan Doa Bersama Serentak
6
NU Lampung Ketuk Pintu Langit untuk Keamanan dan Kedamaian Indonesia
Terkini
Lihat Semua