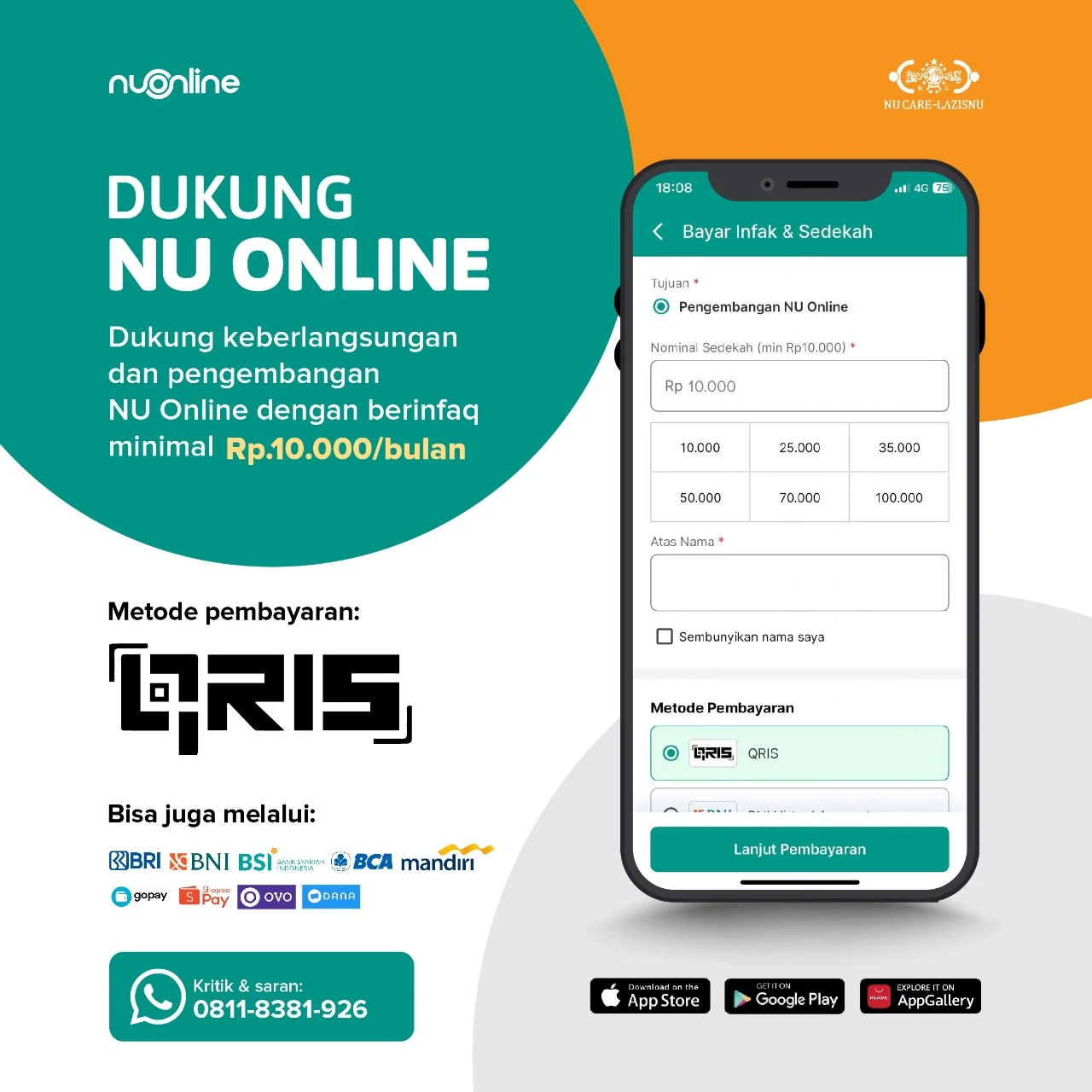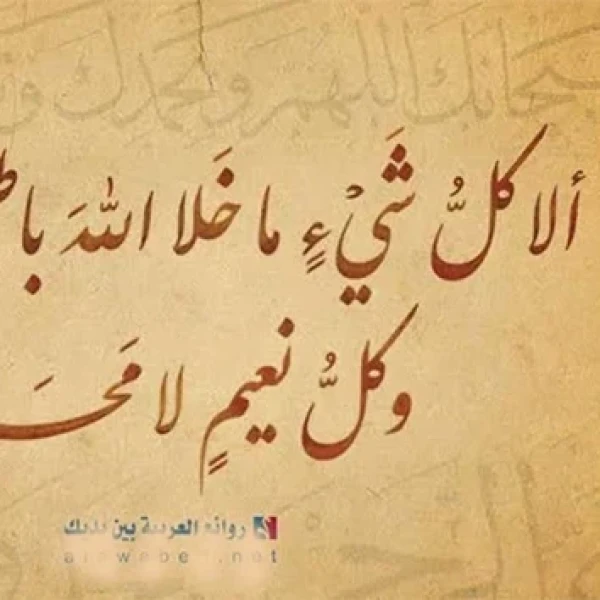Cerita Pendek Agus Kindi
Mereka menyebutnya sebagai Ustadz Kepala Miring. Dia hanya tertawa tiap kali mendengar namanya disebut demikian. "Pada kenyataannya kepala Ali memang miring. Tak bisa lagi Ali tegakkan seperti orang lain," katanya tanpa bermaksud membela diri.
"Semuanya sudah jadi bagian takdir Allah yang harus Ali terima dan Ali syukuri," katanya pendek.
Orang-orang jadi segan untuk bertanya, sejak kapan kepalanya menjadi miring seperti itu. Kepala itu benar-benar terkulai, menempel pada bahu sebelah kanan. Beberapa anak mencoba menirunya memiringkan kepala, lantas menyadari betapa tersiksanya melihat segalanya dengan posisi kepala yang miring.
Sebenarnya namanya Ali Mualim. Dia datang bersama dua temannya, Amir dan Hasan dari sebuah pesantren di Pulau Jawa.
Kampung Tirta merupakan sebuah perkampungan kecil yang terletak diantara dua sungai besar. Sungainya yang deras masih menyimpan banyak sumber hidup.
Namun setelah satu persatu tetua kampung mangkat, mengaji dan bersembahyang seolah tak penting lagi.
"Kalau kepalanya sudah lurus, saya akan belajar mengaji siang dan malam dengan ustadz baru itu," seloroh seorang pemuda kampung sambil tertawa gelak-gelak.
"Kalau dia yang jadi imam sembahyang, apa kita juga ikut-ikutan miringin kepala?" sambut yang lain.
Karena sifat acuhnya itu beberapa orang jadi geram menembus kesabaran hati Ustaz Ali. "Hatinya sudah membatu. Omongan jelek apapun tak mempan lagi," kata seorang yang sok tahu.
"Telinganya sudah tuli karena kepalanya yang miring itu," sambut yang lain.
Namun orang tua yang lebih bijak berkata, "Hati orang-orang yang lurus seperti Ustadz Ali sudah dilindungi oleh malaikat-malaikat dari segala bentuk kemarahan."
"Sebagai kepala kampung, Pak Muh jangan asal menerima sembarang orang asing. Memangnya nggak lihat berita-berita di televisi? Kedoknya saja ustadz atau ahli agama, tapi nyatanya mencuci otak anak muda dengan aliran-aliran agama yang enggak benar!" Pak Yanuar, pemilik koperasi simpan pinjam itu berkata provokatif.
"Terlalu berprasangka itu namanya Pak Yanuar. Kalau semua pendatang kita curigai begitu, tak ada lagi yang datang ke kampung kita ini. Mushala dan madrasah kampung ini sudah lama terbengkalai," timpal Bu Arum, istri kepala kampung. Dia yang sudah paham tabiat mulut Pak Yanuar jadi ikutan sebal.
Bu Arum bergegas masuk, meninggalkan Pak Yanuar yang masih nyerocos di depan Pak Muh, suaminya.
***
Saya akan mengingat hari pertama kedatangannya. Anak-anak kecil tertawa cekikikan, berbisik satu sama lain. Di halaman mushala ini, Pak Muh sebagai kepala kampung mengumpulkan warga untuk menyambut tiga orang pemuda yang akan mengisi madrasah dan mushala yang sudah lama terbengkalai.
Kehadiran orang asing selalu menarik perhatian. Apalagi kali ini ada seorang laki-laki yang aneh karena kepalanya miring.
Mushala An-Nur namanya. Dibangun di atas lahan bekas gudang arang di pinggir sungai. Bentuknya kecil, makin kusam karena tak pernah dirawat.
Sebuah beduk kulit sapi terletak di sudut, tak pernah lagi ditabuh. Cat dindingnya yang putih mulai terlihat kotor karena bekas banyak noda yang ditinggalkan. Amplifier dan pengeras suara yang rusak jadi alasan mengapa azan tak terdengar lagi.
Tak ada yang tahu dan mungkin tak mau tahu, apa yang dikerjakan tiga pemuda asing itu setelah orang-orang pulang dan malam merangkak menuju pagi.
Subuh itu orang-orang terjaga dengan perasaan ganjil. Suara azan subuh merdu berkumandang. Suara siapa yang demikian lembut nan menghanyutkan. Terasa syahdu di udara pagi yang dingin.
Bukan, itu bukan suara tape recorder yang biasanya dipasang untuk menandakan waktu sembahyang. Kenapa suara azan itu tak terdengar putus-putus?Amplifier dan pengeras suara mushala setahu orang-orang sudah lama rusak.
Pintu-pintu dibuka. Langkah-langkah penasaran bergerak menuju halaman mushala, berusaha menjenguk si pemilik suara azan indah itu.
Tentu satu di antara tiga pemuda dari pesantren itu, pikir mereka. Tapi siapa? Cahaya lampu dari dalam mushala tampak menyala terang. Dalam remang subuh yang masih gelap, dari kejauhan mushala itu tampak seperti kunang-kunang.
Pak Muh yang turut penasaran itu pun terkejut. Sebagai pemegang kunci mushala dia tahu betul amplifier dan bohlam yang ada di mushala sudah tak lagi bisa dipakai.
Wajah-wajah muncul di halaman mushala masih berbalut sarung. Tapi mereka tak hendak bergabung bersama saf shalat subuh di mushala itu. Mereka cukup tahu sekarang, siapa si pelantun azan. Seorang laki-laki berkepala miring dengan sebuah toa di tangannya.
***
"Ali bisa diandalkan kalau membetulkan alat-alat listrik, Pak Muh. Tadi malam Ali yang berinisiatif membetulkan lampu karena ada kabelnya yang putus. Tapi amplifiernya tak bisa dibetulkan karena ada beberapa elemennya yang harus diganti," kata Hasan.
"Toa yang dipakai Ali ini nantinya buat alat pelengkap di madrasah, Pak Muh."
Pak Muh manggut-manggut.
"Ibu-ibu di warung tadi membicarakan azan subuh itu loh, Nak Amir. Banyak yang enggak percaya itu suaranya si Ali. Loh, mana dia?" tanya Pak Muh.
"Sedang membersihkan bak wudhu agar bisa dipakai lagi, Pak. Sudah lama tak dipakai jadi kotor dan berlumut," jawab Hasan.
"Itu dia, Nak Amir. Mushala ini belum menggunakan kran yang praktis. Masih mengandalkan air sumur yang harus ditimba. Atau kalau mau berjalan sedikit di dekat sungai ada pancuran umum. Tapi anak-anak nakal suka usil menaruh sampah di sana..."
Harun muncul ke dalam mushala dengan membawa senampan kue dan makanan kering pemberian beberapa ibu-ibu yang datang.
"Saya tak menyangka suaranya saat azan indah sekali..."
"Ali itu penghafal Qur'an, Pak Fuad. Ilmunya luas. Beberapa kali mewakili pesantren untuk perlombaan tilawah tingkat propinsi," jawab Amir.
"Dia anak yang baik. Banyak orang mencemoh fisiknya tapi tak mengenal pribadinya yang tulus. Meskipun kepalanya miring, tapi insya allah, hatinya lurus," sambung Hasan.
Dimulai hari itu rangkaian cahaya mulai melingkari saya. Dibantu beberapa warga yang mulai simpatik serta anak-anak, Mushola An-Nur mulai dibenahi.
Jendela yang engselnya mulai berkarat dibuka lebar dan diminyaki, kaca jendela yang kusam digosok hingga berkilat. Karpet, tikar dan sajadah yang berdebu dibawa anak-anak ke tepi sungai untuk dicuci.
Atap yang digenangi sawang dan jaring laba-laba tak luput untuk dibersihkan. Bak wudhu dibersihkan lalu mulai diisi, mimbar digosok dan amplifier mulai diperbaiki.
"Kenapa tak ada lagi yang pernah shalat di mushala ini, Pak?" tanya Ustaz Ali.
"Semua sibuk bekerja, Nak Ali. Mungkin tak sempat lagi berjalan kaki untuk shalat berjamaah di sini."
"Mushola ini tak terawat. Siapa yang membangunnya, Pak Muh?" tanya Amir.
Pak Muh terdiam sejenak. "Nak Ali mungkin harus dengar cerita ini…”
"Cerita apa Pak?"
"Tentang Han. Dia jagoan kampung ini. Sudah tiga tahun dia pergi dan tak ada yang tahu keberadaannya. Han adalah cucu dari Wak Hamzah, pemilik tanah mushala ini. Dulunya ini gudang menyimpan arang.
Tiga tahun lalu Wak Hamzah mewakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid atau mushala. Wak Hamzah sangat dihormati di kampung ini. Dia juga tahu kelakuan Han dan teman-temannya yang sudah menyalahgunakan gudang ini.
Han bersama teman-temannya kerap mabuk dan mengacau. Kabar yang beredar Han sudah membunuh orang lalu buron, sampai saat ini. Orang-orang takut Han kembali dan menuntut tanah wakaf ini.”
"Kamar gudang di samping mushala itu adalah kamar yang sering ditempati Han. Sewaktu mushala ini dibangun, seperti tempat keramat saja tak ada yang berani menghancurkan kamar gudang itu.”
***
Tiga bulan sejak kedatangannya, orang-orang mulai memanggilnya Ustadz Ali. Meski sedari awal dia enggan dipanggil demikian karena merasa belum pantas. Tapi setidaknya panggilan itu lebih baik ketimbang sebutan Ustadz Kepala Miring. Jika ada anak yang keceplosan maka anak-anak yang lain akan membeliakkan mata.
Amir dan Harun tak lagi menemani Ustadz Ali. Amir diminta menjadi pengurus madrasah di kampung seberang. Sementara Harun berdakwah di daerah lain. Wajah Amir sesekali muncul di Mushala An-Nur.
Ustadz Ali yang menjadi salah satu pengajar di madrasah yang terletak di seberang sungai akan menyeberangi sungai setiap pagi dan kembali di waktu petang.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu di kampung ini mulai menyukainya. Di akhir pekan Ustadz Ali datang menjenguk para tetua kampung yang masih hidup. Hal itu ternyata menghangatkan hati mereka dan membuat banyak orang simpatik. Bahkan Pak Yanuar yang sedari awal bersikap sinis, perlahan sifatnya mulai mengendur.
Satu persatu wajah-wajah baru berani muncul di pintu mushala saat waktu maghrib untuk ikut belajar membaca hijaiyah. Dia tak hanya mengajari anak-anak mengaji, tapi juga ilmu tajwid, kaligrafi dan suka berkisah tentang kisah nabi dan para sahabatnya.
Namun, suatu hari…
“Robbisrohli sodri, wa yassirli amri, wah lul uqdatan min lisani, yafqohu qouli...”
Tok, tok...Prangg!
Anak-anak yang baru saja menutup Iqro dan Al-Quran tersentak. Beberapa buah batu terlontar menembus kaca jendela. Susul menyusul.
Baca Juga
Cerpen : Mencintai Pembunuh Itu
Anak-anak mulai menjerit karena tiba-tiba seseorang menerobos pintu mushala dengan kasar. Sosok pria jangkung berambut gondrong dengan penampilan setengah mabuk sempoyongan, lalu tangannya menunjuk-nunjuk. Wajahnya merah.
Han.
"Siapa yang mengizinkan tempat ini berdiri di tanah ini heh?!” Han berkacak pinggang.
"Gua ahli waris tanah ini. Jadi enggak ada yang punya hak ngebangun apapun di atas tanah ini. Dan elu siapa? Pahlawan baru kampung ini?" Han menatap nyalang ke arah Ustadz Ali.
"Astaghfirulloh," Ustaz Ali menyeruak maju ke hadapan tampak tak gentar. "Kita bicarakan baik-baik di luar. Anda sedang mabuk..."
"Lu nantangin gua hah? Elu tahu siapa gua di kampung ini, heh? Gua jagoan kampung. Lu mau coba?!" Tangan Ustaz Ali ditepis.
Tubuh Han sempoyongan. Dia memukul dadanya berkali-kali. Tiga anak-anak yang paling besar membantu Ustadz Ali bangun. Menjauhkan Ustadz Ali dari jangkauan Han.
"Lu cepat angkat kaki dari kampung ini, keparat. Sebelum hidup lu sia-sia dan gua bertindak lebih jauh,” ancam Han.
Terdengar langkah-langkah kaki. Beberapa warga menerobos masuk. Beberapa orang memberangus Han yang memberontak. Mereka menggeret Han keluar.
Entah apa jadinya jika Han berada di kondisinya yang normal. Tak ada yang berani mendekat, karena Han punya senjata tajam yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Dua pisau berkilat di saku celananya.
Han tambah meracau saat tubuhnya digeret paksa keluar. Anak-anak masih tampak ketakutan.
Setelah malam kehadiran Han yang mengamuk di mushala, dia tak lagi muncul sebab beberapa warga membawanya ke tempat yang aman.
"Kemana Han? Kenapa tidak dilaporkan saja pada polisi..."
"Han itu nekad bisa melakukan hal-hal gila dan tak kenal takut. Kalian belum lupa bagaimana dia menggeret Wak Hamzah dari tempat tidur waktu itu?"
"Kasihan, jiwanya sudah mulai terganggu. Dia sekarang terlihat lebih kurus. Kemana saja dia tiga tahun menghilang? Kasihan almarhumah Mak Gani melihat anak satu-satunya jadi begini..."
Orang-orang mulai meracau seperti kumpulan lebah. “Kita sama-sama berdoa semoga Allah membukakan pintu hati Han. Semoga Han lekas diberikan hidayah dari Allah, " ujar Ustadz Ali parau.
"Pak Ustadz belum mengenal perangainya yang sebenarnya. Dia sudah pernah membunuh orang, Ustadz..."
"Allah punya kuasanya sendiri yang tak pernah kita tahu, Pak..." jawab Ustadz Ali lembut.
Malam itu tanpa prasangka, Ustadz Ali menutup jendela dan pintu mushala tanpa menguncinya. Dan memang dia tak pernah menguncinya. "Semua makhluk punya hak dengan rumah-rumah Allah. Mereka bisa menemui Allah kapan saja," begitu alasan yang selalu dia kemukakan.
Anak-anak sudah meninggalkan mushala setelah shalat isya selesai. Beberapa menawarkan diri untuk bermalam menemani Ustadz Ali. Namun, Ustadz Ali tak mengizinkan anak-anak tidur di mushala kalau bukan di hari libur. Ustadz Ali menguap lalu beranjak menuju kamar gudang.
Baca Juga
Cerpen: Gus Khomarudin
Sebagai seorang penunggu yang selalu terjaga, saya melihat bulan malam ini lebih terang daripada biasanya. Angin bertiup dingin menggulung daun-daun. Saya melihat satu gerakan dari balik semak mendekat ke arah halaman mushala.
Bayangan itu menuju ke arah kamar gudang tempat Ustaz Ali tertidur. Bayangan itu mengetuk pelan beberapa kali sebelum pintu terbuka.
Lalu terdengar suara jeritan tertahan dan gedebuk yang teredam. Tak lama sesosok bayangan itu keluar dan mendongak seraya menyeringai. Saya bisa melihatnya dengan jelas. Wajah Han di sana, penuh kepuasan dan amarah.
Han menyiramkan cairan dari botol yang dibawanya ke sekeliling kamar gudang sebelum sesuatu yang bercahaya membuat semuanya menjadi jelas. Saya merasakan gelombang panas, perlahan tapi pasti mulai mendatangi saya.
Benar, Han menciptakan kertakan api yang semula kecil itu lalu merambat dan membesar. Asap-asap hitam tercipta dari sana. Ustadz Ali, dia ada di sana. Tolong, tolonglah dia...
Api menjalar, menelan semua yang menghalanginya jadi arang dan abu. Pintu, jendela, karpet, rak buku dan mimbar menyala kemerahan.
"Tuhan, lihat...saya sudah membakar orang suci dan tempatmu ini jadi api. Saya pewaris tanah ini! Hahaha..." Han tertawa dan berlari menjauhi halaman mushala untuk menyelamatkan diri. Orang-orang mulai berdatangan, menjerit dan terpana dengan api yang makin menjalar dan membesar.
Orang-orang berteriak ribut dan menggotong ember-ember air dari sumur dan sungai. Tak ada yang memperhatikan Han. Mata Han membeliak saat dia merasakan kedua kakinya mati rasa di tempat. Han menjerit, tapi suaranya ditelan oleh orang-orang yang panik berusaha memadamkan api.
Lidah Han seolah digulung hingga tak bisa lagi berkata-kata. Api menjalar ke tempat Han berdiri.
Dan mungkin ini akhir cerita dari seorang penunggu seperti saya. Tak ada yang bisa saya lakukan. Saya tak bisa berlari atau meminta pertolongan. Saya hanya penunggu, saya hanya sebuah kubah kecil di atap mushala ini.
Sebelum kobaran api di bawah sana membakar tubuh saya bersama kenangan di dalamnya, saya hanya berharap semoga orang-orang bisa menyelamatkan Ustadz Ali.
September 2018
“Tulisan ini adalah pemenang harapan dua lomba cerpen dalam rangka Harlah laman nulampung.or.id, 2018.”
Agus Kindi yang memiliki nama asli Agus Kurniawan ini lahir di Tanjungkarang, 14 Agustus 1985. Saat ini menetap di Sumberrejo, Kemiling, Bandar Lampung. Aktif di Forum Lingkar Pena (FLP) Bandar Lampung.
Terpopuler
1
PCNU Pringsewu Sosialisasikan Keputusan Munas dan Konbes NU 2025
2
3 Amalan Sunnah di Bulan Rabiul Awal
3
Doa dan Niat Menyambut Bulan Maulid
4
Waspadai Era Post-Truth, Ketua PCNU Pringsewu: Yang Benar Bisa Nampak Salah, yang Salah Bisa Nampak Benar
5
Istikmal, Lembaga Falakiyah PBNU Umumkan 1 Rabiul Awal Jatuh pada 25 Agustus 2025
6
Menjadi Tersangka, Immanuel Ebenezer Dipecat dari Jabatan Wamenaker
Terkini
Lihat Semua