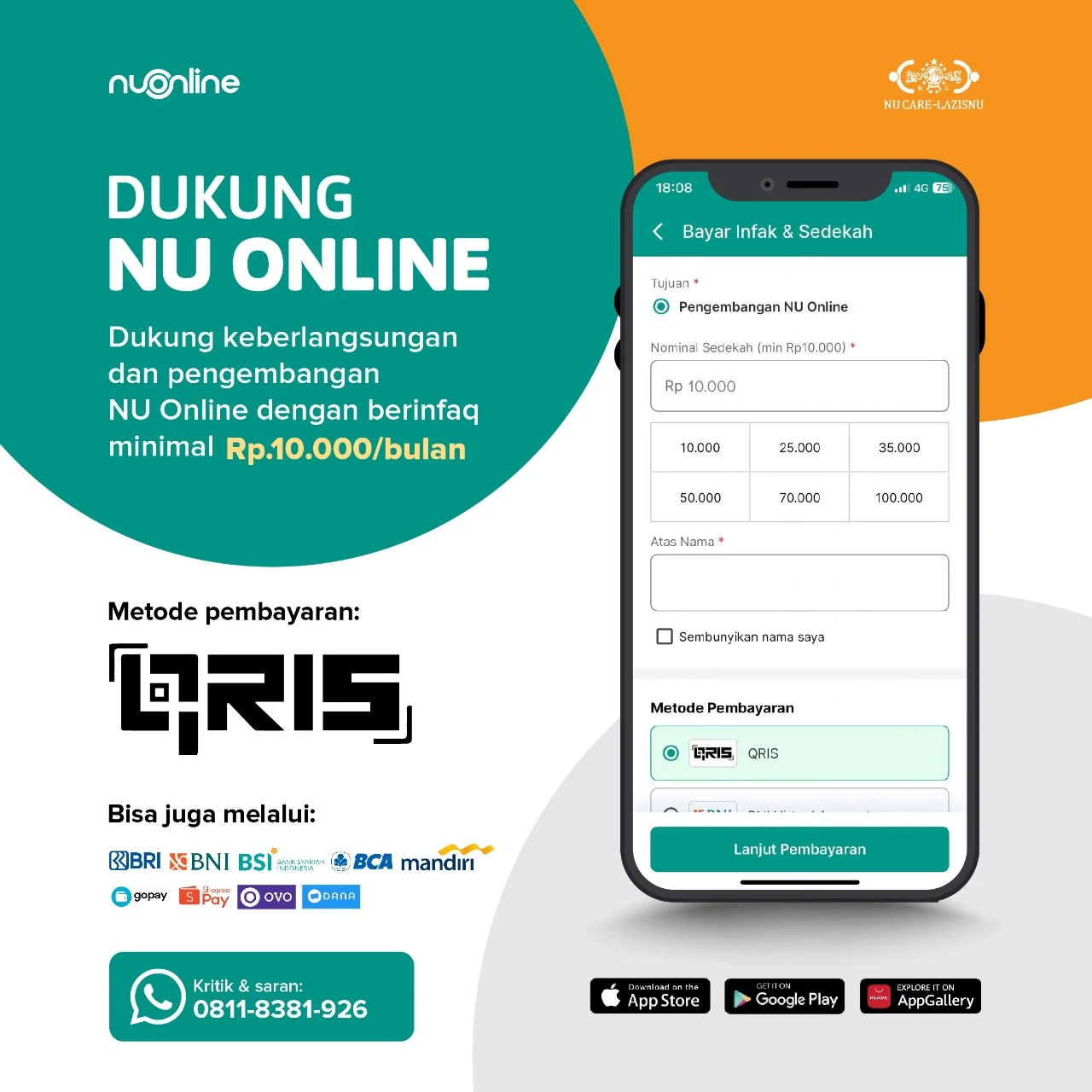Penyelarasan Tasawuf dengan Syariat dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali
Selasa, 11 Maret 2025 | 09:24 WIB
Imam Ghazali (w. 1111) adalah ulama besar yang mampu menjembatani kesenjangan antara ulama-ulama berbasis syariat maupun para sufi di masanya. Beliau sanggup memadukan antara syariat dan hakikat, sehingga tasawuf menjadi bangunan baru yang cukup meyakinkan bagi kedua belah pihak.
Dalam kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama), al-Ghazali menyusun bangunan keislaman yang dapat menghidupkan kegairahan umat Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, dan mengamalkan dengan penuh ketekunan. Kedalaman hakikat dalam tasawuf menjadi sesuatu yang bisa didayagunakan untuk mendukung semangat mempelajari ilmu-ilmu agama.
Dengan begitu, tasawuf bisa berfungsi sebagai obat yang paling ampuh untuk membebaskan umat Islam dari kekakuan dan kekeringan fiqhiyah dan penyakit spekulasi-rasional ilmu kalam. Itulah di antara unsur-unsur positif pengembangan tasawuf dalam menghidupkan dan memantapkan keyakinan agama, serta menyuburkan gairah dalam pengamalan agama.
Menurut Prof. Simuh dalam bukunya berjudul “Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam”, dasar ajaran tasawuf adalah perasaan cinta dan rindu manusia untuk berhubungan dengan kekasihnya, yakni Allah swt.
Baca Juga
4 Adab Tidur Menurut Imam al-Ghazali
Secara historis, perkembangan yang cukup menarik adalah lahirnya kesadaran dari dalam diri umat Islam untuk memodernisasi ajaran tasawuf, dan untuk menghapus konflik antara syariat dan tasawuf. Upaya ini, meski tidak berhasil secara sempurna, namun cukup konstruktif dalam positif.
Misalnya begini, pada level tertentu, al-Ghazali telah sukses mendamaikan ketegangan antara tasawuf dan syariat. Tapi di sisi lain, ajaran tasawuf bercorak falsafi, seperti ajaran manunggaling kawula Gustri, Wahdatul Wujud, dan Panteisme, sampai sekarang masih menimbulkan ketegangan dengan kalangan ortodoks atau ahli fikih.
Kelemahan dasar yang menjadikan perseteruan tasawuf dan syariat kurang memuaskan, umumnya terletak pada penghargaan terhadap tasawuf yang selalu dipandang lebih tinggi dari syariat. Imam Ghazali misalnya membagi iman menjadi tiga tingkatan, dan yang paling tinggi dimiliki oleh para sufi.
Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya’ ‘Ulum al-Din, “Keimanan tingkat awal, imannya orang-orang awam, yakni iman atas dasar semata-mata taklid. Tingkat kedua, imannya para mutakalim, atas dasar campuran taklid dengan sejenis dalil. Tingkat ini masih dekat dengan keimanan orang awam. Tingkat ketiga, imannya para sufi atas dasar persaksian secara langsung dengan perantaraan nurul yakin”.
Ini menjadi jelas bahwa tingkat keimanan sufi adalah yang paling tinggi dari yang lainnya. Meskipun, al-Ghazali tidak bermaksud merendahkan jenis keimanan orang awam maupun para mutakalimin (ahli kalam). Al-Ghazali hanya ingin mengklarifikasi bahwa keimanan itu sifatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan pengalaman keagamaan seseorang.
Terlepas dari itu, imam al-Ghazali adalah ulama besar ahli syariat menganut mazhab Syafi’i dalam hukum Islam, dan seorang teolog penganut mazhab Asy’ari yang sangat kritis. Namun setelah lanjut usia, beliau justru mendapat kepuasan jiwa dalam mendalami tasawuf.
Baca Juga
6 Adab Berpuasa Menurut Imam al-Ghazali
Menurut al-Ghazali, penghayatan tasawuf akan memudahkan seseorang dalam mendalami keyakinan dan perasaan agama, serta dapat membina akhlak yang luhur.
Al-Ghazali menulis dalam kitab Munqidz min al-Dlalal, beliau mengatakan “Sungguh aku mengetahui secara yakin bahwa para sufi itulah orang-orang yang benar-benar telah menempuh jalan Allah secara khusus. Dan bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan sebaik-baiknya, dan laku hidup mereka adalah yang paling benar, serta akhlak adalah yang paling suci. Bahkan seandainya para ahli pikir dan filsuf yang bijak, dan ilmu para ulama yang berpegang pada rahasia syariat berkumpul untuk menciptakan jalan dan akhlak yang lebih baik dari apa yang ada pada mereka (kaum sufi) tidak mungkin bisa menemukannya. Lantaran diam dan geraknya para sufi, baik lahir maupun batin, dituntun oleh cahaya kenabian. Dan, tidak ada selain cahaya kenabian di atas dunia ini, cahaya lain yang bisa meneranginya”.
Kutipan ini menunjukkan bahwa betapa di mata al-Ghazali tasawuf memiliki nilai yang sangat tinggi. Menurutnya, hanya jalan sufi saja yang paling otoritatif dan sempurna dalam menemukan kebenaran Ilahi, bukan melalui jalan syariat dan kalam.
Namun, al-Ghazali tidak membuang begitu saja ajaran syariat maupun kalam. Dalam kitab ‘Ihya ‘Ulum al-Din tergambar dengan jelas pokok pikiran al-Ghazali mengenai hubungan syariat dan hakikat. Sebelum orang mulai bertasawuf, ia harus terlebih dahulu matang dari sisi syariat dan akidah, tanpa kedua ini seseorang akan rawan terjerumus pada ajaran Wahdatul Wujud. Artinya, tasawuf tanpa didasari oleh akidah dan syariat justru akan menjerumuskan pada kesesatan dan makin menjauh dari kebenaran Ilahiah.
Di masa belakangan, tasawuf akhirnya mendapat hati dari kalangan ahli syariat dan diterima sebagai bagian dari sistem agama dan ilmu keislaman yang amat dibanggakan oleh umat Islam pada umumnya.
Rohmatul Izad, Mahasiswa S3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Terpopuler
1
Prihatin pada Meninggalnya Affan Kurniawan, Ini Seruan Ketua PWNU Lampung
2
Jurnalis Muda Madrasah Ini Sabet Juara 1 Photo Competition 2025 Provinsi Lampung
3
Belasungkawa Wafatnya Affan Kurniawan, Ketum MUI Lampung Ajak Masyarakat Tetap Jaga Kondusifitas
4
Amnesty Sebut Tindakan Polisi Lindas Ojol hingga Tewas adalah Brutal dan Langgar HAM
5
Pelantikan PC GP Ansor Periode 2025-2029, Ketua PCNU Pringsewu: Mari Perkuat 3 Konsolidasi Ini
6
Lafal Bacaan Doa Nabi Ibrahim untuk Keamanan Negeri
Terkini
Lihat Semua