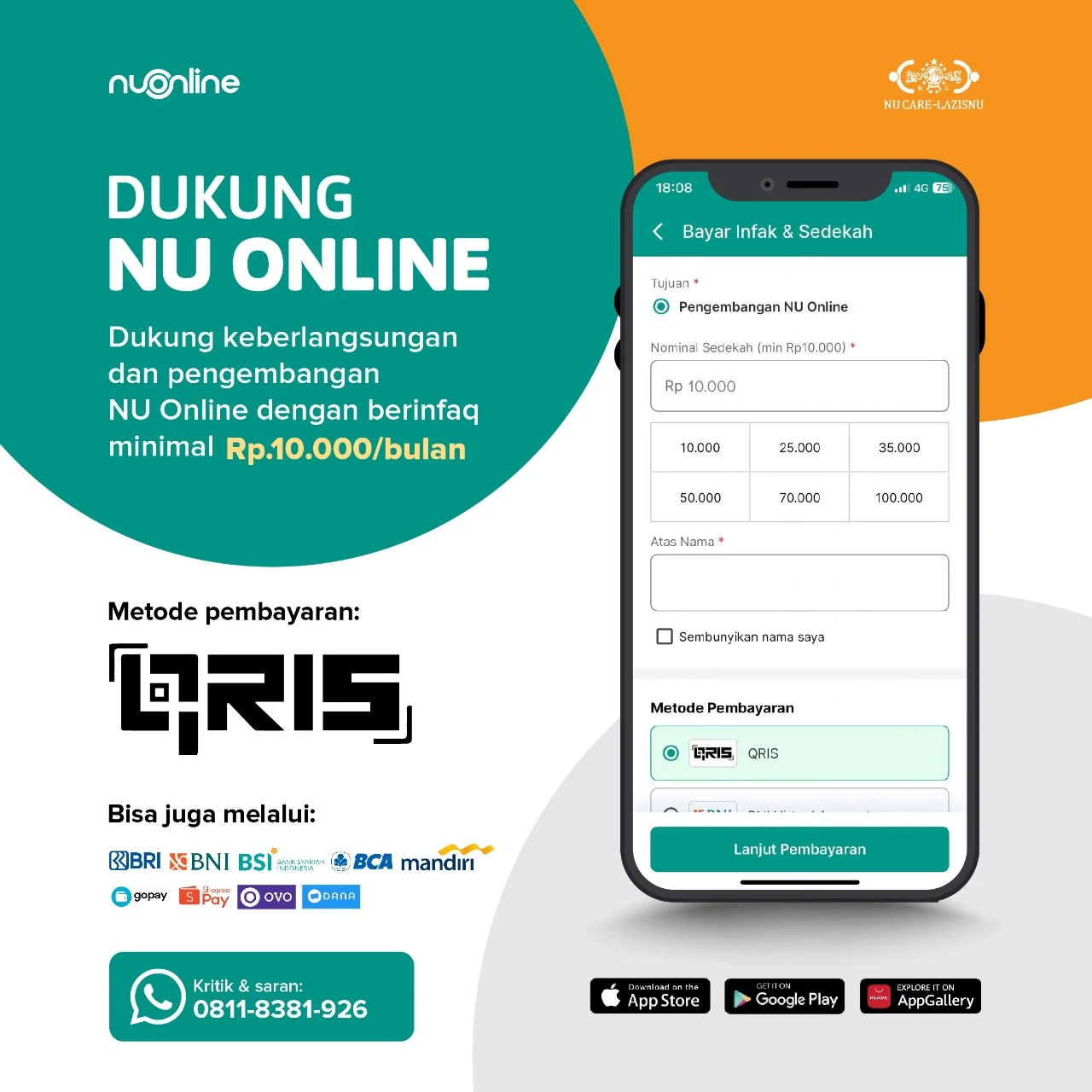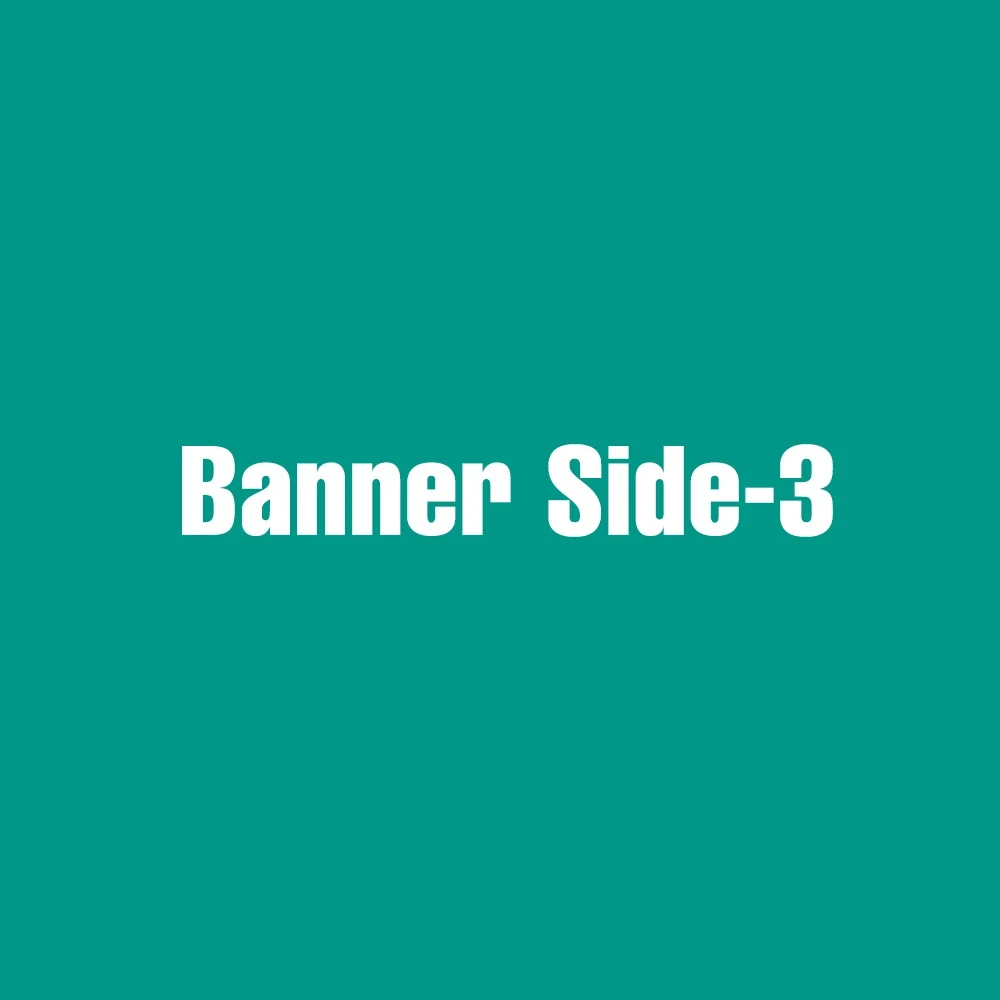Menanam Pohon, Menanam Iman: Islam dan Lingkungan dalam Kitab-Kitab Klasik
Senin, 7 April 2025 | 10:23 WIB
Di tengah bisingnya deru mesin dan debu kota, kita nyaris lupa bahwa menanam pohon adalah bagian dari ibadah. Dalam kitab al-Adab al-Mufrad karya Imam Bukhari, terdapat hadits yang menyentuh: “Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali itu menjadi sedekah baginya.” Di balik kalimat sederhana itu, terbentang luas pemikiran Islam yang ramah lingkungan, yang kadang luput kita tafsirkan secara ekologis.
Kitab-kitab klasik Islam ternyata tak hanya bicara soal fiqih dan akhlak dalam relasi sosial, tetapi juga relasi spiritual dengan alam. Alam bukan sekadar latar tempat kehidupan manusia, tetapi bagian dari tanda-tanda keagungan Allah—ayat-ayat kauniyah. Bahkan, para ulama terdahulu menjadikan lingkungan sebagai bagian dari narasi kesalehan.
Dalam Ihya Ulum al-Din, Imam al-Ghazali membahas adab buang air dengan panjang lebar, termasuk larangan buang hajat di bawah pohon rindang dan di tempat air mengalir. Di balik “larangan kecil” itu, tersirat kesadaran ekologis—agar air tidak tercemar dan pepohonan tetap lestari. Bagi al-Ghazali, kebersihan bukan hanya bagian dari iman, tetapi juga bentuk syukur terhadap nikmat alam.
Kosmologi Islam dan Ekologi
Konsep khalifah fil ardh dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 30) sering diartikan sebagai mandat kepemimpinan manusia atas bumi. Tapi mandat itu bukan semena-mena. Dalam Tafsir al-Kabir karya Fakhruddin ar-Razi, tugas khalifah adalah menjaga keseimbangan, bukan mengeksploitasi. Ar-Razi menafsirkan peran manusia sebagai penjaga harmoni antara makhluk, bukan penguasa yang merusak.
Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Sufi, seperti Ibn Arabi, yang memandang alam sebagai manifestasi dari asmaulhusna nama-nama Allah. Maka merusak lingkungan sejatinya adalah bentuk pelecehan terhadap “kitab kedua” Allah setelah wahyu: alam semesta. Pohon, sungai, angin, dan hujan bukan hanya benda mati, tetapi makhluk yang bertasbih, sebagaimana disebut dalam QS. Al-Isra: 44.
Air, Pohon, dan Udara dalam Fiqih
Dalam literatur fiqih, ulama-ulama mazhab menyusun bab-bab khusus mengenai hak atas air (haq al-ma’) dan larangan pencemaran. Dalam al-Umm, Imam Syafi’i menyatakan bahwa air sungai tidak boleh dikotori karena menjadi hajat umum. Bahkan dalam hukum Islam klasik, air dibagi menjadi tiga: milik bersama (seperti sungai dan hujan), milik individu (sumur), dan milik negara (saluran irigasi).
Kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah (Hanbali) menjelaskan bahwa hak berteduh di bawah pohon umum tidak boleh diganggu. Artinya, merusak pohon rindang di jalanan bisa dianggap sebagai pelanggaran hak sosial. Di tengah maraknya penebangan pohon kota demi pelebaran jalan atau proyek properti, warisan fiqih klasik ini layak dibaca ulang.
Dalam al-Majmu’, Imam Nawawi mengutip berbagai hadits tentang larangan membuang sampah di jalan dan tempat berkumpul. Hari ini, larangan itu lebih relevan dari sebelumnya sampah plastik menumpuk di sungai, selokan tersumbat, dan udara semakin sesak. Barangkali, yang kita butuhkan bukan hanya teknologi hijau, tetapi fiqih yang hijau: fiqih yang menyentuh nurani ekologis umat.
Kisah Para Ulama dan Cinta Alam
Tak sedikit ulama klasik yang memberi teladan konkret. Syekh Abdul Qadir al-Jailani dikisahkan melarang muridnya mematahkan ranting pohon sembarangan. Imam Abu Hanifah, ketika berjalan di pasar, selalu memungut paku dan benda tajam agar tak melukai kaki orang lain. Hal-hal “remeh” ini, hari ini menjadi isu besar: keamanan ruang publik dan keberlanjutan ekosistem kota.
Di Nusantara, KH Hasyim Asy’ari dalam Adabul ‘Alim wal Muta’allim menekankan pentingnya kebersihan lingkungan dalam proses belajar. Para santri diwajibkan membersihkan kamar, halaman, bahkan selokan pondok. Di pesantren tradisional, hidup bersih bukan gaya hidup, tapi bagian dari adab mencari ilmu.
Kitab Tuhfah al-Muhtaj dan Hasyiyah al-Bajuri juga menyinggung pentingnya kebersihan dalam konteks ibadah. Namun lebih jauh dari itu, kesucian (thaharah) adalah simbol keteraturan dan keseimbangan hidup, baik secara spiritual maupun ekologis.
Menjadi Muslim yang Hijau
Hari ini, perubahan iklim bukan lagi wacana akademik, tapi realitas harian: banjir yang makin sering, suhu yang makin ekstrem, dan polusi udara yang membuat sesak napas. Islam sebenarnya punya perangkat etik dan hukum untuk menjawab ini, tapi kita sering meminggirkan warisan klasik yang kaya itu.
Gerakan Green Islam atau Islam Hijau yang muncul di berbagai negara Muslim, mulai dari Turki hingga Indonesia, mencoba menghidupkan kembali semangat ini. Namun agar tidak berhenti pada seremoni tanam pohon saat Hari Santri, dibutuhkan pembacaan ulang terhadap kitab-kitab klasik dengan perspektif lingkungan.
Sekolah-sekolah Islam, pesantren, hingga masjid perlu menjadi pusat ekopedagogi Islam. Mengajarkan bahwa mencabut rumput sembarangan bisa bernilai dosa, dan menyiram tanaman bisa menjadi amal jariah. Bahwa lingkungan adalah bagian dari iman, bukan sekadar urusan pemerintah daerah atau LSM.
Menanam Amal di Atas Tanah
Di tengah krisis lingkungan, kita tak hanya butuh teknologi, tapi juga teologi. Teologi yang mengajarkan bahwa menanam pohon sama mulianya dengan mendirikan salat, bahwa membuang sampah pada tempatnya adalah bentuk taqwa.
Kitab-kitab klasik Islam tak henti memberi ilham bahwa bumi bukan milik kita, tapi titipan anak cucu kita. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda: “Jika kiamat datang dan di tanganmu ada biji kurma, tanamlah meskipun kiamat tiba.” Sebuah perintah yang absurd di logika dunia, tapi penuh makna di logika iman.
Mungkin inilah saatnya kita mengganti jargon “go green” menjadi “go iman”. Karena menjaga alam, sejatinya adalah menjaga janji kita kepada Sang Khalik bahwa sebagai khalifah, kita tak akan merusak bumi, tapi menumbuhkan harapan dari akar iman.
Wahyu Iryana, Penulis Merupakan Sejarawan UIN Raden Intan Lampung.