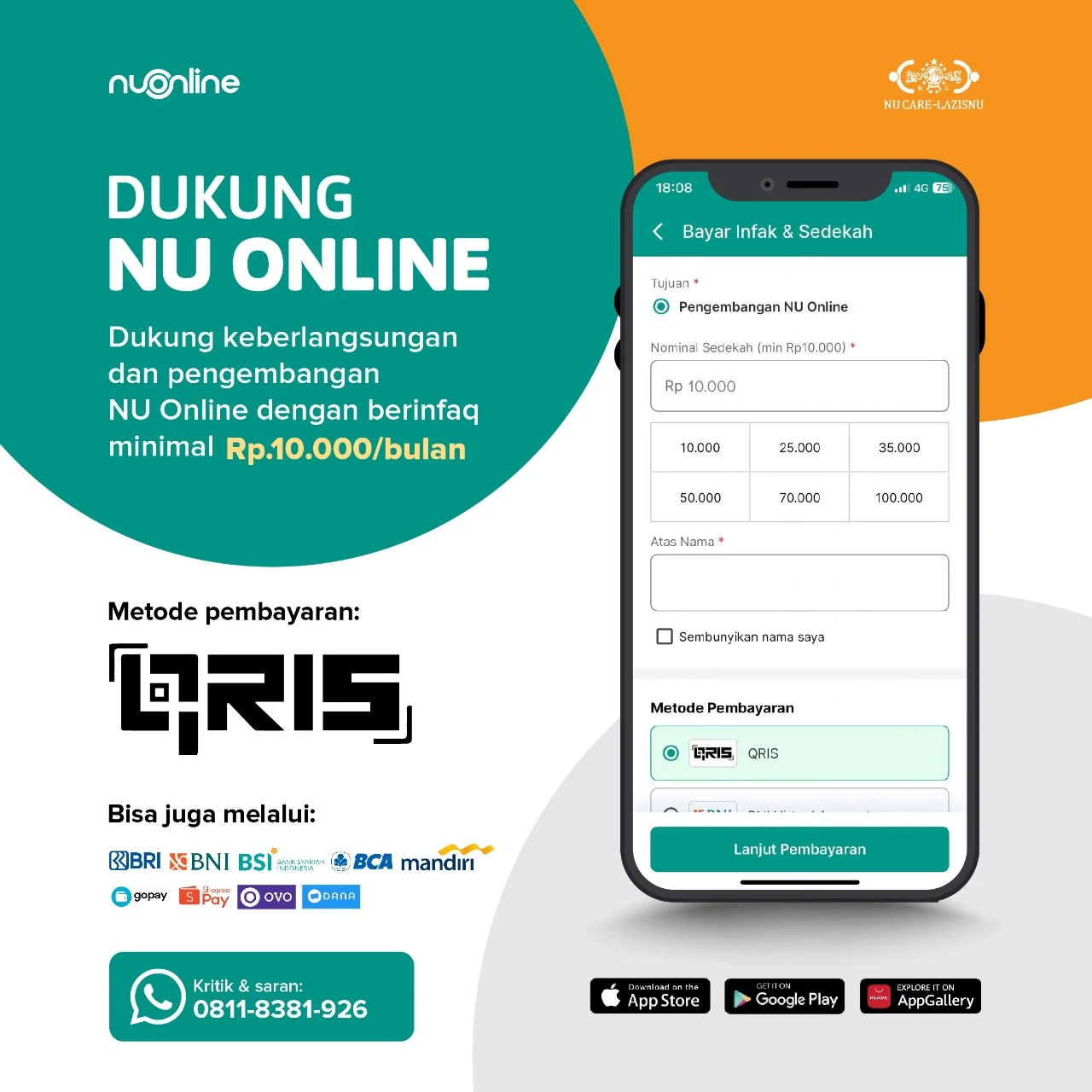Surat Edaran Lembaga Bahtsul Masail PBNU Terbaru Terkait Pelaksanaan Shalat Jumat
Sabtu, 6 Juni 2020 | 12:59 WIB
JAKARTA - Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU mengeluarkan surat edaran (SE) terbaru tentang pelaksanaan Shalat Jum'at dalam kondisi ‘New Normal’.
Dalam SE itu dikatakan, penularan Virus Covid 19 masih terus terjadi. Belum kelihatan bahwa persebaran virus akan segera berakhir, bahkan di sebagian daerah menunjukkan adanya grafik kenaikan orang-orang yang terjangkit virus covid 19.
Sejumlah daerah yang beberapa bulan lalu masih masuk zona kuning sekarang sudah naik menjadi zona merah. Sementara jumlah orang yang terpapar virus meningkat sangat tajam.
Sementara di sisi lain, dampak ekonomi dari persebaran virus ini juga perlu mendapatkan perhatian. Jangan sampai virus covid 19 ini memukul bangsa Indonesia dari sudut kesehatan dan dari sudut ekonomi secara sekaligus.
Untuk tujuan itu, pemerintah menganjurkan agar masyarakat Indonesia mulai mengadaptasikan diri dengan virus covid 19 ini. Artinya, masyarakat bisa tetap menjalankan aktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya dengan menjaga jarak antar orang dan pakai masker. Itulah yang disebut dengan new normal.
Tak hanya aktivitas perekonomian yang perlu menyesuaikan diri, melainkan juga aktivitas keagamaan. Kaidah fikih menyatakan:
مَ ا لَا یُدْ رَ كُ كُ لُّھ لَا یُ ترَ كُ كُ لُّھ .
“Sesuatu yang tidak bisa dicapai keseluruhannya, maka jangan ditinggal sama sekali.”
اَ لمَ یسُ ورُ لَا یَسْ ق ط بِا لمَ عْ سُ ورِ
“Perkara yang mudah dikerjakan tak gugur karena perkara yang sulit dikerjakan”
Dalam konteks new normal ini, maka bagaimana misalnya melaksanakan shalat jum’at yang meniscayakan berjemaah? Apakah dimungkinkan umat Islam memperbanyak ruang-ruang pelaksanaan shalat jum’at ( (تعدد الجمعة فى محلین أو محال dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan? Atau bahkan, bisakah melaksanakan shalat jum’at secara bergelombang/bergantian di satu tempat
?(تعدد الجمعة فى محل واحد أو مسجد واحد)
Ada dua hal yang penting diketahui terlebih dahulu. Pertama, bahwa di samping berbasis individu ( فردي ), shalat Jum’at sesungguhnya juga berbasis komunitas ( جماعي ). Artinya, secara individual, setiap individu muslim harus Shalat Jum’at.
Dengan demikian, seseorang yang tidak shalat Jum’at, maka dosanya hanya ditanggung oleh yang bersangkutan. Dan secara sosial, shalat Jum’at mengandung nilai syi’ar. Karena itu, masyarakat Islam yang tidak mendirikan shalat Jum'at akan mendapatkan dosa kolektif.
Kedua, menurut jumhur fuqaha ( من الائمة و الاصحاب ), shalat Jum’at harus dilaksanakan satu kali di satu tempat di setiap kawasan, desa atau kota. Ini artinya, menurut jumhur, tidak boleh ada shalat Jum'at lebih dari satu kali ( عدم جواز تعدد الجمعة ), baik di tempat yang sama maupun tempat yang berbeda. Sebab, kalau ta’addud al-jum’at itu terjadi, maka yang sah hanya shalat Jum'at yang pertama.
الثَّالِثُ : أَنْ لَا یَسْبِقَھَا وَلَا یُقَارِنَھَا جُمُعَةٌ فِي بَلْدَتِھَا إلَّا إذَا كَبُرَتْ وَعَسُرَ
اجْتِمَاعُھُمْ فِي مَكَان وَقِیلَ لَا تُسْتَثْنَى ھَذِهِ الصُّورَة
“Syarat sah pelakasanaan shalat Jumat yang ketiga adalah tidak diduhului dan berbarengan dengan shalat jumat yang lainnya di wilayah yang sama kecuali jika wilayah tersebut luas dan adanya kesulitan mengumpulkan jamaah shalat jumat pada satu tempat. Dan dikatakan di dalam pendapat lain bahwa situasi dan kondisi ini tidaklah dikecualikan.”
(Muhyiddin Syarf an-Nawawi, Minhaj ath-Thalibin wa 'Umad al-Muftin, Bairut-Dar al-Minhaj, Cet ke-1, 1426 H/2005 M, h. 133).
Namun, ketidak-bolehan ta’addud al-jum’at ini tidak bersifat mutlak. Para ulama mengajukan beberapa alasan dibolehkannya ta’addud al-jum’at di banyak tempat.
Pertama, keterbatasan daya tampung tempat shalat Jum’at.
Kedua, adanya pertikaian ( وجود النزاع ) yang tak memungkinkan dilaksanakannya shalat Jum’at di satu tempat.
Ketiga, jauhnya jarak ( بعد المسافة ) antara penduduk yang tinggal di ujung sebuah kawasan (balad) dengan masjid yang menjadi tempat shalat Jum’at.
وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الْأ ئِمَّةِ أَنَّ أَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِھَا ثَلَاثَةٌ : ضَیْقُ مَحَلِّ
الصَّلَاةِ بِحَیْثُ لَا یَسَعُ الْمُجْتَمِعِینَ لَھَا غَالِباً ، وَالْقِتَالُ بَیْنَ الْفِئَتَیْنِ بِشَرْطِھِ ،
وَبُعْدُ أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا یَسْمَعُ مِ نھُ النِّدَاءَ ، أَوْ بِمَحَلِّ لَوْ خَرَجَ
مِنْھُ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ یُدْرِكْھَا ، إِذْ لَا یَلْزَمُھُ السَّعْيُ إِلَیْھَا إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ اھ
“Kesimpulan dari pendapat para imam adalah bahwa sebab kebolehan mendirikan shalat jumat lebih dari satu lokasi (ta’addud al-jumu’ah) ada tiga. Pertama, sempitnya tempat shalat, sekiranya tempat tersebut tidak mampu menampung jamaah shalat Jumat secara umum. Kedua, adanya pertikaian antara dua kubu sesuai dengan syaratnya. Ketiga, jauhnya jarak penduduk yang berada di batas akhir sebuah kawasan (balad) dengan masjid yang melaksanakan shalat Jumat, seperti berada di tempat yang tidak terdengar suara azan atau di tempat yang seandainya seseorang berangkat dari tempat tersebut (untuk menjalankan shalat Jumat) setelah fajar maka ia tidak akan menemui shalat Jumat (telat).
Sebab tidak ada keharusan baginya menuju tempat pelaksanaan shalat Jumat, kecuali setelah terbit fajar.” (Abdurrahman Ba’alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, Beirut-Dar al- Fikr, 1995 M, h. 51).
Pandangan fikih ulama terdahulu itu bisa dijadikan acuan hukum perihal pelaksanaan shalat Jum’at di era new normal ini. Secara teknis, umat Islam misalnya bisa memanfaatkan musalla-musalla yang selama ini hanya dipakai sebagai tempat shalat maktubah menjadi tempat shalat Jum’at. Ini karena pelaksanaan shalat Jumat tidak harus dilakukan di masjid sebagaimana pendapat mayoritas ulama.
وَذَھَبَ البَعْضُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمَسْجِدِ قَالَ لِأَنَّھَا لَمْ تَقُمْ إِلَّا فِیھِ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ
وَالشَّ افِعِيُّ وَسَائِرُ العُلَمَاءِ إِنَّھُ غَیْرُ شَرْطٍ وَھُوَ قَوِيٌّ
Sebagian ulama mempersyaratkan masjid sebagai tempat pelaksanaan shalat Jumat. Sebab, menurut mereka shalat Jumat tidak ada kecuali di masjid. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa masjid bukan syarat bagi pelakasanaan shalat Jumat. Dan ini adalah pendapat yang kuat." (Muhammad Syamsul Haq Abadi, ’Aun al-Ma'’ud Syarhu Sunani Abi Dawud, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet ke-2, 1415 H, juz, III, h. 281)
Namun, persoalan berikutnya muncul. Misalnya bagaimana jika tak ditemukan tempat lain yang memungkinkan untuk ditempati shalat jum'at?Bolehkah mendirikan shalat jum'at secara bergelombang di satu tempat?
Dalam kasus ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, ulama yang mengacu pada ketentuan ( ضابط ) berikut: Dalam kondisi darurat di mana lokasi jum’atan yang ada hanya bisa menampung sebagian jama’ah akibat penerapan phyisical distancing dan secara riil tidak ditemukan lokasi lain yang bisa ditempati shalat jum'at, maka dibolehkan mendirikan shalat jum'at secara bergelombang/bergantian.
Dhobith atau acuan tersebut masih bersifat normatif dan umum ( .(تخریج المناط Karena itu, untuk melaksanakan shalat bergelombang dibutuhkan verifikasi lapangan ( تحقیق المناط ). Ini untuk memastikan bahwa suatu kawasan sudah memenuhi syarat bagi dilaksanakannya ta’addud al-jum’at di satu kawasan. Sebab, ta’addud aljum’at di satu kawsan ini hanya bisa dilaksanakan dalam kondisi darurat atau atas dasar kebutuhan yang mendesak ( .(الحاجة الملحة
Dan sekiranya shalat jum’at secara bergelombang itu dilaksanakan, maka ia harus mempertimbangkan hal berikut.
Pertama, jumlah orang yang ikut shalat Jum’at pada setiap gelombang harus dipastikan tak kurang dari 40 orang, sebagaimana dipersyaratkan para ulama terkuat.
فَمَذْھَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَرْبَعِینَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ مَذَاھِبُ السَّلَفِ
فِى ذَلِكَ
“Madzhab Syafii menyatakan bahwa bahwa keabsahan pelaksanaan shalat Jumat harus diikuti 40 orang. Sedangkan para ulama salaf dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat.”
(Abdul Malik al-Juwaini, Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab, Jeddah-Dar al- Minhaj, Cet ke-2, 1430 H/2009 M, juz, II, h. 481)
Kedua, karena dilaksanakan dalam kondisi darurat, maka jumlah gelombang pelaksanaan Jum’atan itu harus berdasarkan kebutuhan. Artinya, jika pelaksanaan shalat Jum’at cukup dilakukan dengan dua gelombang, maka tak boleh membuat gelombang ketiga dan seterusnya.
Kaidah fikih mengatakan:
مَا أُبِیحَ لِلضَّرُورَةِ یُقَدَّرُ بِقَدَرِھَا
“Apa saja yang diperbolehkan karena darurat, ditentukan menurut kadarnya.”
Pendapat Kedua, sebagian ulama berpendapat demikian; sekiranya ta’ddud al-jum’ah di banyak tempat tak memungkinkan, maka solusinya bukan dengan mendirikan shalat Jum’at secara bergelombang di satu tempat, melainkan mempersilahkan umat Islam yang tidak mendapatkan kesempatan shalat Jum’at di satu tempat untuk shalat zuhur di rumah masing-masing.
Dengan ini, target pelaksanaan shalat Jum’at di satu wilayah sudah terpenuhi, sementara mereka yang tak kebagian shalat Jum’at di tempat itu dianggap sebagai orang uzur (ma’dzur) yang berhak mendapatkan dispensasi hukum (rukhsoh).
Pendapat ini didasarkan pada keumuman teks “man lahu ‘udzrun” dalam pernyataan Imam Syafi’i berikut:
قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَھُ للهَُّ تَعَالَى : " وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِیضٍ وَلَا مَنْ لَھُ عُذْرٌ وَإِنْ حَضَرُوھَا أَجْزَأَتْھُمْ
“Imam Syafii berkata: ‘Tidak ada kewajiban bagi musafir, hamba sahaya, perempuan, orang yang sakit, dan orang memiliki udzur. Dan jika mereka menghadiri jumatan maka hal itu mencukupi bagi mereka (sah)”
Pandangan fikih di atas bisa menjadi acuan umat Islam dalam melaksanakan shalat Jum’at bagi umat Islam di daerah yang persebaran virus covid 19 telah terkendali dan sudah memberlakukan kehidupan new normal. Namun, bagi umat Islam yang tinggal di zona merah virus covid 19, maka mereka bisa tetap merujuk pada pandangan LBM PBNU sebelumnya, yaitu umat Islam dilarang melakukan aktivitas berkumpul termasuk melaksanakan shalat Jum’at ( ترك الجمعة بالكلیة ) yang menyebabkan tersebarnya virus covid 19. Sekali lagi, pelarangan bukan pada shalat Jum’atnya melainkan pada aktivitas berkumpulnya.
“Demikian hasil bahtsul masail tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at dalam
Kondisi New Normal ini disampaikan untuk menjadi pegangan warga NU khususnya serta umat Islam Indonesia umumnya. Seraya berdoa, meminta pertolongan Allah SWT, semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) segera bebas dari pandemi Covid-19,” tulis SE yang ditandatangani di Jakarta, 5 Juni 2020 oleh Ketua LBM PBNU KH. M. Nadjib Hassan dan Sekretaris H. Sarmidi Husna, MA.
Sementara Tim Perumus antaralain KH. Afifuddin Muhajir, KH. Abdul Ghafur Maimun, KH. Miftah Faqih, KH. Zulfa Mustofa, KH. Abdul Moqsith Ghazali, KH. Azizi Hasbullah, KH. Mahbub Ma'afi, KH. Asnawi Ridwan, KH. Ahmad Nazhif Abdul Mujib, KH. Darul Azka, KH. Fajar Abdul Basyir, KH. Anis Masduki, K. Zaenal Amin, K. Ahmad Muntaha AM, K. Alhafidz Kurniawan. (rls)
Terpopuler
1
Kita Sedang Membangun Apa? Ini Renungan Mendalam dari QS At-Taubah: 109
2
Ngati, Ngaji, Ngopi: Cara PCNU Pringsewu Perkuat Silaturahmi dan Konsolidasi
3
Ngaji AD/ART dan Perkum PCNU Pringsewu, Ini Pesan PWNU Lampung pada Pengurus NU
4
Khutbah Jumat: Hidup Harus Bermanfaat Bagi Umat Manusia
5
3 Tipe Orang dalam Organisasi menurut Rais dan Ketua PCNU Pringsewu
6
BWI Pringsewu Terbitkan Buku Panduan Lengkap Wakaf, Penting untuk Nadzir!
Terkini
Lihat Semua