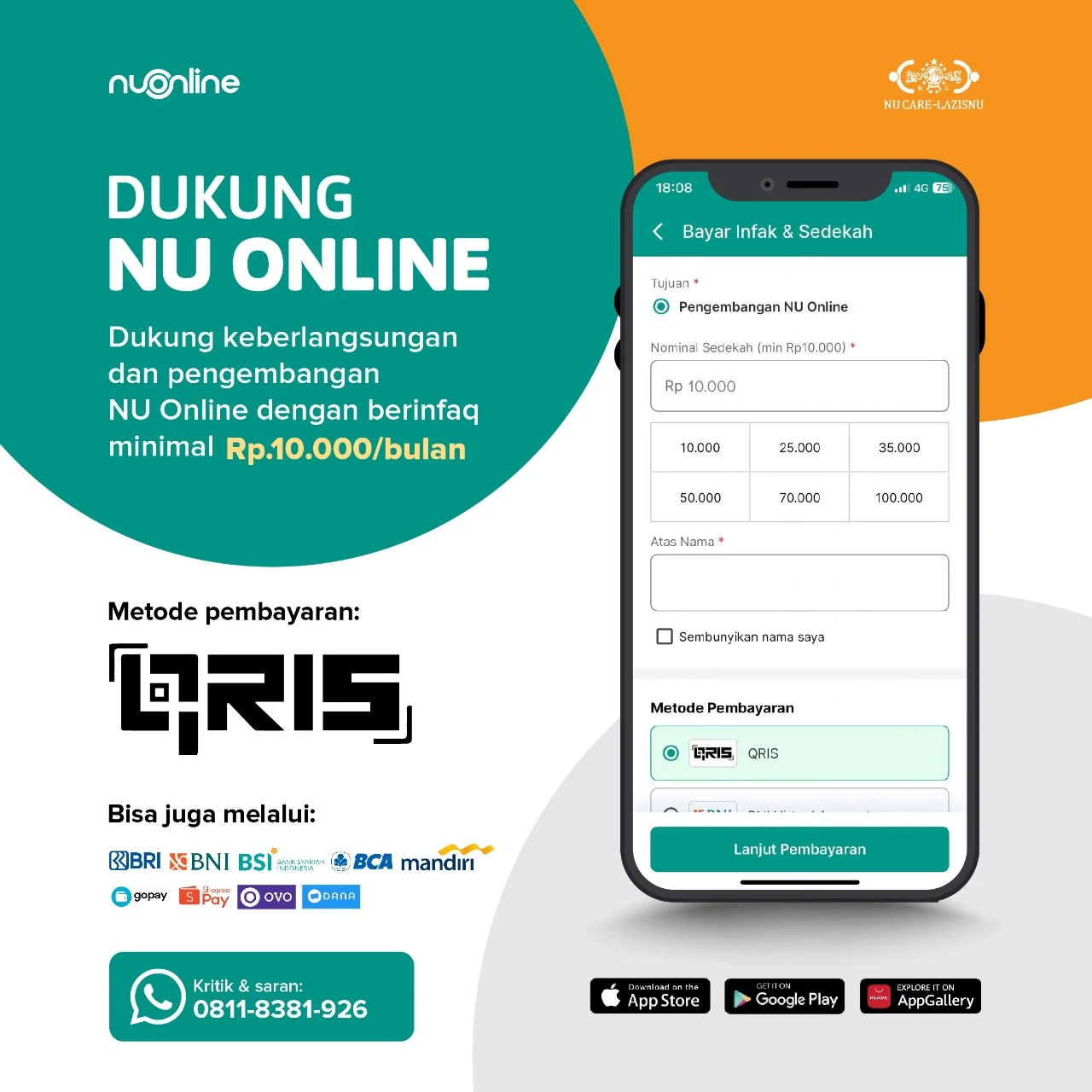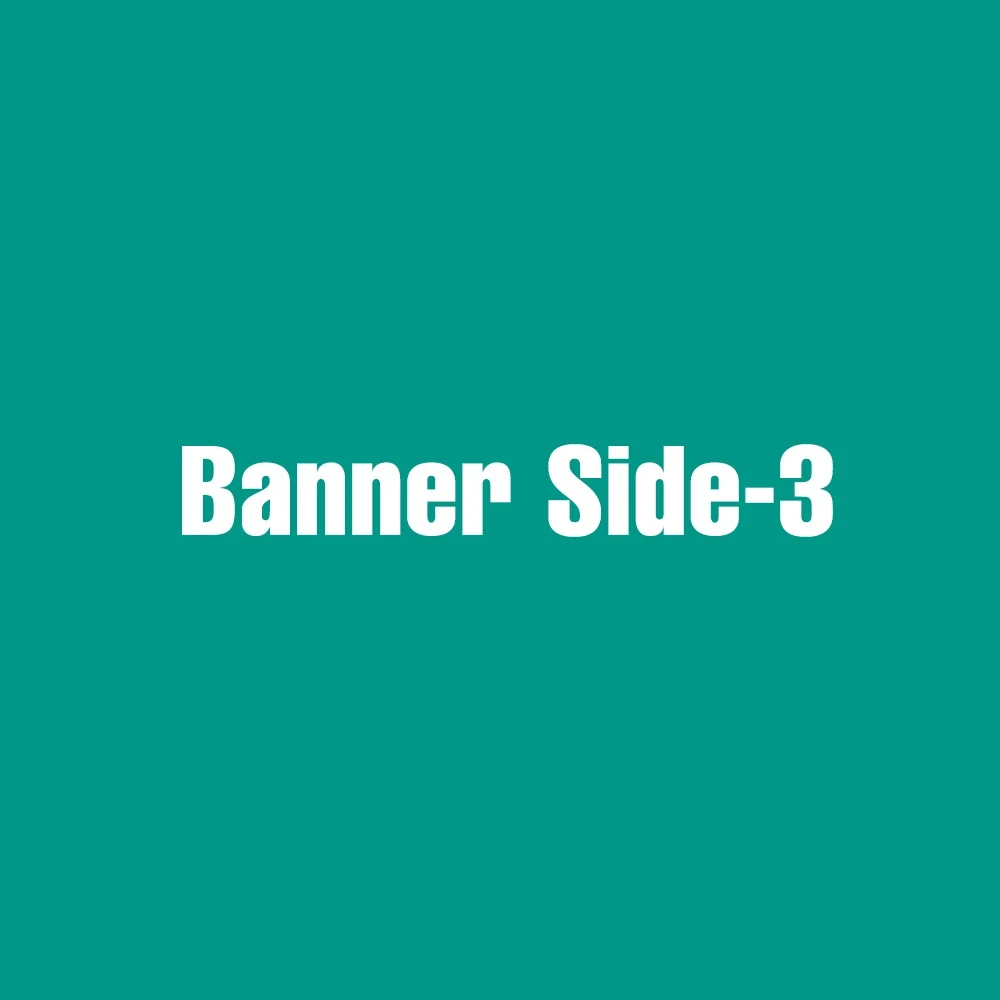Membumikan Riset Ilmiah di PTKI: Jejak Klasik, Tantangan Mutakhir
Kamis, 15 Mei 2025 | 13:54 WIB
Wahyu Iryana
Penulis
Pada awal abad ke-20, ketika dunia Islam menghadapi gelombang modernitas, para ulama Nusantara tak tinggal diam. Mereka menulis, meneliti, dan mencatat sejarah, hukum, tafsir, dan bahkan ilmu pengobatan dengan semangat ilmiah luar biasa. Misalnya, Al-Hujjah karya KH Ahmad Hanafiah dari Sukadana ditulis sebagai respons terhadap situasi kolonial, atau Ad-Durr an-Nafi’ fi Syarh al-Latif karya KH Raden Muhammad Thaib di Tanjungkarang yang merekam dinamika hukum Islam di Sumatera. Kitab-kitab itu bukan sekadar produk ulama tetapi hasil riset mendalam, berdasar data empiris zaman itu dan ketekunan terhadap sumber-sumber primer klasik.
Kini, di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi, kita justru menyaksikan paradoks di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Jumlah doktor, guru besar, dan sarjana terus meningkat. Namun, kualitas dan kuantitas riset yang benar-benar berbasis data akurat, disiplin metodologis yang kuat, dan berdampak pada masyarakat masih jauh dari harapan. Ini adalah gejala stagnasi epistemologis di tengah kemegahan institusional.
Menurut Pangkalan Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat milik Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, hanya 22% proposal riset PTKIN dalam lima tahun terakhir yang dinilai berkualitas tinggi. Laporan Sinta (Science and Technology Index) Kemenristekdikti juga menunjukkan produktivitas publikasi ilmiah PTKIN masih tertinggal jauh dari perguruan tinggi umum. Jika riset hanya dipandang sebagai kewajiban administratif demi naik jabatan, lulus kuliah, atau meraih hibah maka yang terjadi bukan kemajuan keilmuan, tetapi formalisasi tanpa ruh.
Para ulama klasik memberikan teladan metodologis. Dalam Tafsir al-Ibriz, KH Bisri Musthofa menjelaskan tujuan penulisan, metodologi, serta rujukan yang digunakan sebuah struktur yang sejajar dengan kerangka akademik modern. Syaikh Nawawi Banten dalam Tafsir Marah Labid menyebut perbedaan pandangan antar mufassir dan posisi argumennya secara terbuka. Itu bukti bahwa tradisi ilmiah ulama dahulu tidak inferior dibandingkan sistem akademik barat bahkan mungkin lebih jujur dan terbuka.
Turats sebagai Sumber Primer yang Terlupakan
Ironisnya, khazanah klasik (turats) yang begitu kaya kerap diabaikan dalam penelitian akademik masa kini. Banyak skripsi dan disertasi di PTKIN lebih bertumpu pada teori-teori modern tanpa upaya mengontekstualisasikan dengan sumber klasik Islam. Padahal di luar negeri Oxford, Harvard, Leiden justru membangun pusat studi manuskrip Islam. Sementara kita yang memiliki naskah dan manuskripnya, malah menyimpannya dalam kardus dan membiarkannya rusak dimakan rayap.
Maka sangat dibutuhkan pergeseran paradigma: riset sebagai ibadah ilmiah, bukan sekadar syarat administratif. Untuk membangun riset yang berdampak, tiga syarat pokok mutlak: data akurat, disiplin ilmu terjaga, dan kejujuran akademik. Dalam konteks ini, peran reviewer nasional menjadi kunci untuk menjaga marwah akademik.
Reviewer: Antara Kritis dan Tawadhu’
Prof. Sahiron, Direktur Pendidikan Islam Kemenag RI, dalam satu forum akademik nasional menegaskan bahwa amanah sebagai reviewer nasional bukan ruang untuk merasa paling tahu, tetapi tanggung jawab menjaga kualitas ilmiah. “Reviewer itu tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling tahu. Tapi ia juga tidak boleh abai. Harus kritis, harus normatif, dan harus objektif,” ujar beliau. Ini adalah prinsip penting, sebab setiap riset adalah ruang dialog antara keilmuan, kejujuran, dan kebermanfaatan.
Masalah lain yang mengemuka di PTKIN adalah tumpang tindih keilmuan dalam riset. Seorang doktor tafsir meneliti kebijakan pendidikan tanpa dasar pedagogik; dosen fikih membahas fintech tanpa data statistik dan teori ekonomi. Akibatnya, hasil riset tidak tajam, analisis kabur, dan rekomendasi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan soal larangan lintas disiplin, tapi soal kecermatan metodologis dan tanggung jawab epistemik.
Untuk mencegah disorientasi metodologis, maka semua penelitian harus melewati proses validasi topik, kesesuaian pendekatan, dan kompetensi keilmuan. Rektor, LPM, hingga reviewer di tingkat fakultas harus berani menegakkan standar yang ketat. Tidak semua bisa meneliti segalanya. Kita butuh keberanian untuk berkata: ini bukan bidang anda, carilah kolaborator, atau dalami dulu ilmunya.
Pembangunan ekosistem pengetahuan sangat mendesak. Ini meliputi perpustakaan digital yang inklusif, pelatihan metodologi lintas disiplin, dan kemitraan antar-PTKIN dalam riset kolaboratif. Bayangkan jika UIN Sunan Kalijaga, UIN Raden Intan Lampung, dan UIN Malang menyusun riset bersama tentang moderasi Islam berbasis turats dan data lapangan, maka akan lahir lompatan epistemik yang luar biasa.
Hasil riset tidak harus selalu dalam bentuk jurnal ilmiah. Artikel populer, podcast, dan video pendek edukatif berbasis riset bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Inilah dakwah keilmuan era digital. Peneliti harus belajar menjadi komunikator. Ilmu yang tidak dimasyarakatkan hanyalah menara gading, tak bernyawa.
PTKIN harus menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Hasil riset zakat bisa diterapkan oleh BAZNAS. Penelitian tentang keluarga sakinah bisa dijadikan acuan KUA. Dengan demikian, hasil riset tidak hanya berhenti di rak fakultas, tapi menjadi kebijakan, layanan, bahkan solusi.
Riset sebagai Dakwah dan Perubahan Sosial
Riset bukan semata soal metodologi, tapi juga jalan dakwah. KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah setelah melakukan riset sosial terhadap kondisi pendidikan dan kesehatan rakyat. KH Hasyim Asy’ari menulis Adabul ‘Alim wal Muta’allim karena keprihatinan terhadap menurunnya adab santri. Semua itu bermula dari observasi, refleksi, dan kepekaan sosial inti dari riset itu sendiri.
Meningkatkan kualitas riset di PTKIN bukan semata tentang insentif atau dana. Ini soal etos ilmiah. Bila ulama klasik bisa menulis ratusan halaman dengan tinta dan pelita, tanpa listrik dan internet, maka tak ada alasan kita di era digital tak mampu melampaui mereka. Yang dibutuhkan adalah semangat, kejujuran, dan keberanian berpikir.
Seperti nasihat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, “Ilmu yang tidak diamalkan adalah kegilaan. Dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan.” Maka riset di PTKIN harus menjadi ilmu yang diamalkan bukan sekadar angka di laporan atau berkas di lemari. Data harus akurat, metode harus kuat, disiplin ilmu harus dijaga. Yang paling penting, hasil riset harus menyentuh umat, memberi solusi, dan menjadi amal jariyah ilmiah.
Wahyu Iryana, Penulis Merupakan Reviewer Nasional dalam llmu Adab dan Humaniora 2025-2027
Terpopuler
1
Lafal Bacaan Doa Nabi Ibrahim untuk Keamanan Negeri
2
14 Doa Nabi Muhammad Saw, Cocok Dibaca di Hari Maulid Nabi
3
Hukum Menjarah Rumah Orang Lain saat Unjuk Rasa
4
PCNU Pringsewu Terima Wakaf Tanah untuk Lembaga PAUD di Kecamatan Ambarawa
5
PW GP Ansor Lampung Komitmen Jaga Persatuan lewat Istighotsah dan Doa Bersama Serentak
6
NU Lampung Ketuk Pintu Langit untuk Keamanan dan Kedamaian Indonesia
Terkini
Lihat Semua