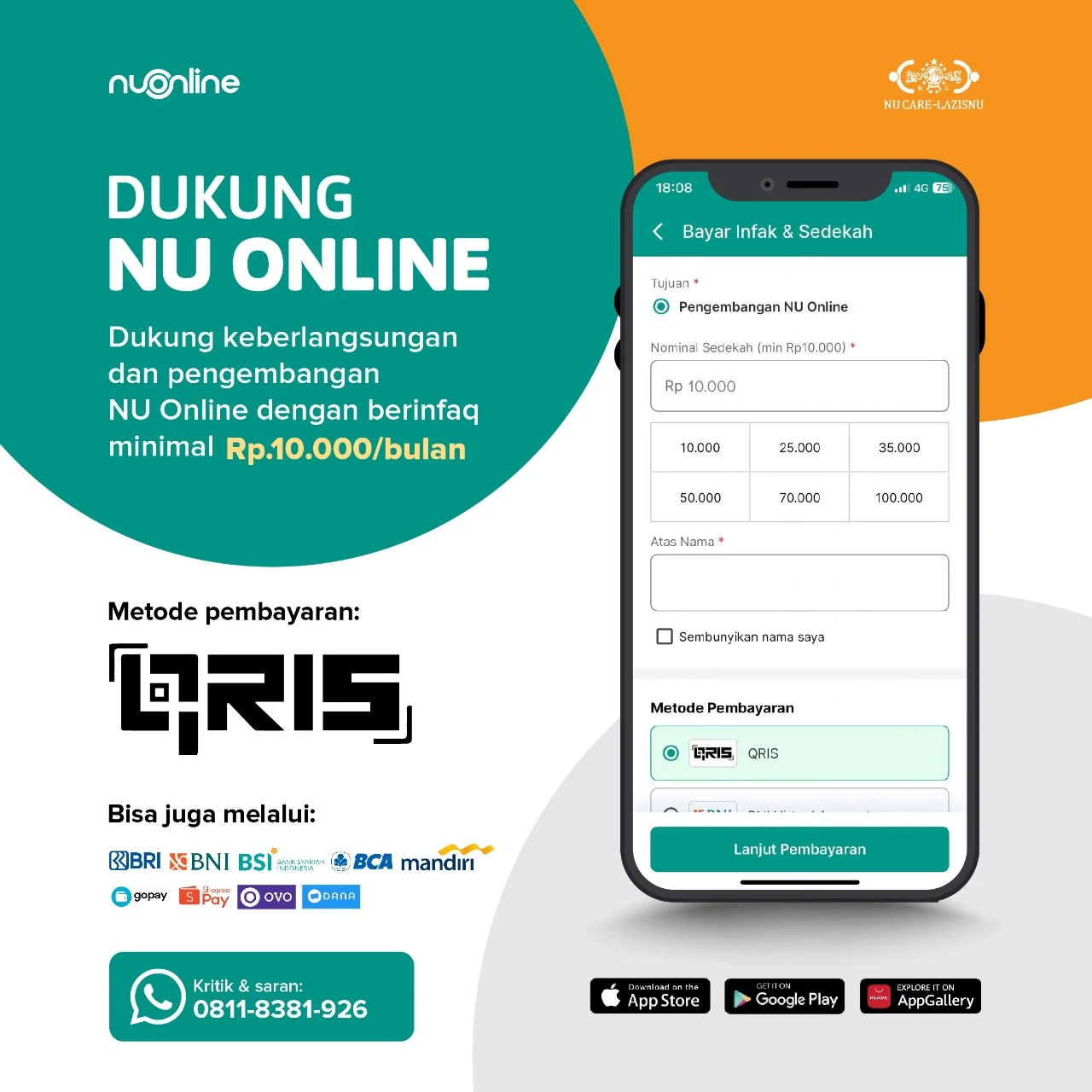Sketsa Pemikiran Ekonomi NU Dan NU Ekonomi ( Bagian Pertama)
Rabu, 4 Februari 2015 | 13:40 WIB
 Oleh :Titut Sudiono, S.Ag.,M.E.Sy
Wakil Ketua PW. LKNU Provinsi Lampung
Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi ulama tradisionalis yang memiliki pengikut yang besar jumlahnya, organisasi non-pemerintah paling besar yang masih bertahan dan mengakar dikalangan bawah. Bertahannya NU sejatinya sangat ditentukan oleh kemampuan pengikutnya dalam melestarikan ideologi yang dianut dan tingkat penerimaan masyarakat bawah yang masih kuat.
Nahdlatul Ulama tidak lahir langsung jadi, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Beberapa organisasi embrio terlebih dahulu lahir, seperti Nahdlatul Wathan, Nahdlatut Tujjar, dan Tashwirul Afkar. Orientasi ulama dalam gerak pendidikan, politik, dan ekonomi yang dibangun para ulama menjelang kelahiran NU ini telah menjadi bukti bahwa ada yang dipikirkan ulama begitu komplit. Tidak sekedar persoalan agama yang hendak dibangun oleh para ulama, tapi juga pendidikan, politik, dan ekonomi.
Sayangnya, persoalan ekonomi yang juga menjadi cikal bakal kelahiran Nahdlatul Ulama, justru dalam gerak perkembangan NU sering kali terabaikan. Ekonomi menjadi wilayah garapan yang tidak begitu dihiraukan oleh NU. Tak heran jika sejak berdirinya hingga sekarang keberhasilan NU dalam membangun sistem ekonomi tidak begitu tampak. Bahkan NU justru “terperosok” oleh godaan politik yang sangat menggiurkan dan melupakan pemberdayaan ekonomi jama’ah. Padahal konstituen NU yang terbesar adalah petani, nelayan, dan buruh, yang seringkali menjadi “korban” penindasan dari sistem ekonomi.
Perihal ini dapat dilihat pada era Presiden SBY sejak tahun 2004, dimana kehidupan ekonomi rakyat kecil benar-benar terpukul dengan sempat naiknya harga BBM hingga tiga kali akibat dampak krisis keuangan AS di akhir tahun 2008. Kemudian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang digulirkan pemerintah SBY bagaikan program sinterklas yang belum mampu merubah struktur ekonomi nasional yang timpang dengan sejumlah indikator; yaitu minusnya pertumbuhan pasar tradisional dan meledaknya angka pengangguran dan kemiskinan. Padahal para pedagang pasar tradisional dan masyarakat miskin adalah mayoritas warga NU yang hanya mengenyam pendidikan agama saja dan memilih untuk menjadi seorang wirausaha sebagai pedagang kulakan kecil di pasar tradisional.
Basis Sosiologi Warga NU
Sebelum kita membahas solusi bagaimana NU mampu berdaya mengentaskan warganya dari jeratan kemiskinan, maka kita perlu membedah basis sosiologi warga NU. Pertama, mayoritas warga NU tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian petani dan nelayan. Sebagian dari mereka bahkan hanya sebagai petani penggarap (peasant) yang tidak memiliki tanah atau lahan. Kaum nelayan di Indonesia juga merupakan kaum nelayan bermodal lemah dengan teknologi rendah sehingga tangkapan mereka masih jauh dari tangkapan ikan nelayan-nelayan asing berteknologi tinggi yang sering mencuri ikan di wilayah Indonesia.
Kedua, pola produksi ekonomi warga NU -yang notabene pertanian- masih berpola subsitensi alias berorientasi memenuhi kebutuhan hidup sendiri belum berorientasi pada pasar. Ketiga, walaupun dibeberapa kota berbasis warga NU seperti di Lampung sudah tumbuh kelas menengah pengusaha yang cukup kuat, tetapi mereka masih berkutat pada sektor informal seperti pengrajin dan pedagang kulakan. Jarang ditemui pengusaha berlatar belakang Nahdliyyin yang berkiprah disektor formal yang padat modal seperti industri IT,telekomunikasi, otomotif dan elektronik.
Keempat, tanpa disadari dan perlu diakui bahwa warga NU adalah lulusan pesantren dan IAIN/STAIN yang relatif belum mempunyai kapabilitas “link and Match” dengan kebutuhan teknokratis dan sektor industri modern. Bahkan tingginya kebutuhan tenaga ahli keuangan syariah akibat “meledaknya” sektor industri perbankan syariah belum secara maksimal dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendidikan NU salah satu contohnya.
Sketsa pemikiran ekonomi sebagai basis gerakan
Pada awal abad ke-19 adalah fase awal pembentukan cita-cita menuju manifestasi republik ini. Pergolakan pemikiran dan gagasan mengenai pembentukan arah pembangunan negara sesungguhnya sudah dimulai dengan munculnya pendirian Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1911 yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI) tahun 1912 yang seiring dengan pendirian Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan di tahun yang sama, kemudian berlanjut dengan munculnya komunitas nasionalisme para pemuda dari daerah Jawa, Sumatera, yang mengatasnamakan Jong Java, Jong Sumatera dan lainnya. Selain itu pula muncul organisasi yang diinisiasi oleh para ulama diwilayah Surabaya Jawa Timur di tahun 1918 yakni Nahdlatut Tujjar sebagai simbol gerakan ekonomi perdesaan saat itu. Kemudian disusul dengan munculnya organisasi Tashwirul Afkar di tahun 1922 sebagai manifestasi dari gerakan keilmuan dan kebudayaan di kalangan jama’ah Nahdliyyah serta munculnya organisasi Nahdlatul Wathan yang dipelopori oleh KH. A. Wahab Chasbullah sebagai gerakan politik yang berorientasi kebangsaan.
Ini menunjukkan bahwa sebenarnya aktifitas ekonomi itu sudah berkembang sedemikian rupa dikalangan masyarakat kaum santri saat itu, bahkan tidak hanya dalam sektor ekonomi pertanian, tetapi mulai merambah ke sektor bisnis. Para ulama yang terlebih dulu mendirikan Nahdlatut Tujjar (gerakan kaum saudagar) bertempat tinggal diberbagai kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Kediri.
Perlu diketahui bahwa Surabaya saat itu merupakan kota yang tidak hanya terbesar di Indonesia, tetapi terbesar di Asia. Waktu itu Tokyo belum apa-apa. Kyoto walaupun sudah maju, tetapi belum sebanding dengan Surabaya (selain kota Bandar, juga kota niaga dan industri serta kota minyak). Perlu diingat penerapan mesin uap yang merupakan tanda dari revolusi industri itu pertama kali dilakukan di Surabaya.
Kenyataan ini bisa menjelaskan bahwa dinamika ekonomi kota ini sangat pesat, di mana kaum santri yang ada di kawasan kota niaga dan industri telah terlibat dalam aktifitas dagang yang sama. Daerah Pabean Ngampel sebagai pusat perdagangan di Surabaya saat itu dikuasai oleh kaum santri baik dari kalangan Arab maupun pribumi. Para kiai pesantren seperti KH. A. Wahab Chasbullah, KH. Ridwan Abdullah, KH. A. Hasyim Asy’ari sendiri memiliki hubungan erat dengan para pelaku ekonomi, baik dari kalangan pribumi, Arab maupun Cina di pusat perdagangan itu. KH. A. Hasyim Asy’ari sendiri selain berdagang ternak di pasar hewan Tunggorono, beliau juga berdagang minyak nilam, serta kain. Demikian juga dengan KH. A. Wahid Hasyim juga menekuni usaha bisnis di bidang tekstile.
Pada umumnya para pengurus NU memiliki perusahaan, baik atas nama lembaga atau pribadi yang mendapatkan kredit dari Bank Indonesia (BI). Ini menunjukkan bahwa perusahaan mereka cukup “bonafide”, seperti halnya KH. A.Wahab Chasbullah memiliki perusahaan dalam bentuk CV. Karoenia. Yang bergerak dibidang berbagai jenis usaha, seperti import sepeda, distribusi beras dan usaha pelayaran. Setelah Indonesia merdeka, para tokoh NU telah menguasai berbagai bidang bisnis. KH. Achmad Syaikhu misalnya seorang pengusaha sepatu terbesar di Surabaya, dan bisnis yang dikembangkan ini tentunya melibatkan para importir dan eksportir besar, selain itu juga tetap melibatkan banyak kaum santri tentunya, baik sebagai distributor atau suplayer, sehingga semuanya mampu menopang gerakan dakwah dari jaringan keulamaan saat itu.
Dengan demikian, jaringan tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menghadapi monopoli kolonial Belanda. Ketika Nahdlatut Tujjar (gerakan kaum saudagar) akan bergabung atau dilebur kedalam jam’iyah Nahdlatul ‘Ulama bukan berarti naluri dan intuisi berdagang dan berbisnis para ulama surut. Mereka justru harus lebih bekerja keras lagi karena organisasi membutuhkan banyak biaya untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk turun ke daerah yang kesemuanya harus dibiayai sendiri. Tradisi ini diturunkan langsung ke Pengurus NU di tingkat ranting paling bawah, sehingga tradisi berniaga di lingkungan kaum santri juga terus mengalami perkembangan yang cukup pesat saat itu.
Dalam kondisi seperti itu, maka yang perlu dirumuskan oleh para ulama saat itu, bukan bagaimana menumbuhkan kewiraswastaan di kalangan kaum santri, atau manajemen perusahaan yang harus buat mereka. Dan bukan karena di tengah tekanan Belanda, mereka tidak bisa masuk sektor birokrasi, baik karena alasan etis atau teknis. Belanda hanya memilih partner dagang mereka dari kelompok Eropa sendiri, selebihnya diberikan kepada mitra asing mereka atau yang sering disebut dengan istilah warga Timur Asing, yang terdiri dari orang Arab, Cina, India dan Jepang. Pilihan yang tepat bagi kaum santri adalah usaha sendiri sebagai pedagang atau petani. Maka yang mendesak untuk dirumuskan adalah etika atau moral bisnis, sebagai pedoman bagi para pelaku usaha di lingkungan NU dan umat Islam pada umumnya, sebab mereka saling melakukan kerjasama dalam berniaga yang diharapkan tidak saling merugikan, dapat dipercaya serta saling menguntungkan.
Kerjasama dalam bidang berniaga ini diwujudkan dalam bentuk pendirian badan-badan usaha untuk memajukan bidang pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh syariat Islam.(Bersambung)
Oleh :Titut Sudiono, S.Ag.,M.E.Sy
Wakil Ketua PW. LKNU Provinsi Lampung
Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi ulama tradisionalis yang memiliki pengikut yang besar jumlahnya, organisasi non-pemerintah paling besar yang masih bertahan dan mengakar dikalangan bawah. Bertahannya NU sejatinya sangat ditentukan oleh kemampuan pengikutnya dalam melestarikan ideologi yang dianut dan tingkat penerimaan masyarakat bawah yang masih kuat.
Nahdlatul Ulama tidak lahir langsung jadi, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Beberapa organisasi embrio terlebih dahulu lahir, seperti Nahdlatul Wathan, Nahdlatut Tujjar, dan Tashwirul Afkar. Orientasi ulama dalam gerak pendidikan, politik, dan ekonomi yang dibangun para ulama menjelang kelahiran NU ini telah menjadi bukti bahwa ada yang dipikirkan ulama begitu komplit. Tidak sekedar persoalan agama yang hendak dibangun oleh para ulama, tapi juga pendidikan, politik, dan ekonomi.
Sayangnya, persoalan ekonomi yang juga menjadi cikal bakal kelahiran Nahdlatul Ulama, justru dalam gerak perkembangan NU sering kali terabaikan. Ekonomi menjadi wilayah garapan yang tidak begitu dihiraukan oleh NU. Tak heran jika sejak berdirinya hingga sekarang keberhasilan NU dalam membangun sistem ekonomi tidak begitu tampak. Bahkan NU justru “terperosok” oleh godaan politik yang sangat menggiurkan dan melupakan pemberdayaan ekonomi jama’ah. Padahal konstituen NU yang terbesar adalah petani, nelayan, dan buruh, yang seringkali menjadi “korban” penindasan dari sistem ekonomi.
Perihal ini dapat dilihat pada era Presiden SBY sejak tahun 2004, dimana kehidupan ekonomi rakyat kecil benar-benar terpukul dengan sempat naiknya harga BBM hingga tiga kali akibat dampak krisis keuangan AS di akhir tahun 2008. Kemudian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang digulirkan pemerintah SBY bagaikan program sinterklas yang belum mampu merubah struktur ekonomi nasional yang timpang dengan sejumlah indikator; yaitu minusnya pertumbuhan pasar tradisional dan meledaknya angka pengangguran dan kemiskinan. Padahal para pedagang pasar tradisional dan masyarakat miskin adalah mayoritas warga NU yang hanya mengenyam pendidikan agama saja dan memilih untuk menjadi seorang wirausaha sebagai pedagang kulakan kecil di pasar tradisional.
Basis Sosiologi Warga NU
Sebelum kita membahas solusi bagaimana NU mampu berdaya mengentaskan warganya dari jeratan kemiskinan, maka kita perlu membedah basis sosiologi warga NU. Pertama, mayoritas warga NU tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian petani dan nelayan. Sebagian dari mereka bahkan hanya sebagai petani penggarap (peasant) yang tidak memiliki tanah atau lahan. Kaum nelayan di Indonesia juga merupakan kaum nelayan bermodal lemah dengan teknologi rendah sehingga tangkapan mereka masih jauh dari tangkapan ikan nelayan-nelayan asing berteknologi tinggi yang sering mencuri ikan di wilayah Indonesia.
Kedua, pola produksi ekonomi warga NU -yang notabene pertanian- masih berpola subsitensi alias berorientasi memenuhi kebutuhan hidup sendiri belum berorientasi pada pasar. Ketiga, walaupun dibeberapa kota berbasis warga NU seperti di Lampung sudah tumbuh kelas menengah pengusaha yang cukup kuat, tetapi mereka masih berkutat pada sektor informal seperti pengrajin dan pedagang kulakan. Jarang ditemui pengusaha berlatar belakang Nahdliyyin yang berkiprah disektor formal yang padat modal seperti industri IT,telekomunikasi, otomotif dan elektronik.
Keempat, tanpa disadari dan perlu diakui bahwa warga NU adalah lulusan pesantren dan IAIN/STAIN yang relatif belum mempunyai kapabilitas “link and Match” dengan kebutuhan teknokratis dan sektor industri modern. Bahkan tingginya kebutuhan tenaga ahli keuangan syariah akibat “meledaknya” sektor industri perbankan syariah belum secara maksimal dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendidikan NU salah satu contohnya.
Sketsa pemikiran ekonomi sebagai basis gerakan
Pada awal abad ke-19 adalah fase awal pembentukan cita-cita menuju manifestasi republik ini. Pergolakan pemikiran dan gagasan mengenai pembentukan arah pembangunan negara sesungguhnya sudah dimulai dengan munculnya pendirian Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1911 yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI) tahun 1912 yang seiring dengan pendirian Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan di tahun yang sama, kemudian berlanjut dengan munculnya komunitas nasionalisme para pemuda dari daerah Jawa, Sumatera, yang mengatasnamakan Jong Java, Jong Sumatera dan lainnya. Selain itu pula muncul organisasi yang diinisiasi oleh para ulama diwilayah Surabaya Jawa Timur di tahun 1918 yakni Nahdlatut Tujjar sebagai simbol gerakan ekonomi perdesaan saat itu. Kemudian disusul dengan munculnya organisasi Tashwirul Afkar di tahun 1922 sebagai manifestasi dari gerakan keilmuan dan kebudayaan di kalangan jama’ah Nahdliyyah serta munculnya organisasi Nahdlatul Wathan yang dipelopori oleh KH. A. Wahab Chasbullah sebagai gerakan politik yang berorientasi kebangsaan.
Ini menunjukkan bahwa sebenarnya aktifitas ekonomi itu sudah berkembang sedemikian rupa dikalangan masyarakat kaum santri saat itu, bahkan tidak hanya dalam sektor ekonomi pertanian, tetapi mulai merambah ke sektor bisnis. Para ulama yang terlebih dulu mendirikan Nahdlatut Tujjar (gerakan kaum saudagar) bertempat tinggal diberbagai kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Kediri.
Perlu diketahui bahwa Surabaya saat itu merupakan kota yang tidak hanya terbesar di Indonesia, tetapi terbesar di Asia. Waktu itu Tokyo belum apa-apa. Kyoto walaupun sudah maju, tetapi belum sebanding dengan Surabaya (selain kota Bandar, juga kota niaga dan industri serta kota minyak). Perlu diingat penerapan mesin uap yang merupakan tanda dari revolusi industri itu pertama kali dilakukan di Surabaya.
Kenyataan ini bisa menjelaskan bahwa dinamika ekonomi kota ini sangat pesat, di mana kaum santri yang ada di kawasan kota niaga dan industri telah terlibat dalam aktifitas dagang yang sama. Daerah Pabean Ngampel sebagai pusat perdagangan di Surabaya saat itu dikuasai oleh kaum santri baik dari kalangan Arab maupun pribumi. Para kiai pesantren seperti KH. A. Wahab Chasbullah, KH. Ridwan Abdullah, KH. A. Hasyim Asy’ari sendiri memiliki hubungan erat dengan para pelaku ekonomi, baik dari kalangan pribumi, Arab maupun Cina di pusat perdagangan itu. KH. A. Hasyim Asy’ari sendiri selain berdagang ternak di pasar hewan Tunggorono, beliau juga berdagang minyak nilam, serta kain. Demikian juga dengan KH. A. Wahid Hasyim juga menekuni usaha bisnis di bidang tekstile.
Pada umumnya para pengurus NU memiliki perusahaan, baik atas nama lembaga atau pribadi yang mendapatkan kredit dari Bank Indonesia (BI). Ini menunjukkan bahwa perusahaan mereka cukup “bonafide”, seperti halnya KH. A.Wahab Chasbullah memiliki perusahaan dalam bentuk CV. Karoenia. Yang bergerak dibidang berbagai jenis usaha, seperti import sepeda, distribusi beras dan usaha pelayaran. Setelah Indonesia merdeka, para tokoh NU telah menguasai berbagai bidang bisnis. KH. Achmad Syaikhu misalnya seorang pengusaha sepatu terbesar di Surabaya, dan bisnis yang dikembangkan ini tentunya melibatkan para importir dan eksportir besar, selain itu juga tetap melibatkan banyak kaum santri tentunya, baik sebagai distributor atau suplayer, sehingga semuanya mampu menopang gerakan dakwah dari jaringan keulamaan saat itu.
Dengan demikian, jaringan tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menghadapi monopoli kolonial Belanda. Ketika Nahdlatut Tujjar (gerakan kaum saudagar) akan bergabung atau dilebur kedalam jam’iyah Nahdlatul ‘Ulama bukan berarti naluri dan intuisi berdagang dan berbisnis para ulama surut. Mereka justru harus lebih bekerja keras lagi karena organisasi membutuhkan banyak biaya untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk turun ke daerah yang kesemuanya harus dibiayai sendiri. Tradisi ini diturunkan langsung ke Pengurus NU di tingkat ranting paling bawah, sehingga tradisi berniaga di lingkungan kaum santri juga terus mengalami perkembangan yang cukup pesat saat itu.
Dalam kondisi seperti itu, maka yang perlu dirumuskan oleh para ulama saat itu, bukan bagaimana menumbuhkan kewiraswastaan di kalangan kaum santri, atau manajemen perusahaan yang harus buat mereka. Dan bukan karena di tengah tekanan Belanda, mereka tidak bisa masuk sektor birokrasi, baik karena alasan etis atau teknis. Belanda hanya memilih partner dagang mereka dari kelompok Eropa sendiri, selebihnya diberikan kepada mitra asing mereka atau yang sering disebut dengan istilah warga Timur Asing, yang terdiri dari orang Arab, Cina, India dan Jepang. Pilihan yang tepat bagi kaum santri adalah usaha sendiri sebagai pedagang atau petani. Maka yang mendesak untuk dirumuskan adalah etika atau moral bisnis, sebagai pedoman bagi para pelaku usaha di lingkungan NU dan umat Islam pada umumnya, sebab mereka saling melakukan kerjasama dalam berniaga yang diharapkan tidak saling merugikan, dapat dipercaya serta saling menguntungkan.
Kerjasama dalam bidang berniaga ini diwujudkan dalam bentuk pendirian badan-badan usaha untuk memajukan bidang pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh syariat Islam.(Bersambung)
Terpopuler
1
Pelantikan IPNU-IPPNU, Ketua NU Pringsewu: Pelajar NU Harus Pinter, Seger, dan Bener
2
Langitkan Doa di Awal Tahun Pelajaran Baru 2025, MAN 1 Pringsewu Gelar Istighotsah
3
Mahasiswa KKN UIN Raden Intan Lakukan Konservasi Air Melalui Pembuatan Lubang Resapan Biopori
4
Ngaji Tafsir Online: Sebab Diharamkannya Riba dan Ancaman bagi Pelakunya
5
Rektor UIN Raden Intan Kukuhkan 298 Guru Profesional PPG Pendidikan Agama Islam
6
Dinas Kominfotik dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Sosial kepada Keluarga Almarhum PTHL
Terkini
Lihat Semua