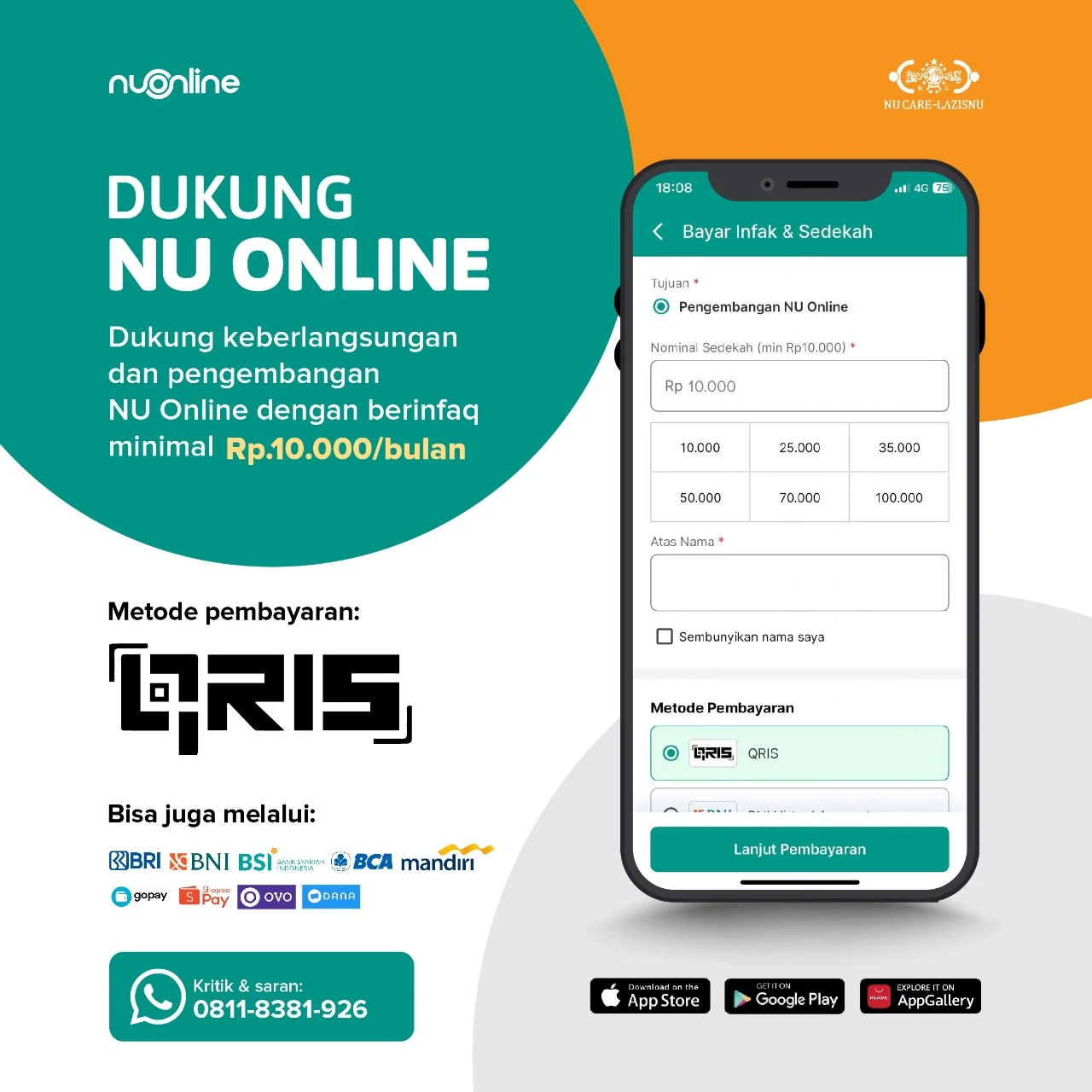Oleh: Rudy Irawan (Wakil Ketua PCNU Bandar Lampung/Dosen UIN Raden Intan Lampung)
pasca pendaftaran pasangan calon gubernur-wakil gubernur, calon bupati-wakil bupati, calon walikota-wakil walikota, menyeruak lagi ke permukaan istilah mahar politik. Tampaknya bangsa kita ini memiliki “budaya eufimisme” atau yang semula disebut “penghalusan bahasa” agar tidak vulgar, yang secara substansial sesungguhnya bertentangan dengan nilai agama, kepatutan, dan hukum menjadi “seolah-olah” patut dan lumrah. Banyak contoh bisa dikemukakan di sini, seperti kenaikan harga menjadi penyesuaian, seseorang ditangkap atau ditahan oleh aparat penegak hukum disebut diamankan, penjara disebut lembaga pemasyarakatan, pembantu menjadi asisten rumah tangga, juga termasuk mahar politik.
Kata “mahar” yang asalnya adalah “pemberian seorang calon suami kepada calon isteri, diberikan sebelum akad nikah sebagai tanda ikatan pernikahan, berdasarkan cinta dan kasih sayang, untuk membentuk keluarga yang sakinah, dan mewujudkan kebahagiaan dan berketurunan, berdasarkan agama masing-masing”. Dalam Islam, pernikahan harus menyebut kalimat Allah, karena mahar ini diberikan berkaitan dengan peristiwa yang sakral. Anehnya, kata “mahar” ini nasibnya, mudah-mudahan saya tidak keliru, digunakan sebagai “pemberian sejumlah tertentu” sebagai biaya politik, dari para calon kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi dari dewan pimpinan pusat partai politik. Bahasa “kasar” atau “vulgar”-nya bisa difahami money politik, sogok, suap, yang dalam bahasa agama disebut risywah, meskipun tentu saja kesimpulan demikian, bisa dibantah oleh para pejabat parpol.
Muncul dan ramainya “mahar politik” ini sebenarnya sudah lama, terutama di setiap ada hajatan “demokrasi” dari pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah, karena boleh jadi sebuah partai politik itu membutuhkan biaya yang sangat mahal, apalagi di dalam upaya memenangi sebuah even dan kontestasi politik calon kepala daerah, yang diharapkan menjadi “pundi-pundi” pendanaan parpol. Yang menarik adalah, istilah “mahar” mencuat karena ada seseorang yang “mencalonkan” diri menjadi cagub Jawa Timur, yang karena gagal diusung oleh parpol tertentu, tidak kuat menahan diri, akhirnya bicara ke media. Sudah pasti dibantah oleh pimpinan parpol yang merasa “dicemarkan” karena dianggap meminta “mahar” atau “setoran” puluhan milyar.
Ongkos politik dan kekuasaan di negeri kita ini tampaknya memang sangat mahal. Karena dapat dipastikan, setelah “mahar politik” akan diteruskan dengan biasa saksi di TPS, bahan bakar saat kampanye, cetak gambar, cetak kaos, cetak spanduk atau backdrop, belum dana “pembinaan” konstituen dan dana “komunikasi” antara koordinator atau bahasa Jawanya “sabet” di masing-masing tingkatan.
Setelah biaya-biaya itu semua, ketika calon sukses memenangi kontestasi pileg atau pilkada, maka giliran berikutnya adalah “walimah” atau “pesta” politik. Apakah setelah pesta politik itu berakhir, sudah selesai. Tampaknya, belum juga. Karena seperti halnya, keluarga, seorang kepala daerah juga seperti kepala keluarga. Pemimpin tentu harus dan wajib “menafkahi” parpol pengusung dan sudah pasti konstituennya. Jika kepentingan masyarakat umum diatur secara legal dan sah melalui refulasi atau undang-undang, maka nafkah politik ini, kira-kira yang bisa menjawab tentu para politisi.
Tampaknya, cerita relasi, saudara, teman, dan handai taulan yang menjadi politisi, memang ada “kewajiban” berinfak, sedekah, dan biaya lain, yang diambil dari sebagian penghasilan para politisi tersebut. Bedanya jika mahar itu di depan, yang secara hukum tentu bisa menimbulkan pertanyaan, namun jika infaq dan sedekah dari penghasilan ini, tampaknya dari aspek fiqh atau hukumnya diperbolehkan. Lebih dari itu juga sebagai “loyalitas dan komitmen” politisi yang bersangkutan terhadap partainya sebagai wadah atau instrumen politik untuk “mendapatkan” kekuasaan atau jabatan politik. Lalu bagaimana korelasi antara “mahar, walimah, dan nafkah politik” terhadap kinerja kepala daerah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu tidak mudah.
Secara obyektif, parameter mengukur kinerja seorang kepala daerah tentu didasarkan pada program dan rambu-rambu yang ditetapkan sebelumnya. Dari sisi parameter ini tentu tidak ada persoalan. Hanya saja, kata para ahli ekonomi, jika “mahar, walimah, dan nafkah politik” ini dianggap suatu “keharusan dan investasi politik” maka rumus yang berlaku adalah setidaknya, pertama, butuh kembali modal atau break event point. Kedua, ketika budgeting anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah sangat detail dan strik, tentu agak susah untuk memanfaatkan celah-celah untuk memanfaatkan “peluang” untuk menyiasati dan “menyalahgunakannya”.
Apakah akan “memanfaatkan” model “rolling” pejabat sebagai “pundi-pundi” untuk mendapatkan kompensasi politik dan bentuk “nafkah politik”, jika belajar dari pengalaman beberapa kepala daerah yang “terrsandung” operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tampaknya modus operandi demikian, masih menjadi “cara” efektif. Ujung-ujungnya pejabat yang diangkat dengan model tersebut, akan juga melakukan upaya yang sama untuk mengembalikan “modal” yang sudah dikeluarkan demi posisi yang didudukinya. Karena menyangkut juga soal “nasib kepala daerah” yang terkena OTT, padahal sesungguhnya yang lain tidak beda, atau karena soal mainnya “rapi atau tidak”. Ini mengingatkan saya pada kata bijak bestari: الحق بلا نظام يغلبه الباطل بنظام artinya “kebenaran yang tidak domanaj secara tertib, akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanaj secara tertib”.
Sebagai salah seorang warga berharap, pengalaman yang sudah terjadi dijadikan guru yang terbaik, agar tidak mengulang lagi. Meskipun dalam kalkulasi politik ekonomi, akan sangat sulit dilaksanakan. Semoga saya salah menduga dan tidak benar adanya. Soal “mahar, walimah, dan nafkah politik” sudah saatnya diakhiri atau setidaknya diminimalisir. Kita berharap KPK yang semula dianggap sebagai lembaga extra ordinary body, ternyata tidak atau belum mampu menghilangkan korupsi di negeri kita tercinta ini. Bahkan kecenderungannya, makin hari makin menjadi-jadi dan nggegirisi. Menjadi kepala daerah juga termasuk umara’, yang menurut Rasulullah saw, memiliki posisi yang sangat strategis, untuk membawa suatu daerah. Jika pemimpinya baik, maka warga akan baik, tetapi sebaliknya jika ternyata seorang kepada daerah terbukti korup atau merusak, maka warganya yang akan menanggung.
Mengakhiri renungan ini, mari kita simak seksama, sabda Rasulullah SAW:
صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس ، الأمراء والعلماء رواه ابو نعيم في الحلية
“Dua kelompok umatku apabila mereka baik, maka manusia (umatnya) juga baik, yakni : umara’ (pejabat negara dan atau pemerintahan) dan ulama” (Riwayat Abu Naim di dalam al-Hulyah).
Semoga kepaa daerah yang akan terpilih dalam pilkada nanti, dapat memposisikan diri ya sebagai pejabat yang menjalankan amanat dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagaimana ungkapan fox populi fox dey artinya “suara rakyat adalah suara Tuhan” dapat menjadi teladan warganya, memimpin dengan adil, dan memakmurkan rakyat yang sudah memberikan amanatnya kepada Anda yang terpilih. Allah a’lam bi sh-shawab.